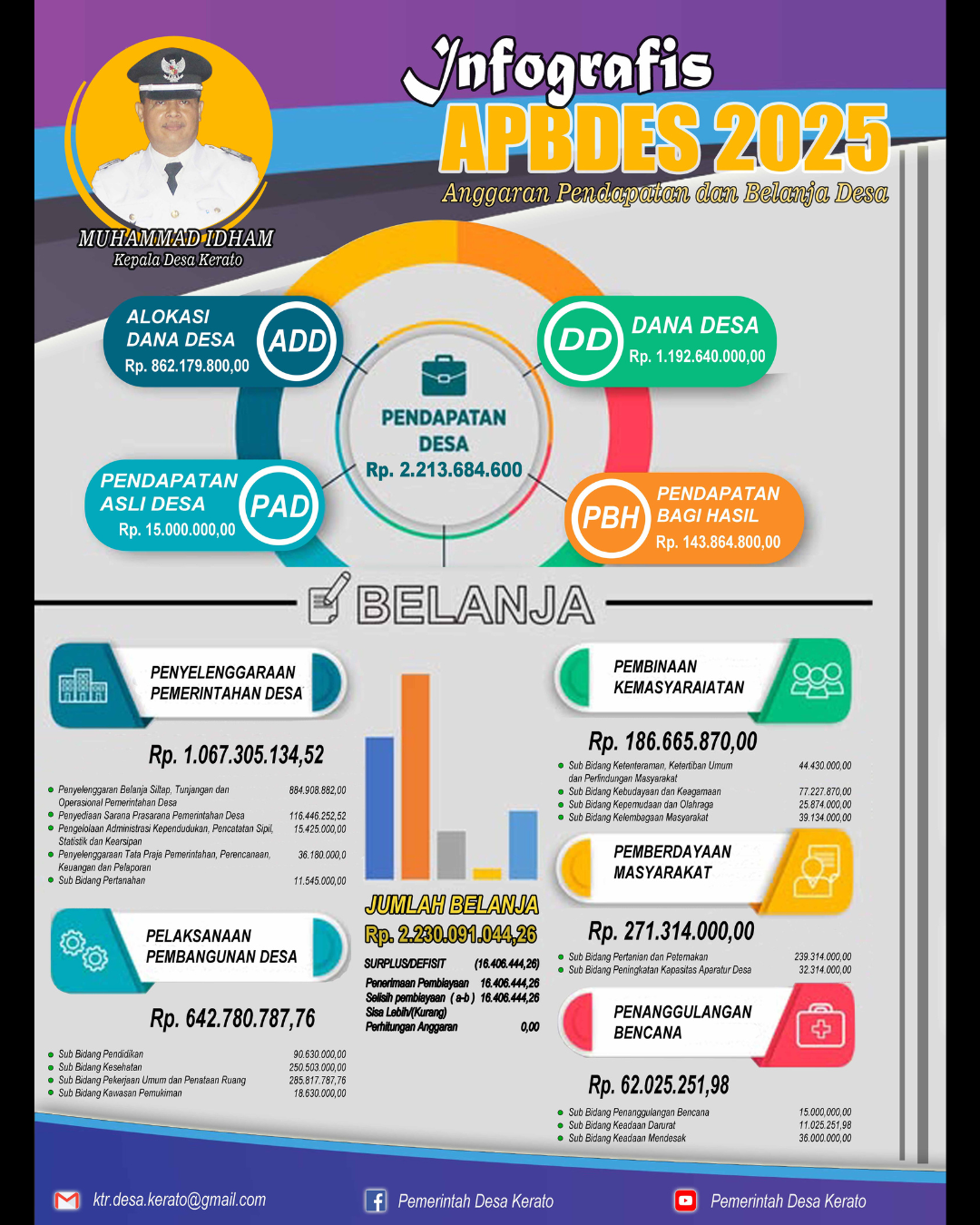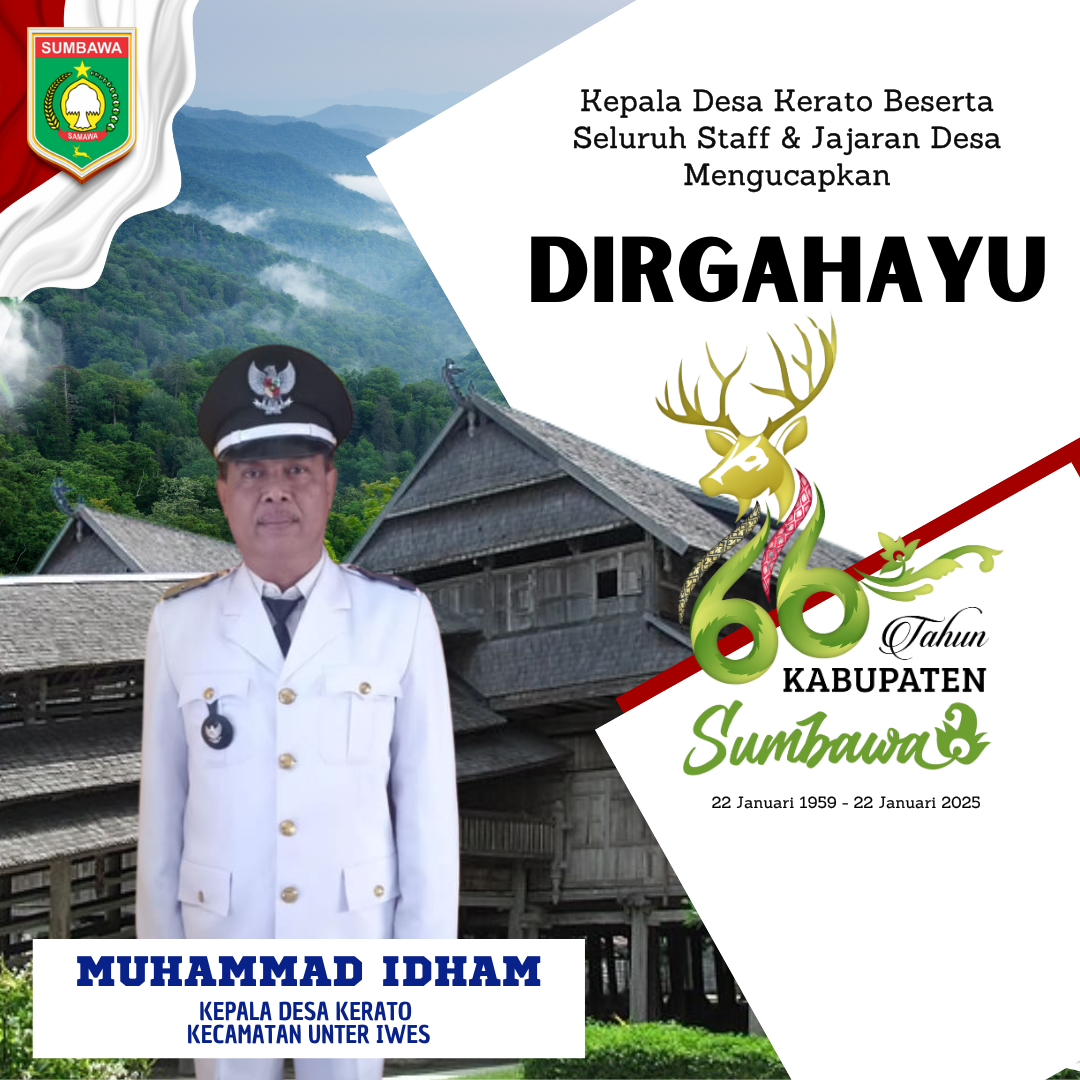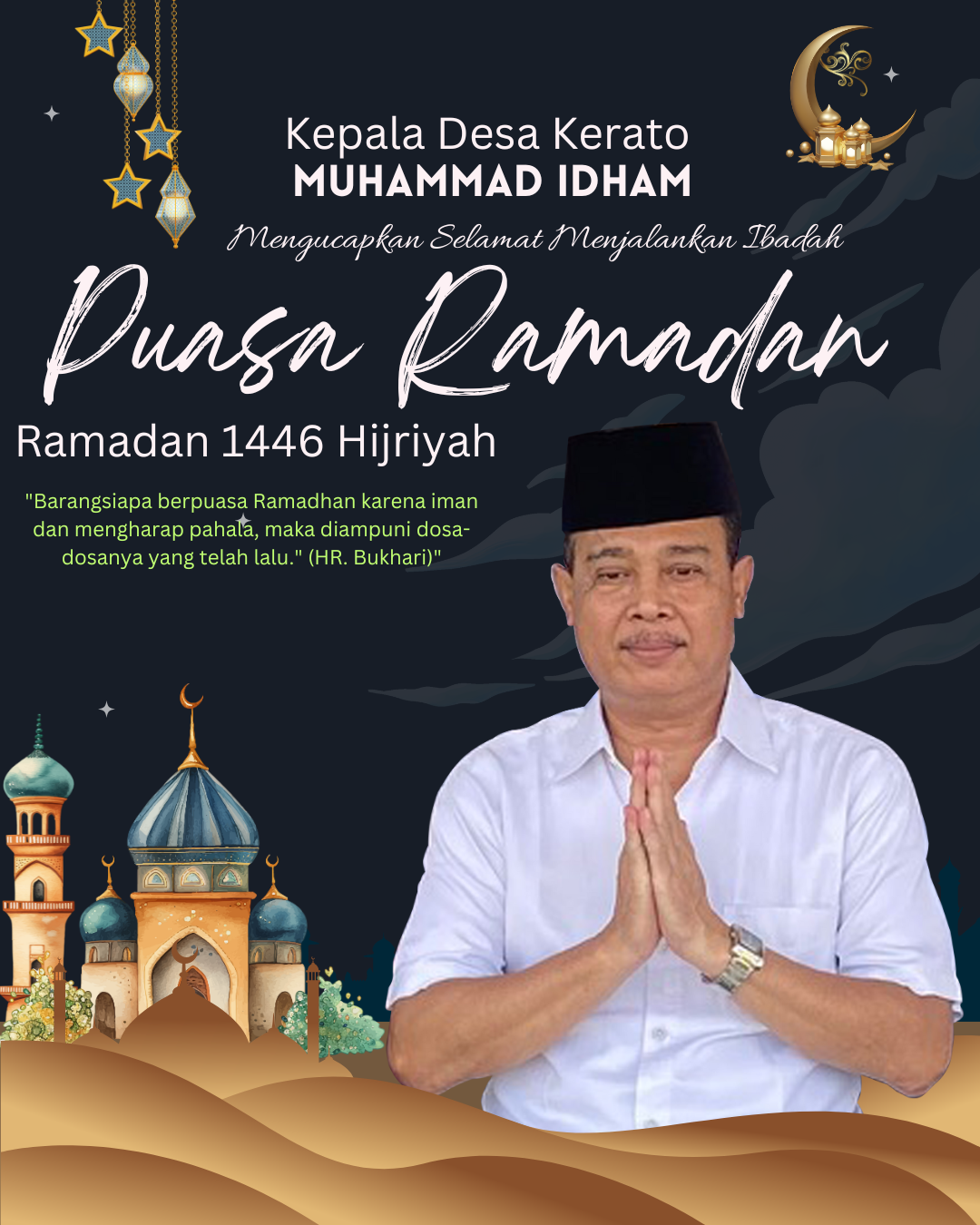Oleh: Fitrah Andiyan (Presiden Mahasiswa Universitas Samawa)
Kelangkaan LPG 3 kilogram di Kabupaten Sumbawa hari ini bukan lagi sekadar gangguan distribusi. Ia telah berubah menjadi indikator rapuhnya tata kelola subsidi di tingkat daerah. Ketika masyarakat kecil harus mengantre berjam-jam, harga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), dan akses terhadap barang bersubsidi semakin sulit, maka persoalan ini tidak bisa lagi ditutupi dengan dalih teknis atau keterbatasan kuota. Yang sedang diuji adalah kapasitas pemerintah dalam menjaga mandat kesejahteraan rakyat.
Subsidi energi sejatinya merupakan instrumen keadilan sosial. Negara hadir untuk mengoreksi ketimpangan pasar agar kelompok ekonomi lemah tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar. LPG 3 kilogram adalah bagian dari kebijakan tersebut yang dijalankan melalui Pertamina sebagai operator distribusi nasional. Namun kebijakan yang tidak diawasi secara ketat justru menciptakan distorsi: subsidi melebar tanpa kontrol, sasaran tidak presisi, dan ruang spekulasi terbuka di tingkat distribusi.
Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah tidak bisa berlindung di balik alasan pengurangan kuota dari pusat. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk melakukan advokasi kebutuhan riil wilayahnya, menyusun basis data konsumsi yang akurat, serta memperkuat sistem pengawasan distribusi hingga ke tingkat pangkalan. Ketika keluhan masyarakat terus berulang tanpa solusi struktural, maka yang tampak adalah pola respons jangka pendek, bukan kepemimpinan strategis.
Pembentukan satuan tugas (satgas) dan forum koordinasi memang memberi kesan responsif. Namun ukuran keberhasilan kebijakan bukanlah jumlah rapat atau pernyataan resmi, melainkan stabilitas harga dan ketersediaan barang di lapangan. Jika masyarakat tetap menghadapi kelangkaan dan lonjakan harga, maka instrumen pengawasan tersebut belum bekerja secara efektif. Lebih jauh, ketika masyarakat didorong menjadi pengawas utama harga dan distribusi, terjadi pergeseran tanggung jawab dari negara kepada warga. Padahal, dalam prinsip pelayanan publik, negara adalah aktor utama yang wajib menjamin kepastian akses dan keadilan distribusi.
Aksi Aliansi BEM Kabupaten Sumbawa pada awal Februari 2026 harus dipahami sebagai ekspresi kontrol sosial dalam demokrasi. Legitimasi pemerintahan tidak hanya lahir dari proses elektoral, tetapi dari kemampuannya memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Ketika subsidi gagal tepat sasaran dan distribusi tidak stabil, legitimasi itu perlahan terkikis. Klaim koordinasi dan komunikasi tidak cukup; legitimasi dibangun oleh hasil konkret.
Lebih dalam lagi, persoalan LPG 3 kilogram mencerminkan problem struktural dalam pengendalian subsidi. Tanpa integrasi data kesejahteraan dan sistem distribusi yang transparan, subsidi rentan disalahgunakan dan dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. LPG 3 kilogram kini digunakan lintas kelas sosial tanpa mekanisme verifikasi yang jelas. Tanpa pembaruan data dan digitalisasi pengawasan, subsidi berubah menjadi komoditas bebas yang mudah dimanipulasi.
Situasi ini menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan daerah. Kepemimpinan tidak diukur dari retorika pembangunan, tetapi dari keberanian mengambil langkah korektif: audit distribusi secara menyeluruh, penindakan tegas terhadap pelanggaran HET, evaluasi kuota berbasis kebutuhan riil daerah, serta transparansi data kepada publik. Tanpa itu, krisis LPG berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan.
Pada akhirnya, persoalan LPG 3 kilogram di Sumbawa bukan sekadar tentang energi rumah tangga. Ia adalah cermin tentang sejauh mana negara benar-benar hadir untuk rakyat kecil. Ketika dapur masyarakat terancam padam, yang ikut terancam bukan hanya stabilitas harga, tetapi legitimasi kekuasaan itu sendiri.