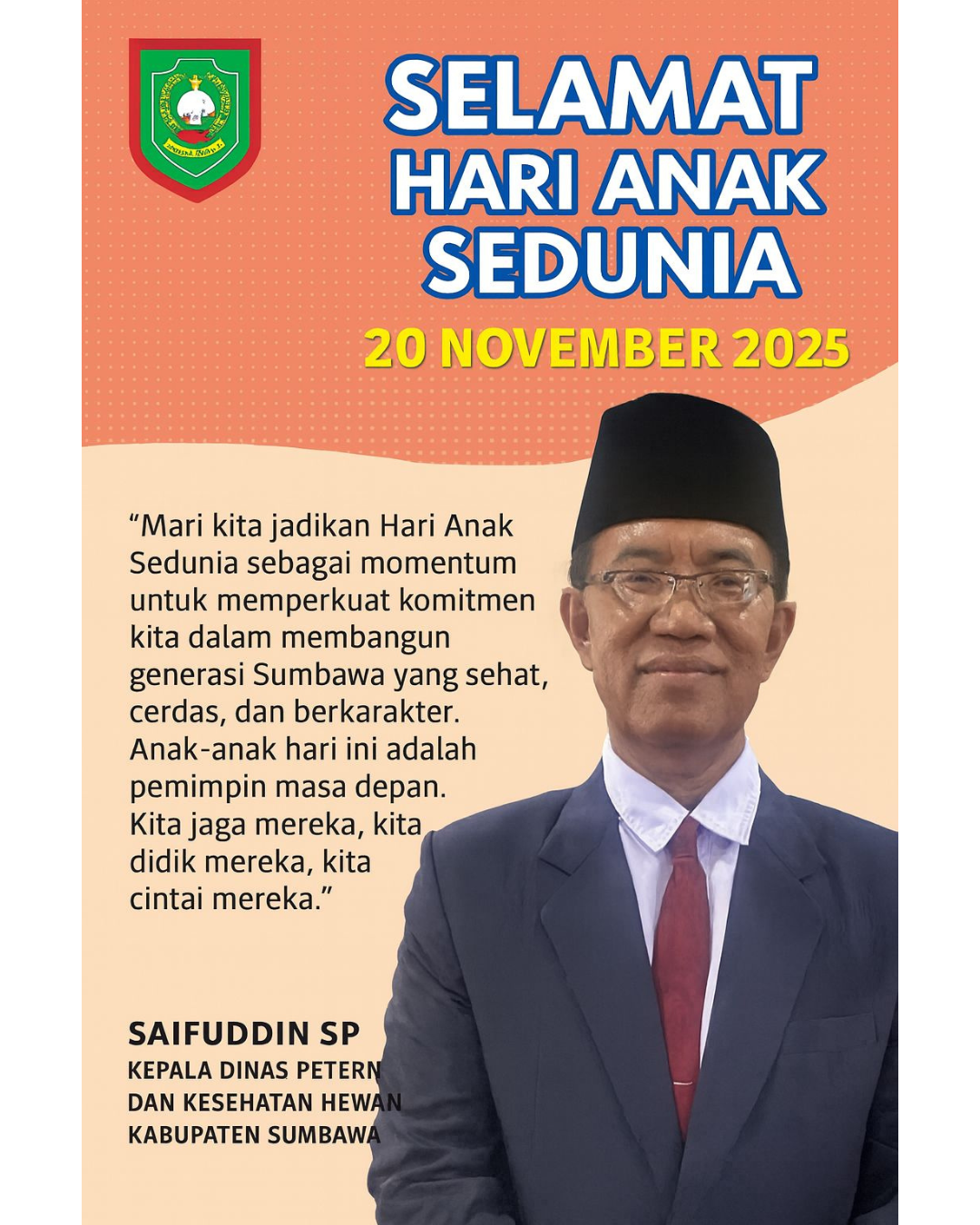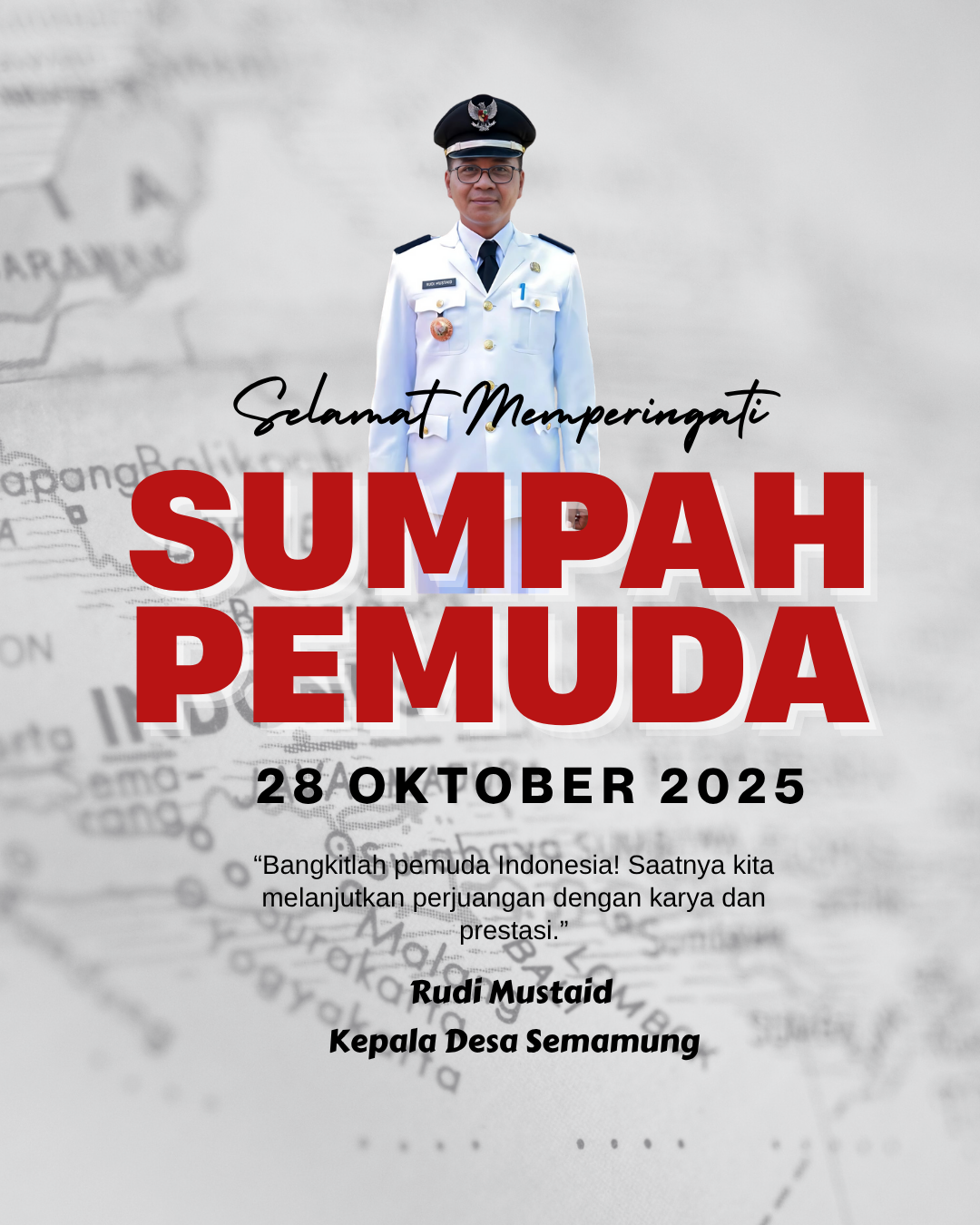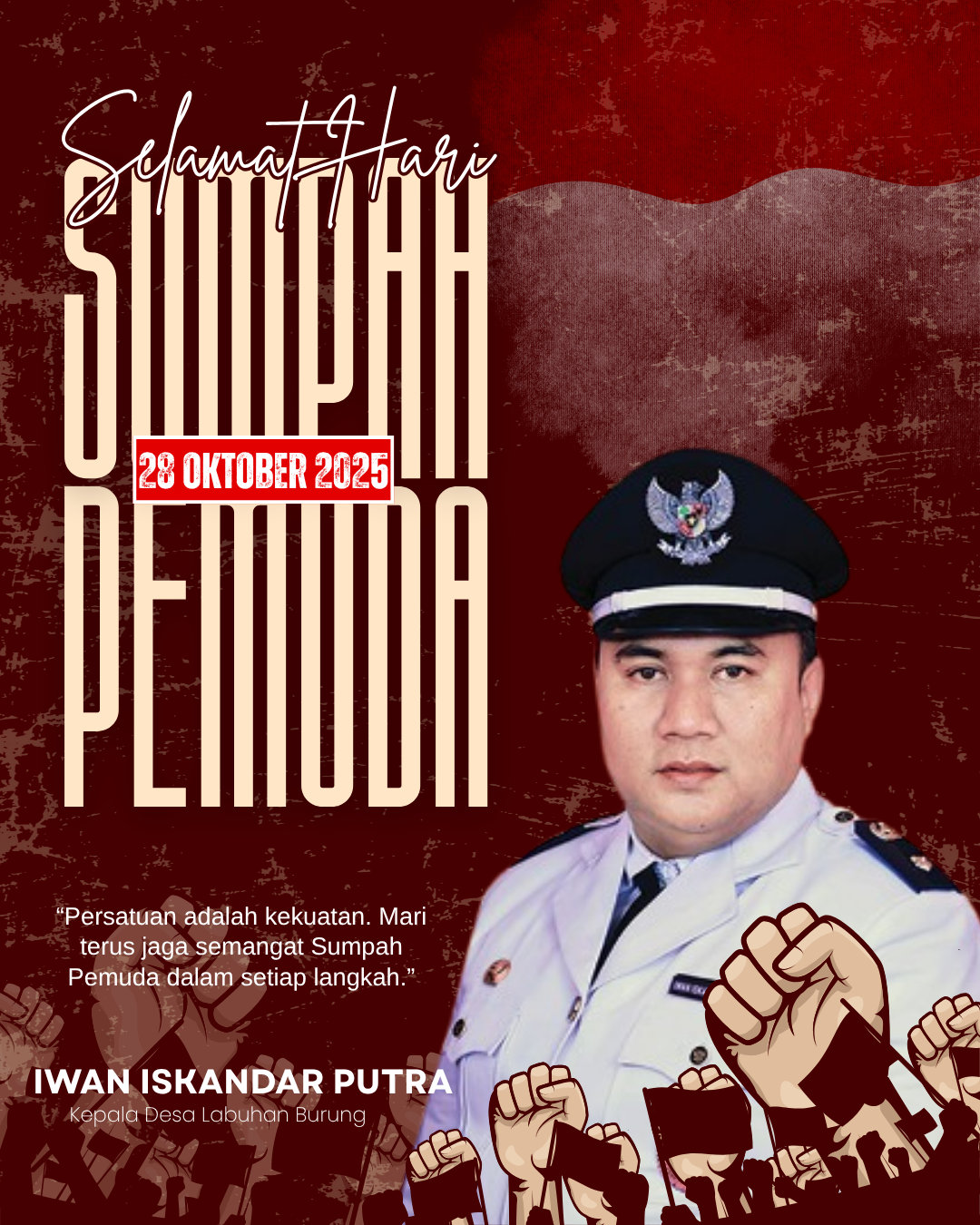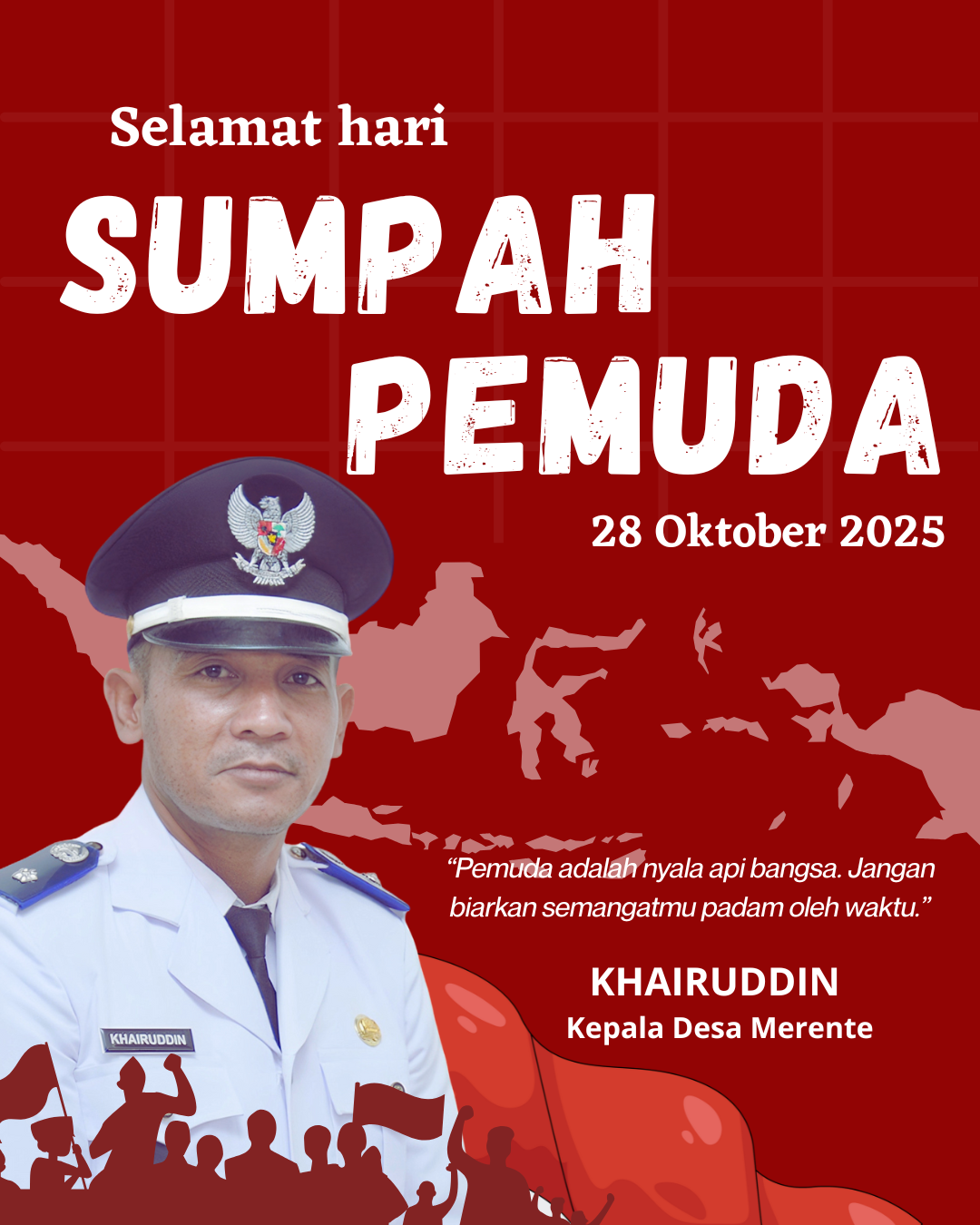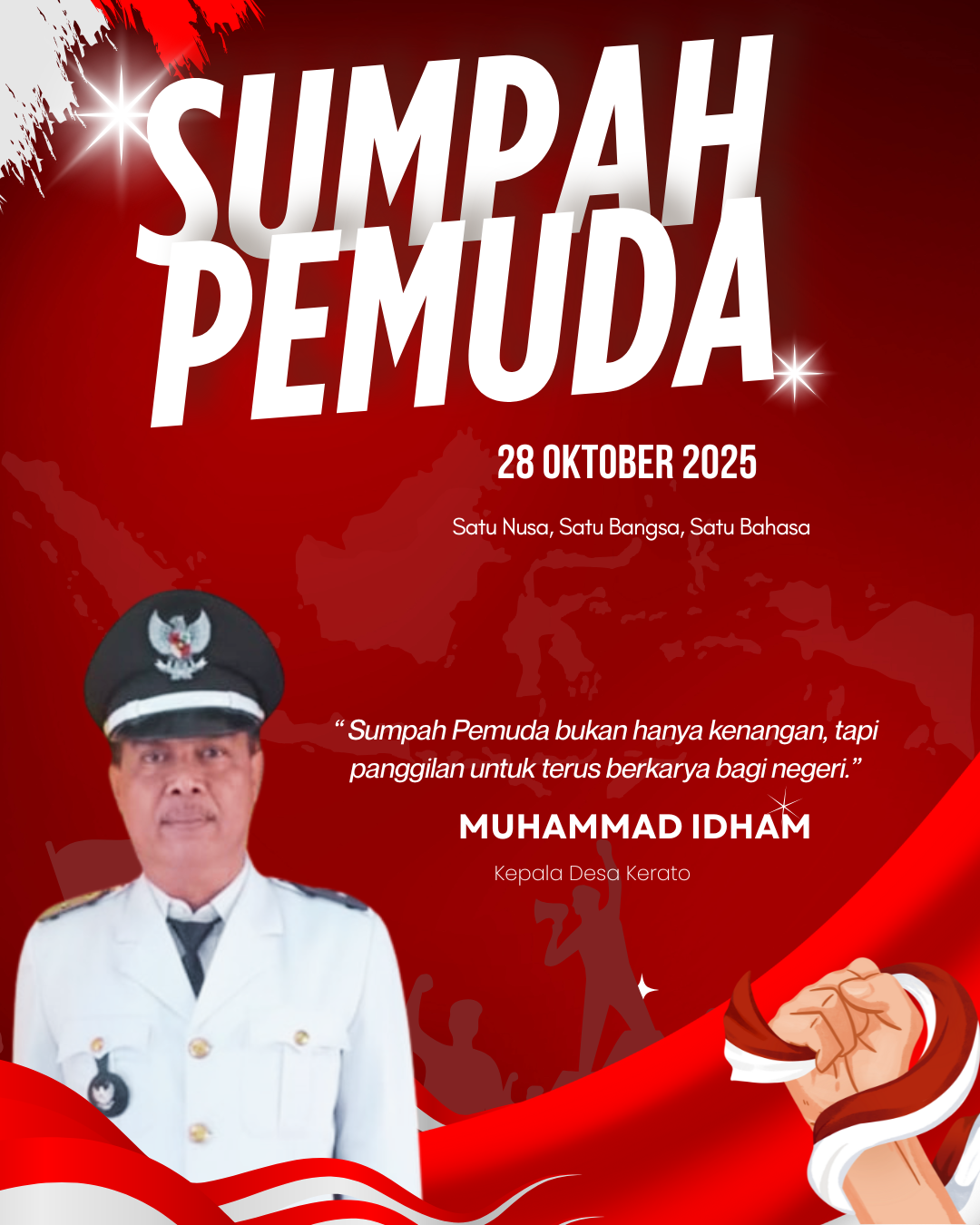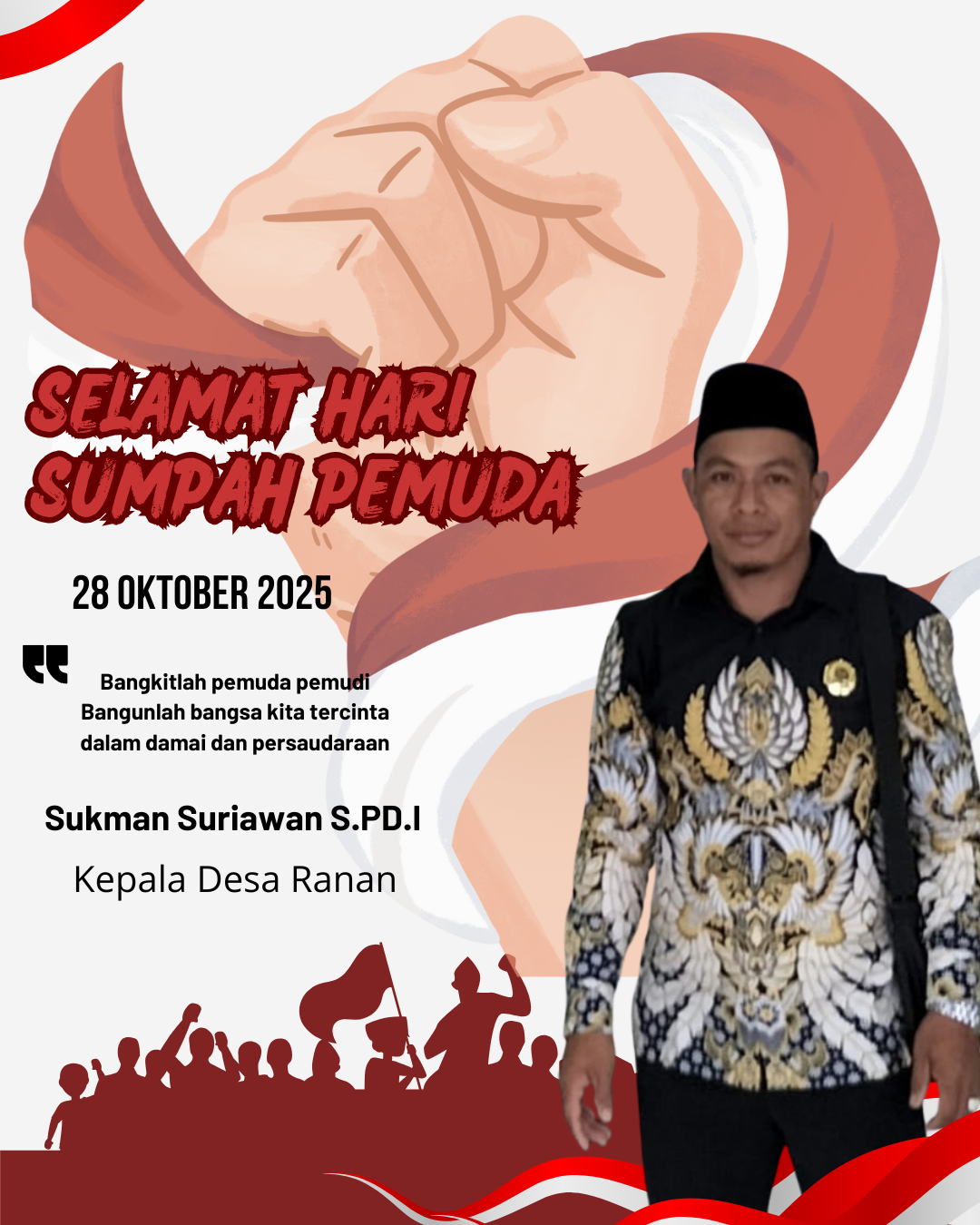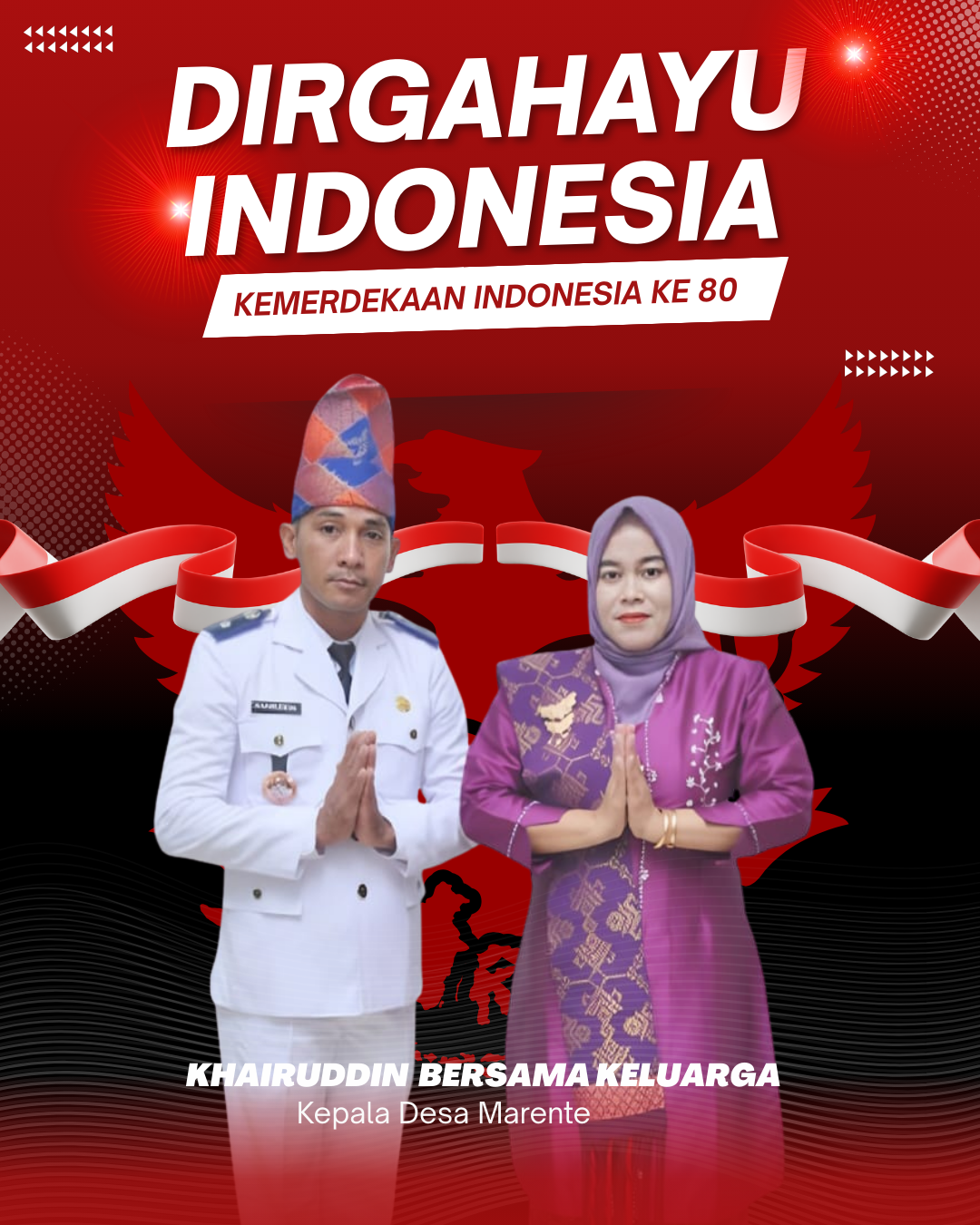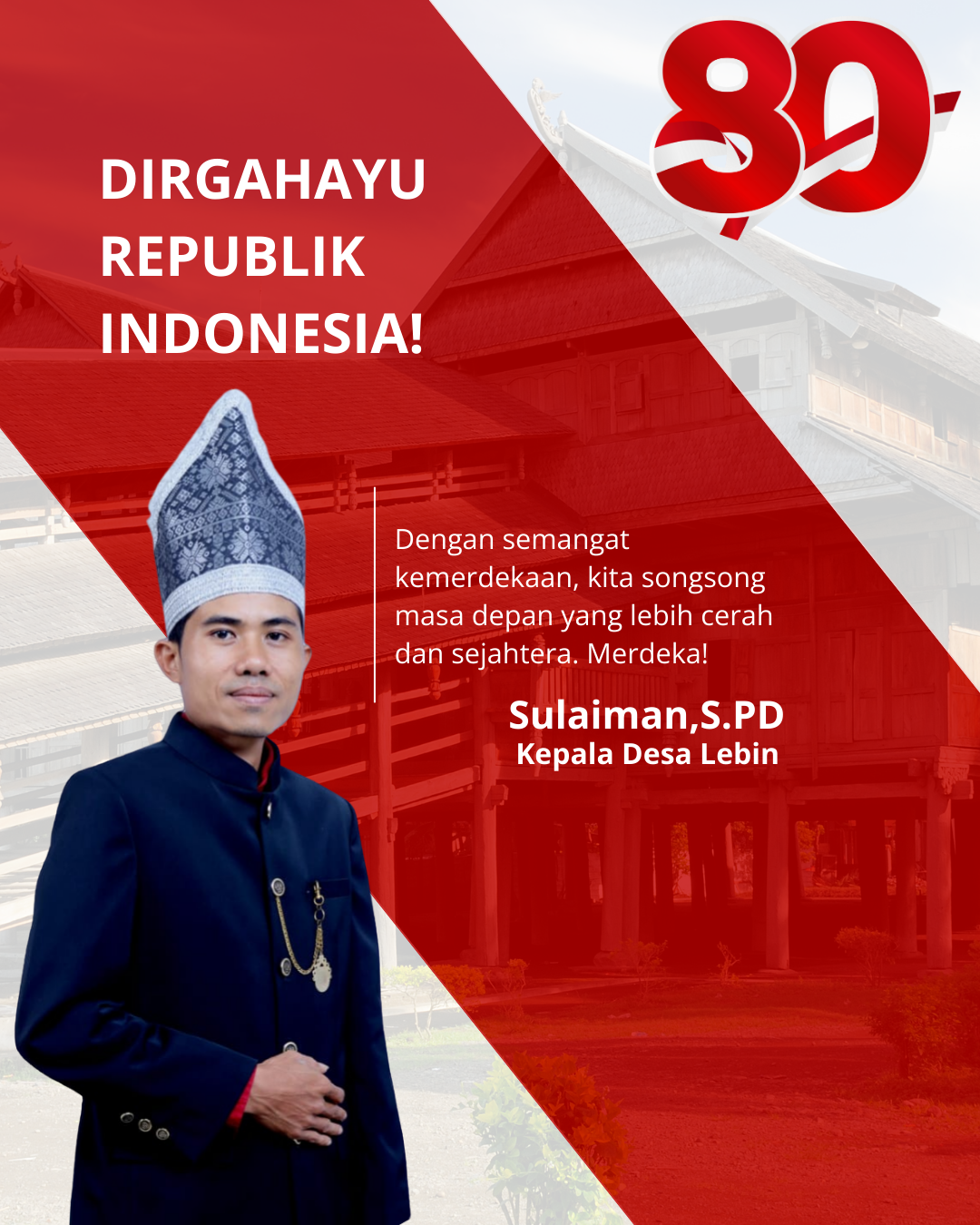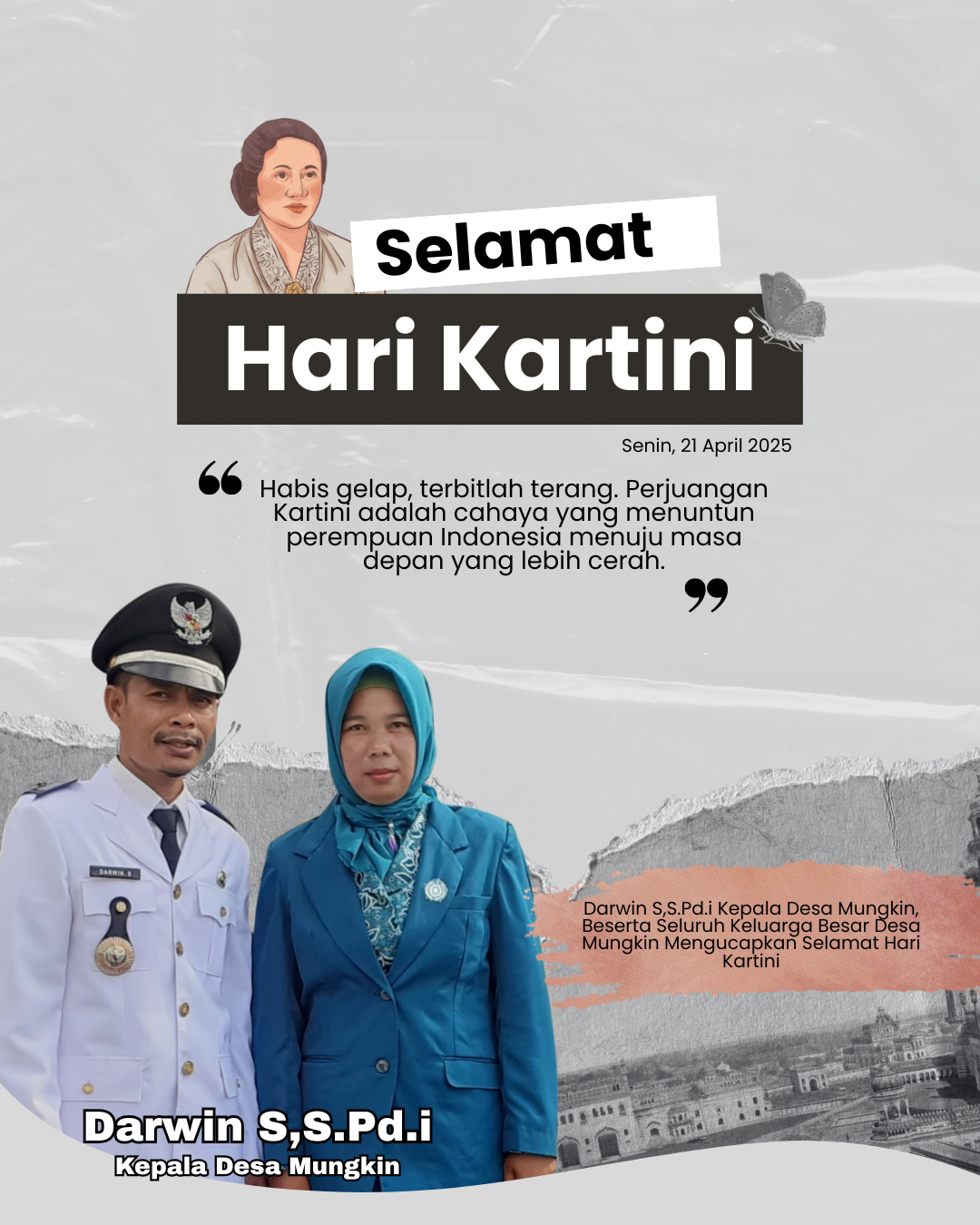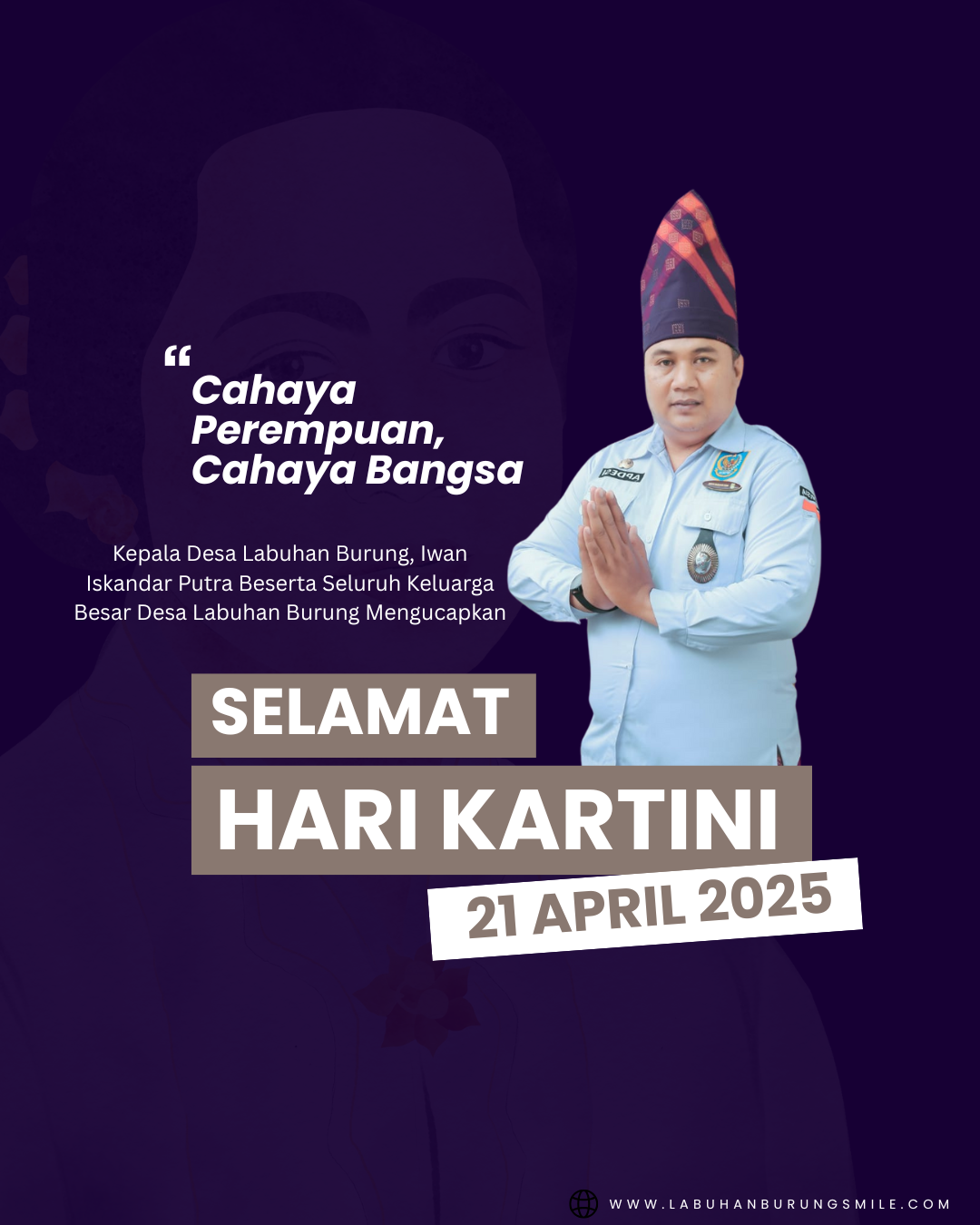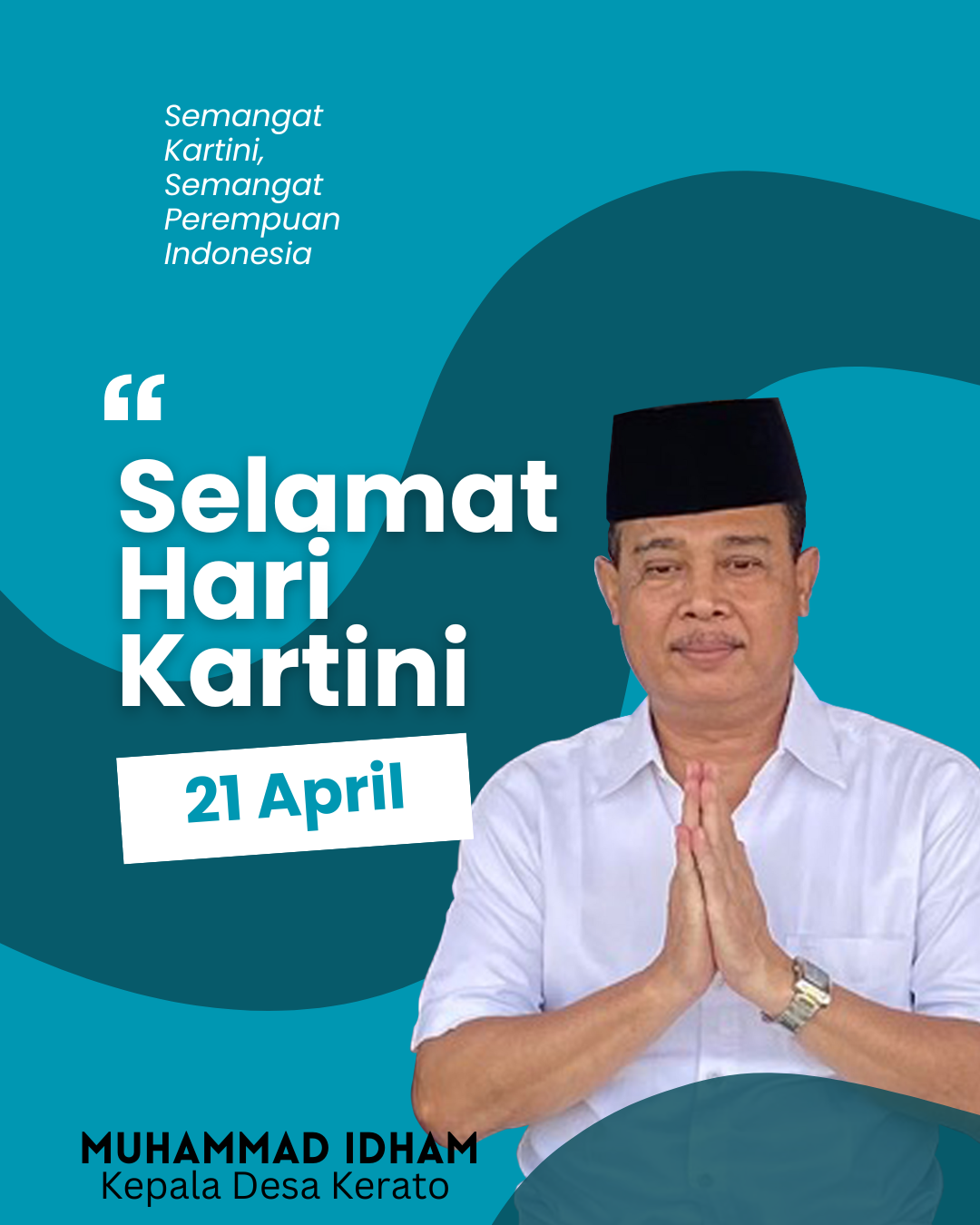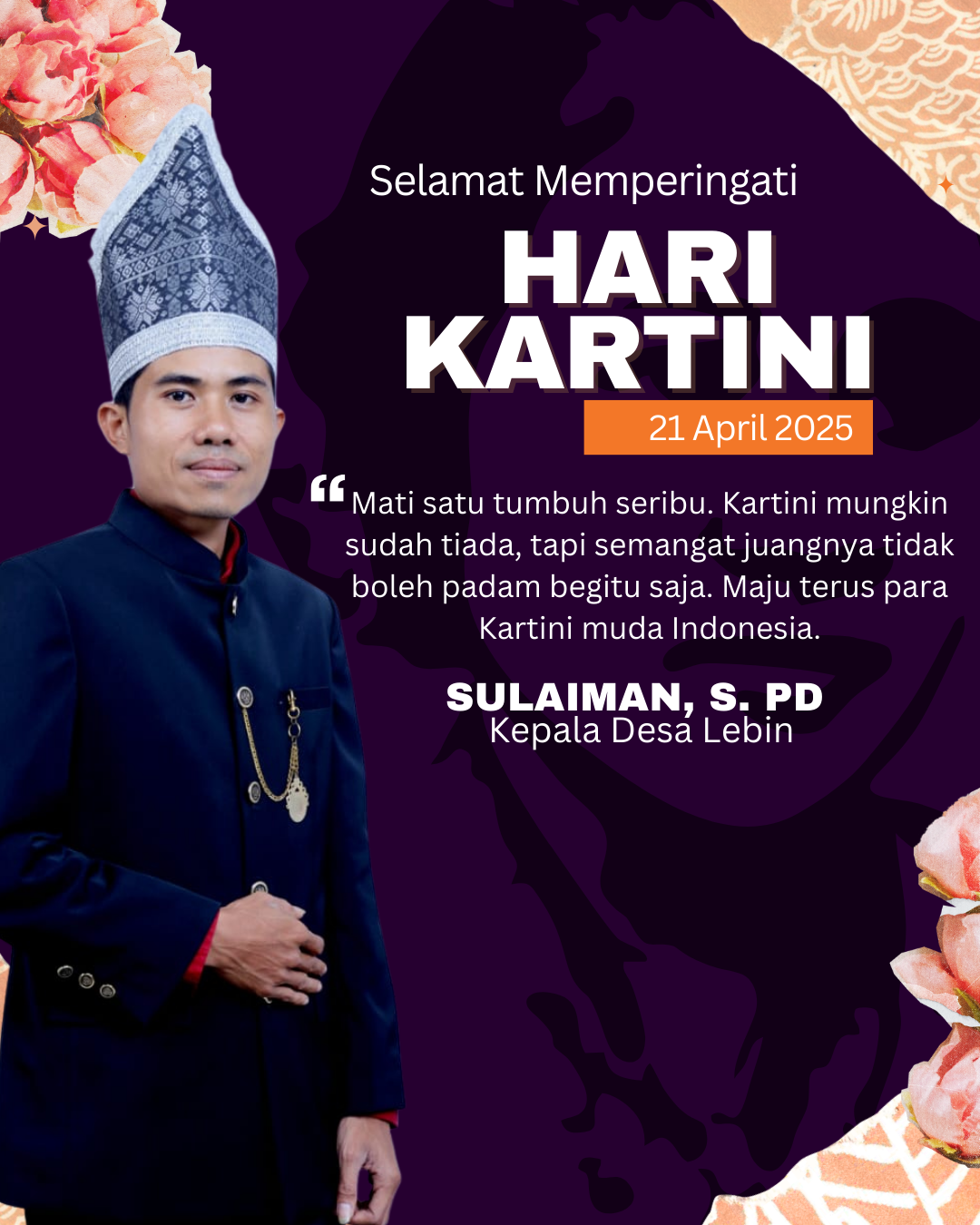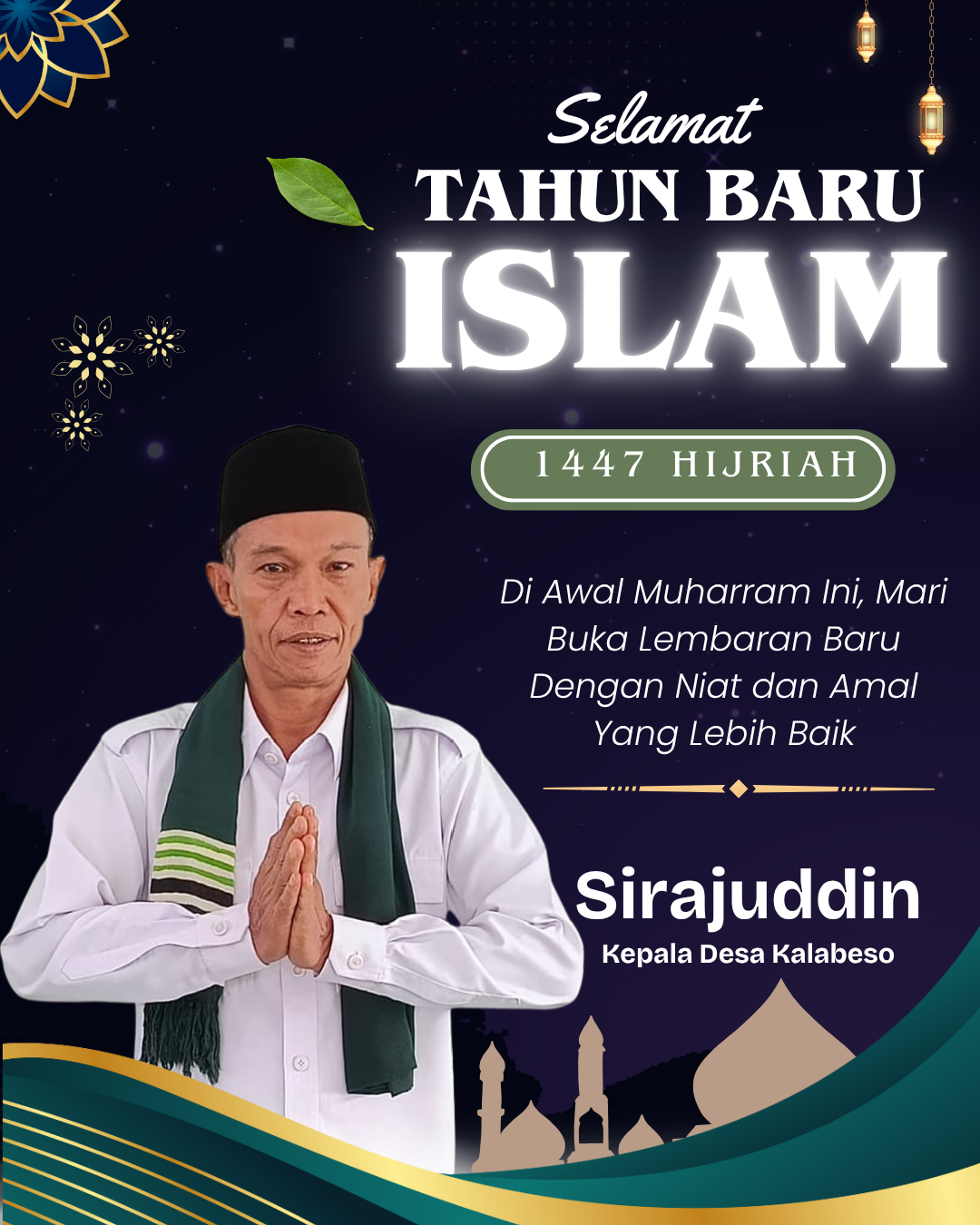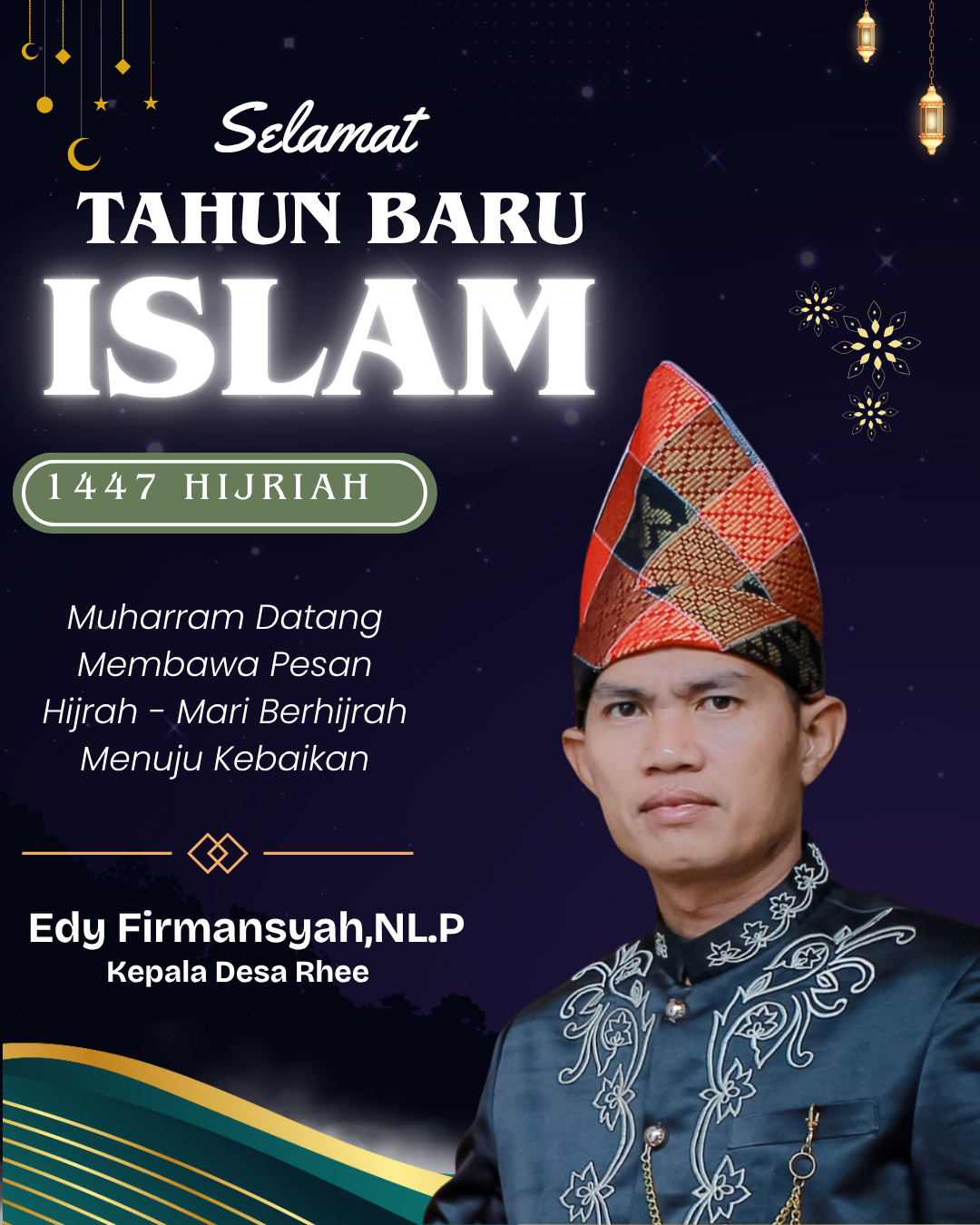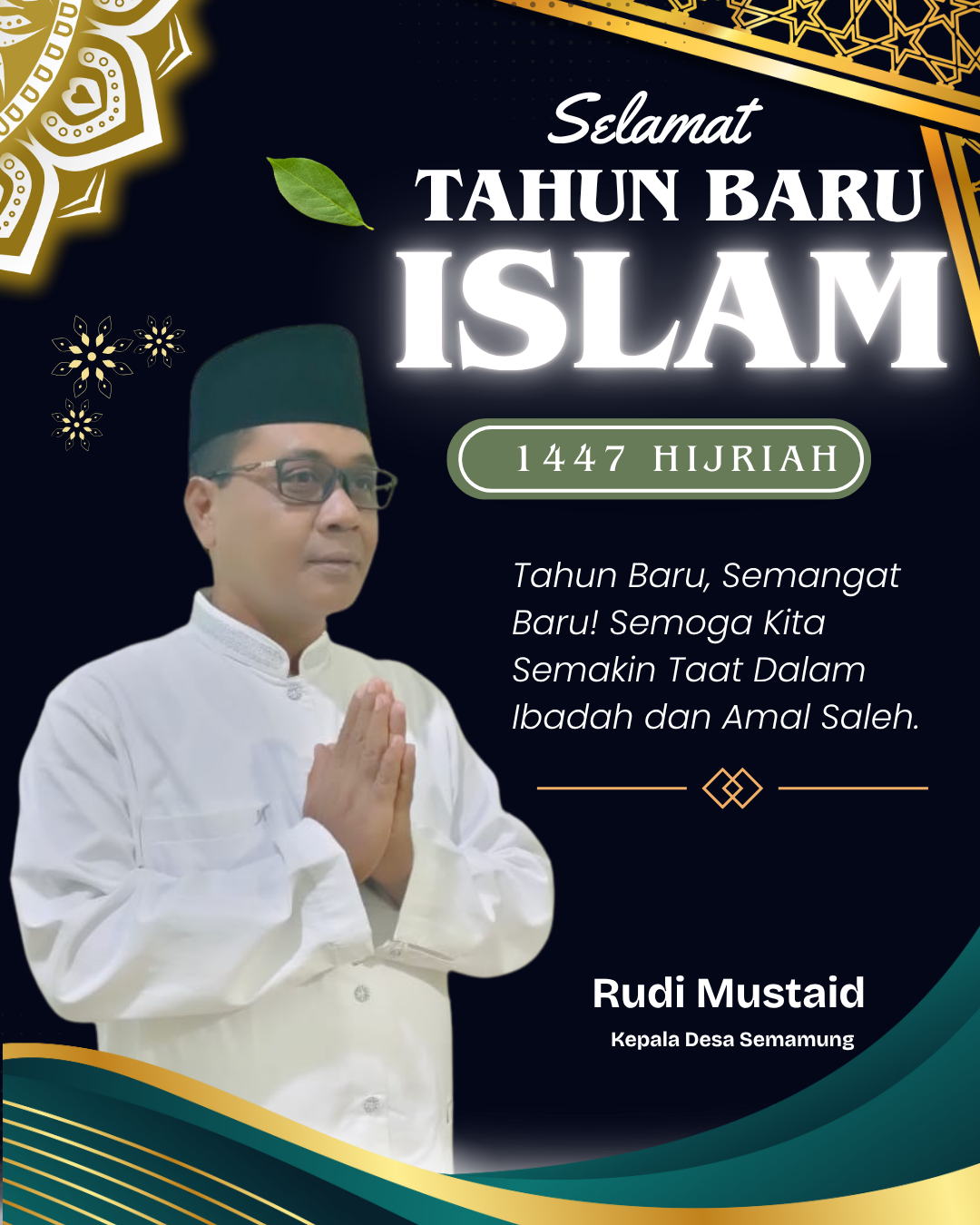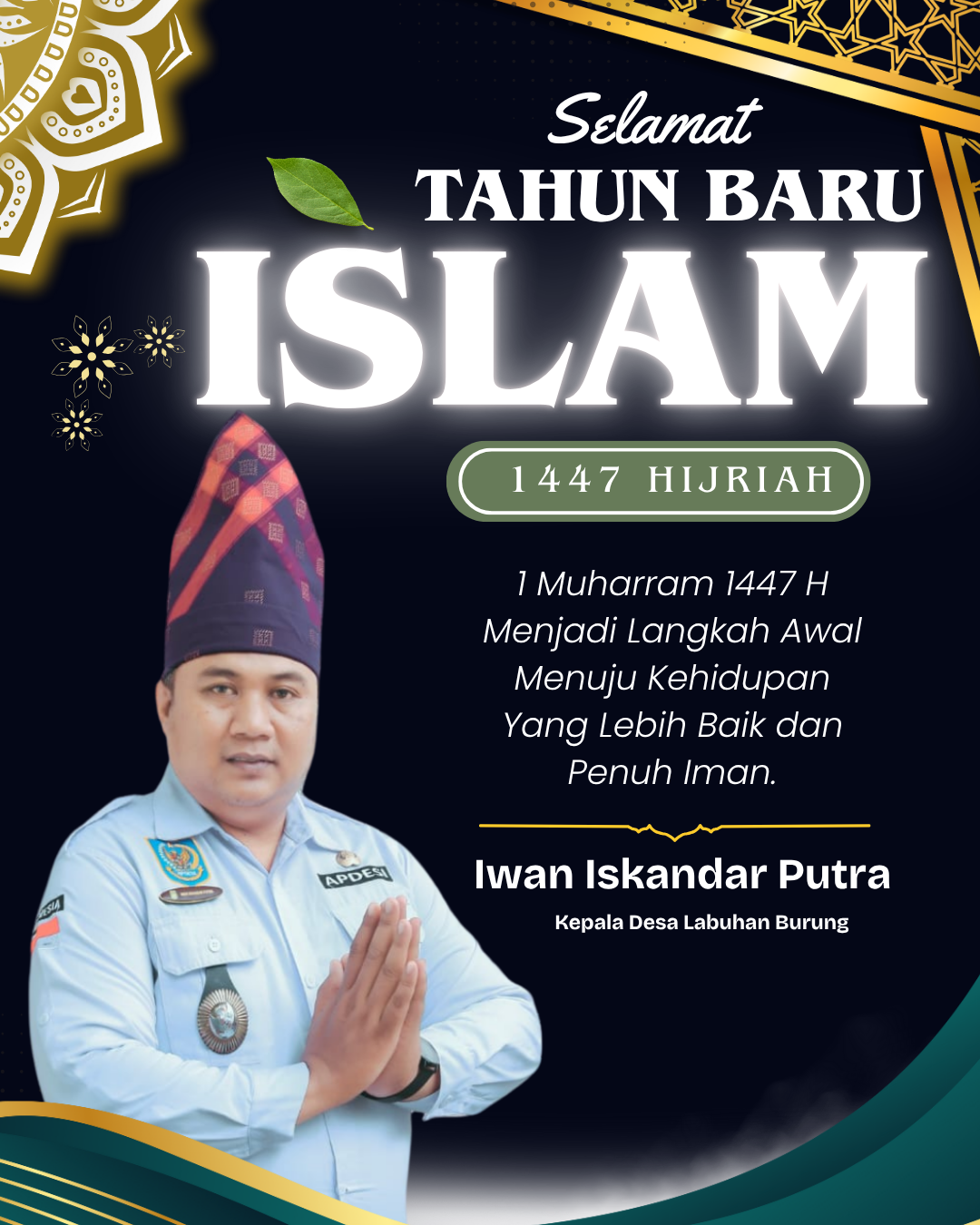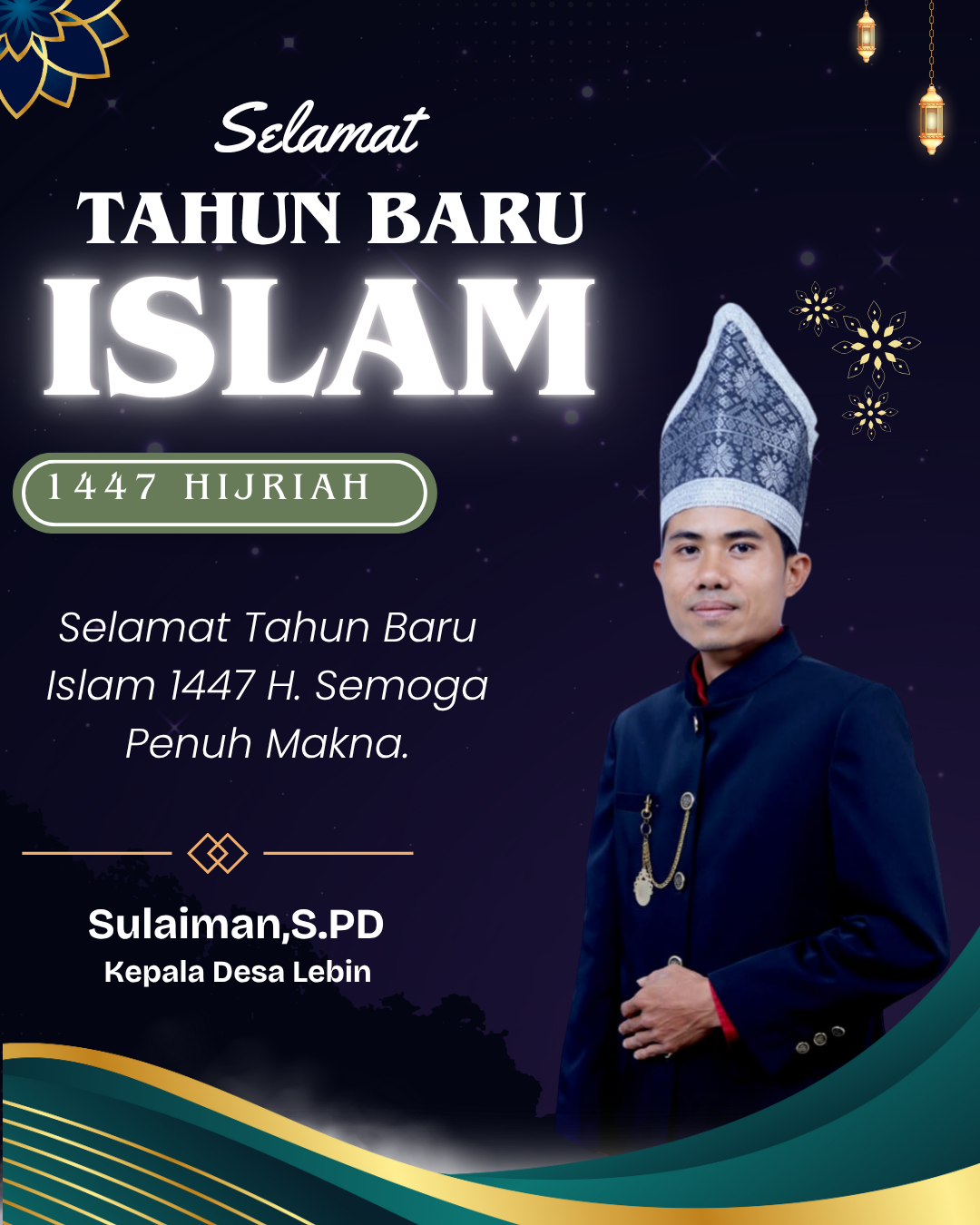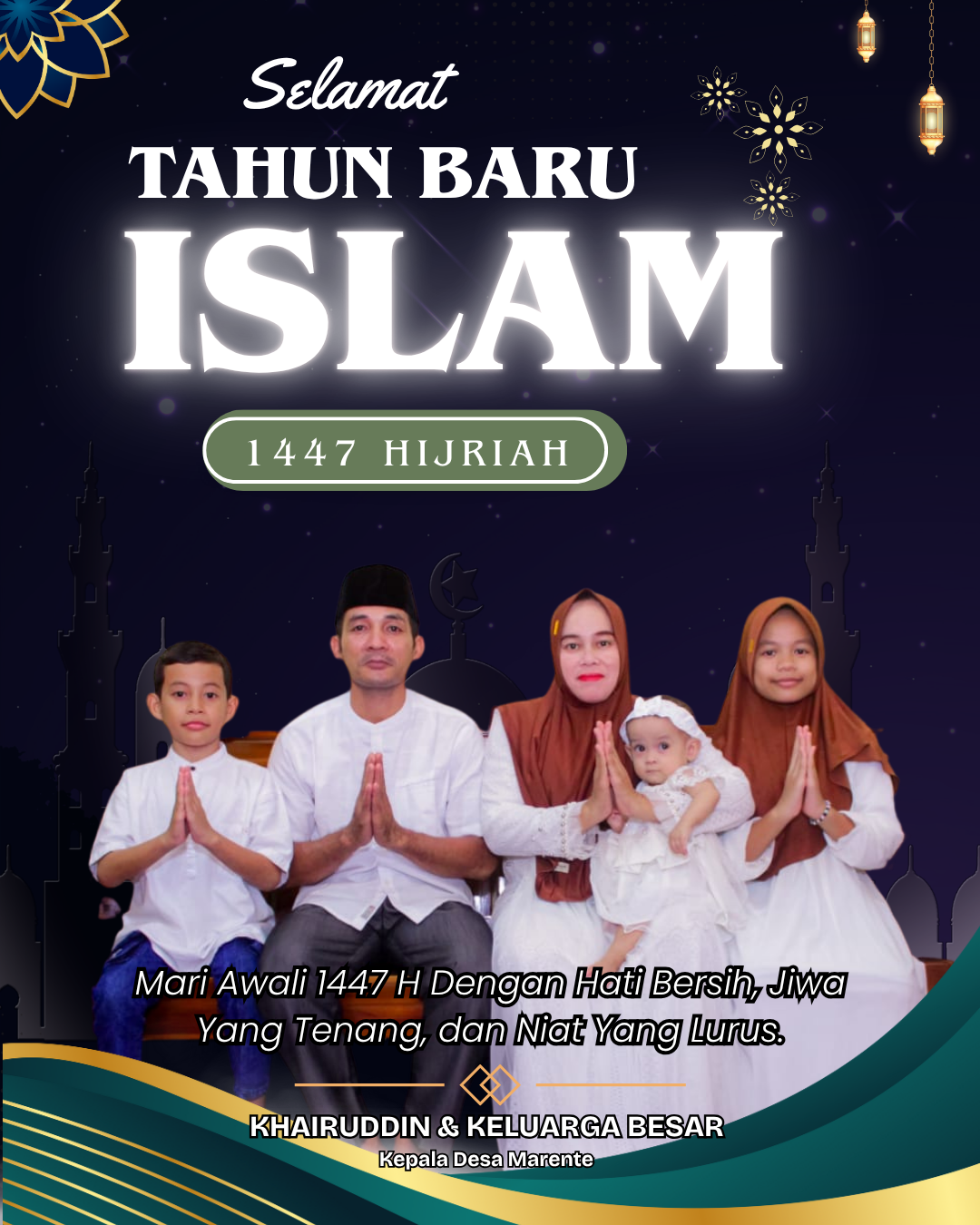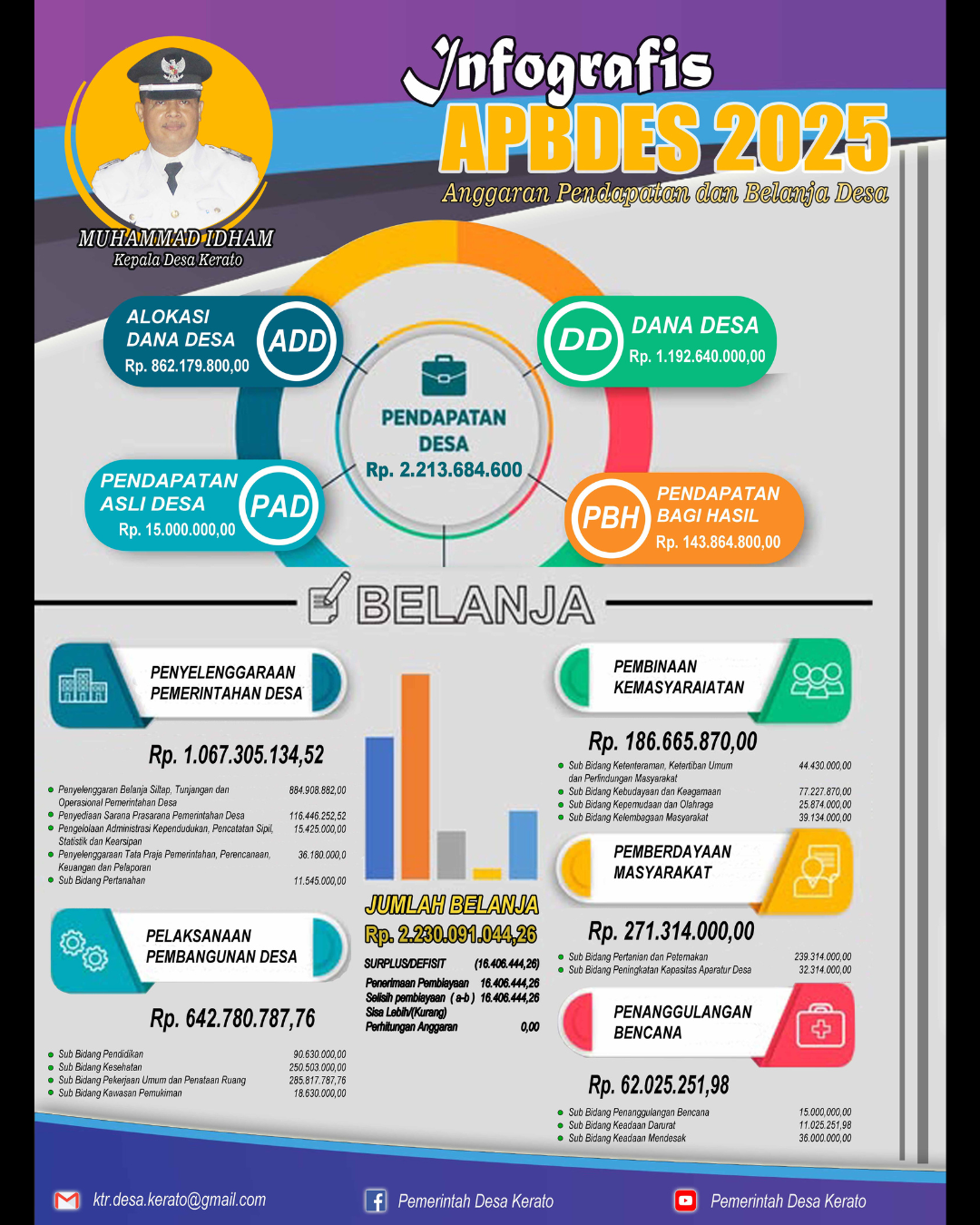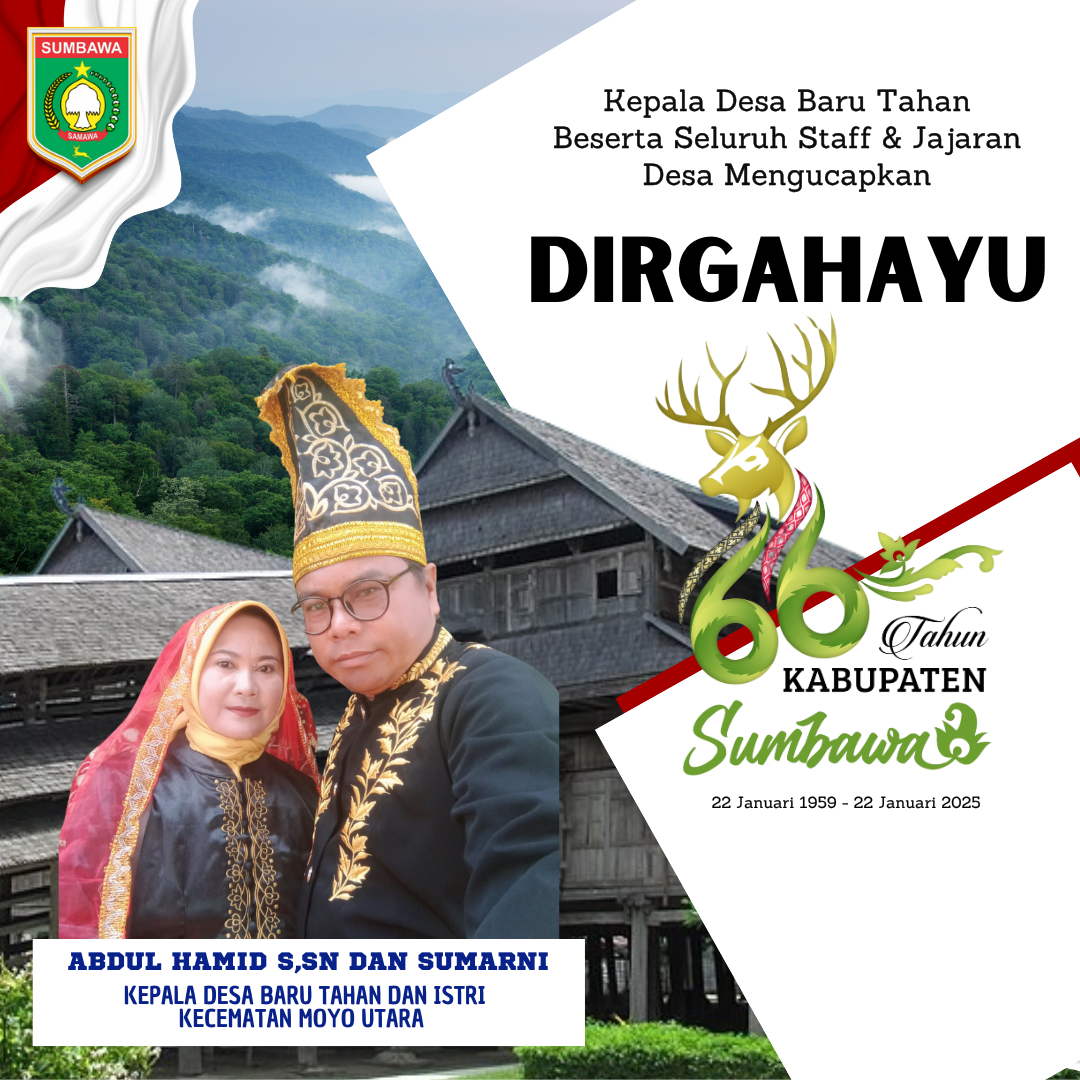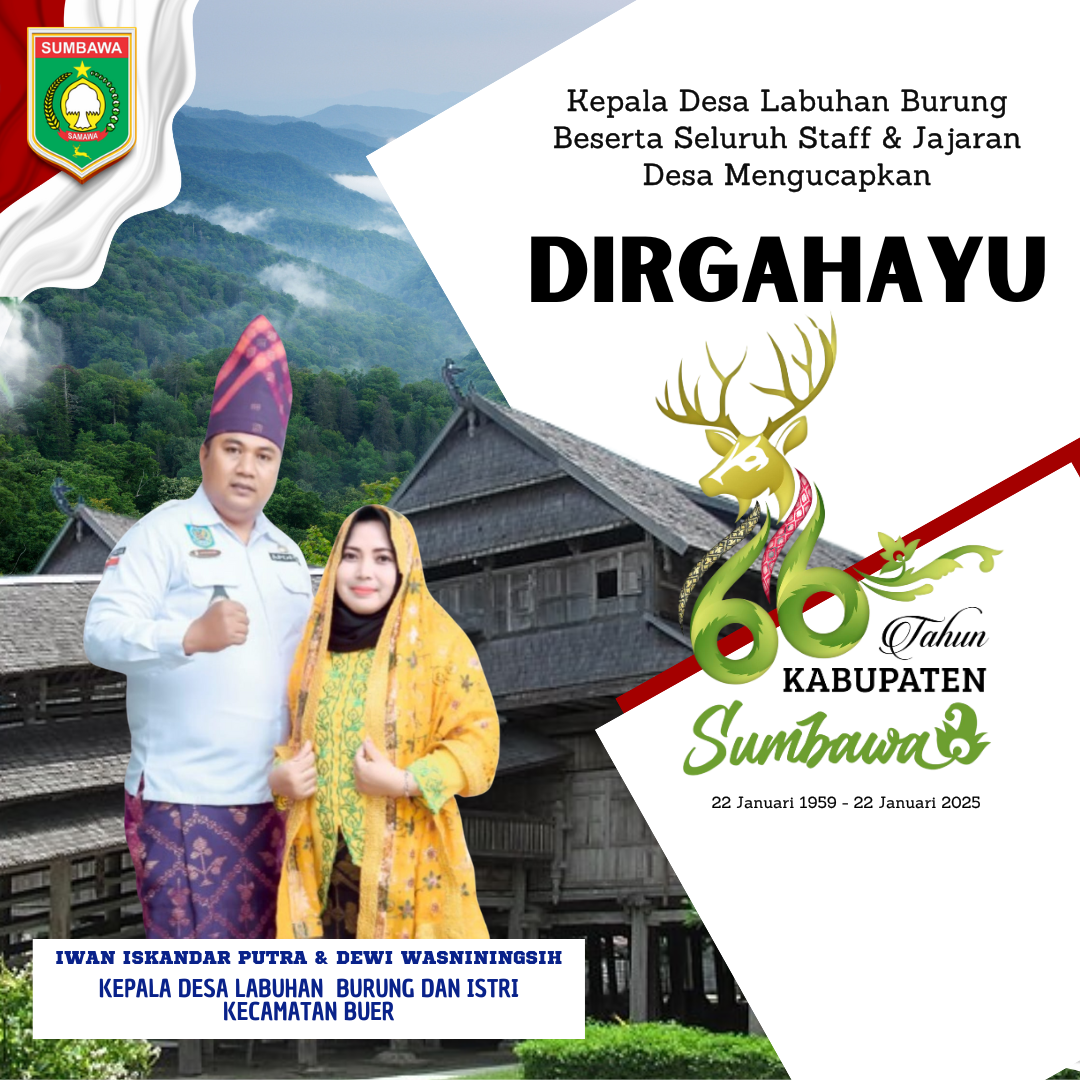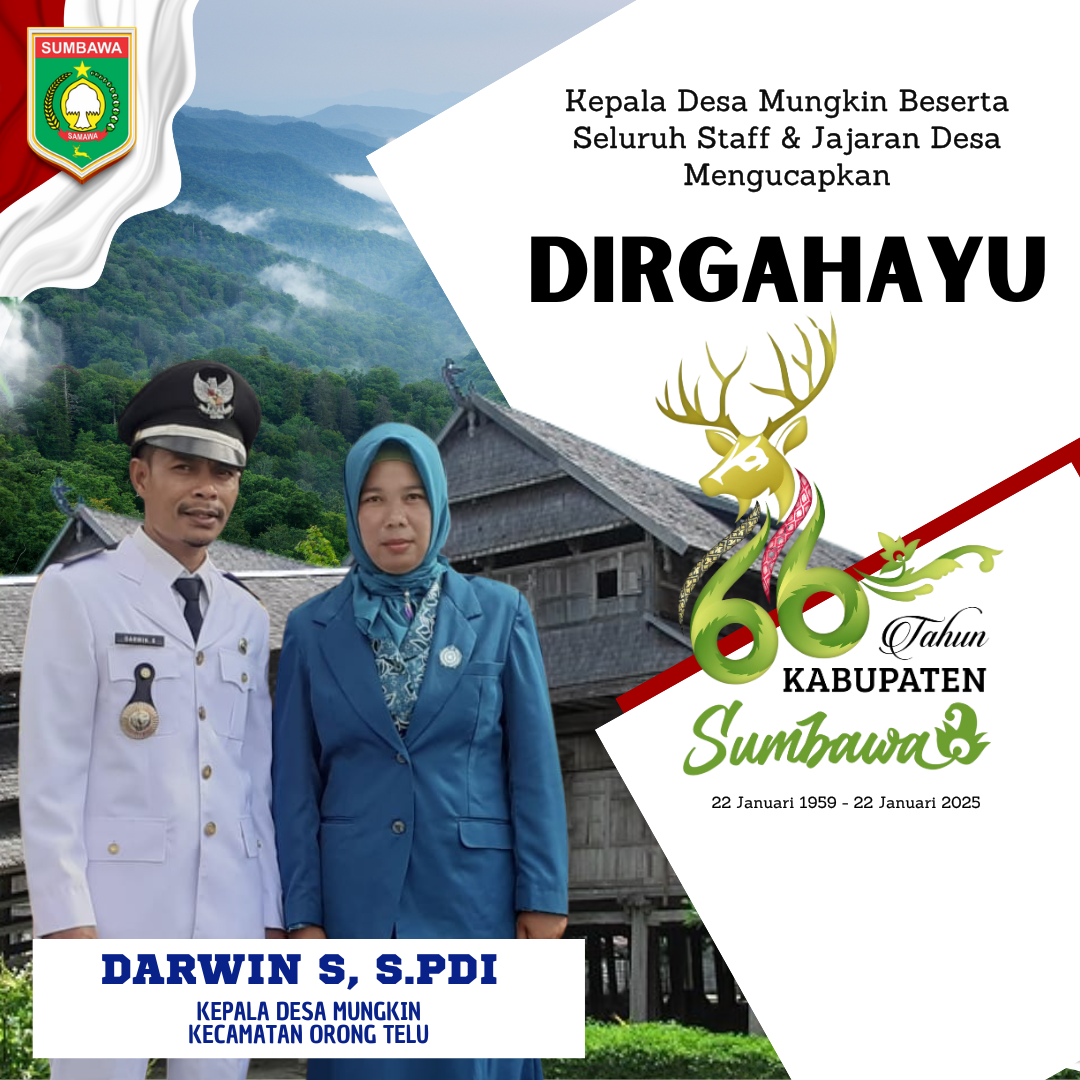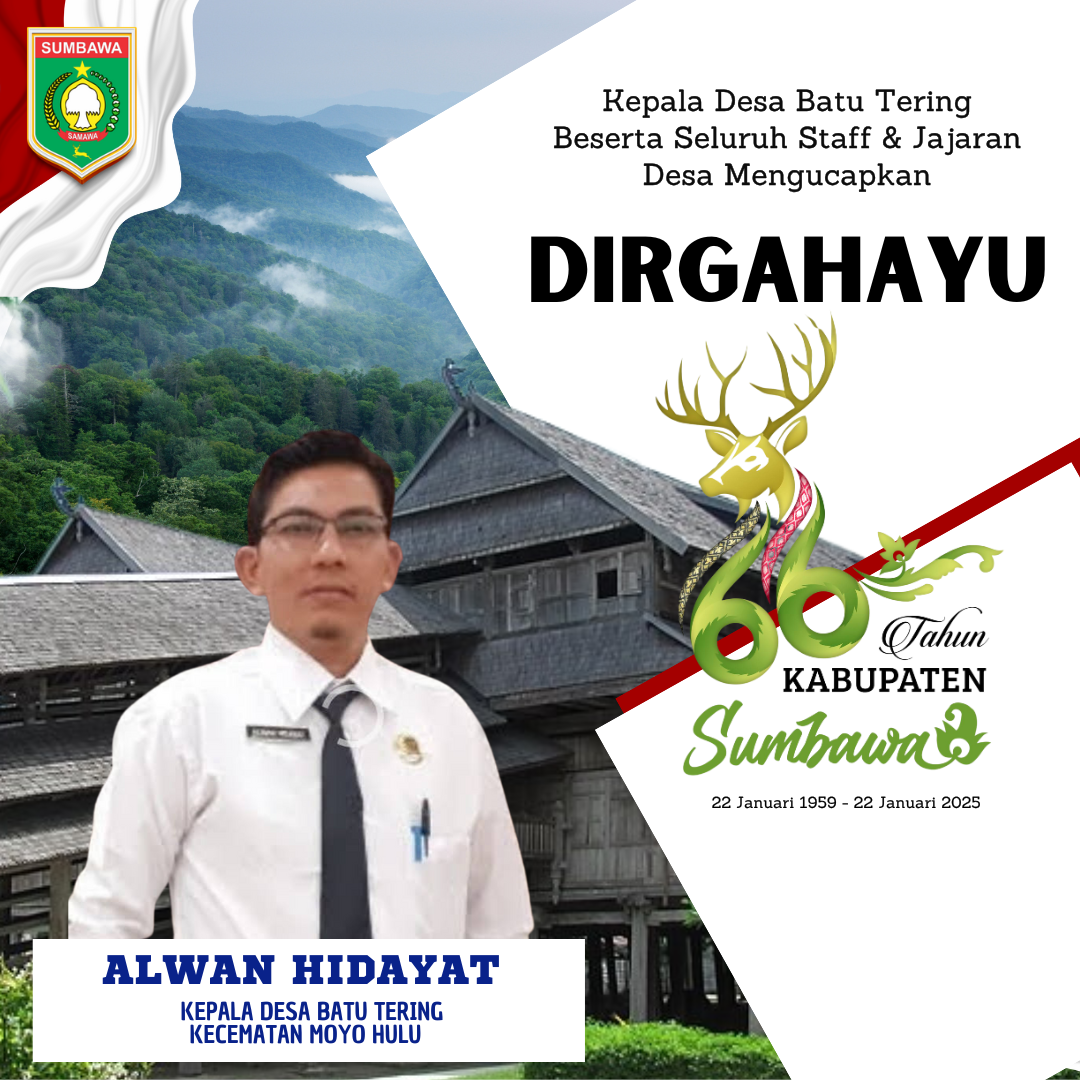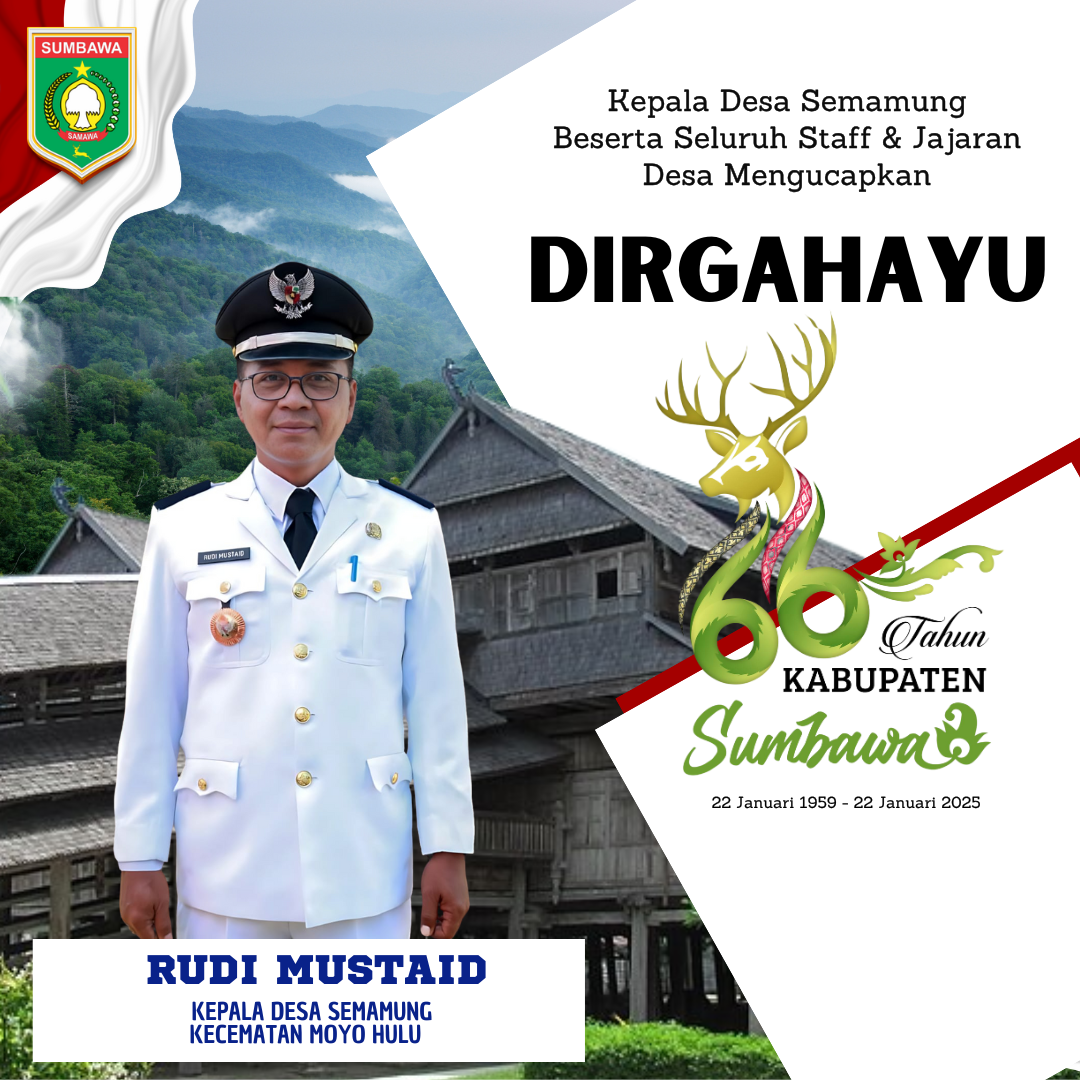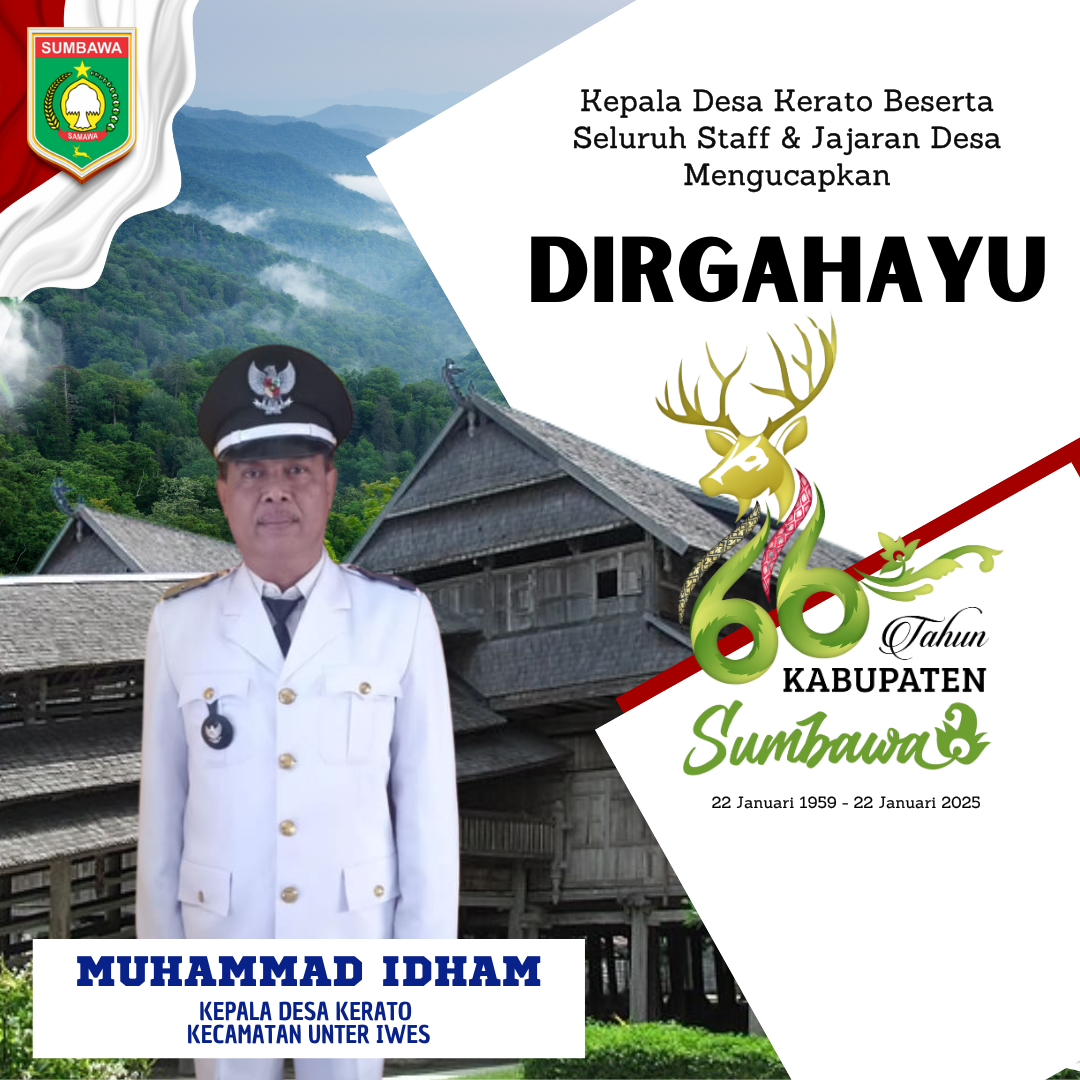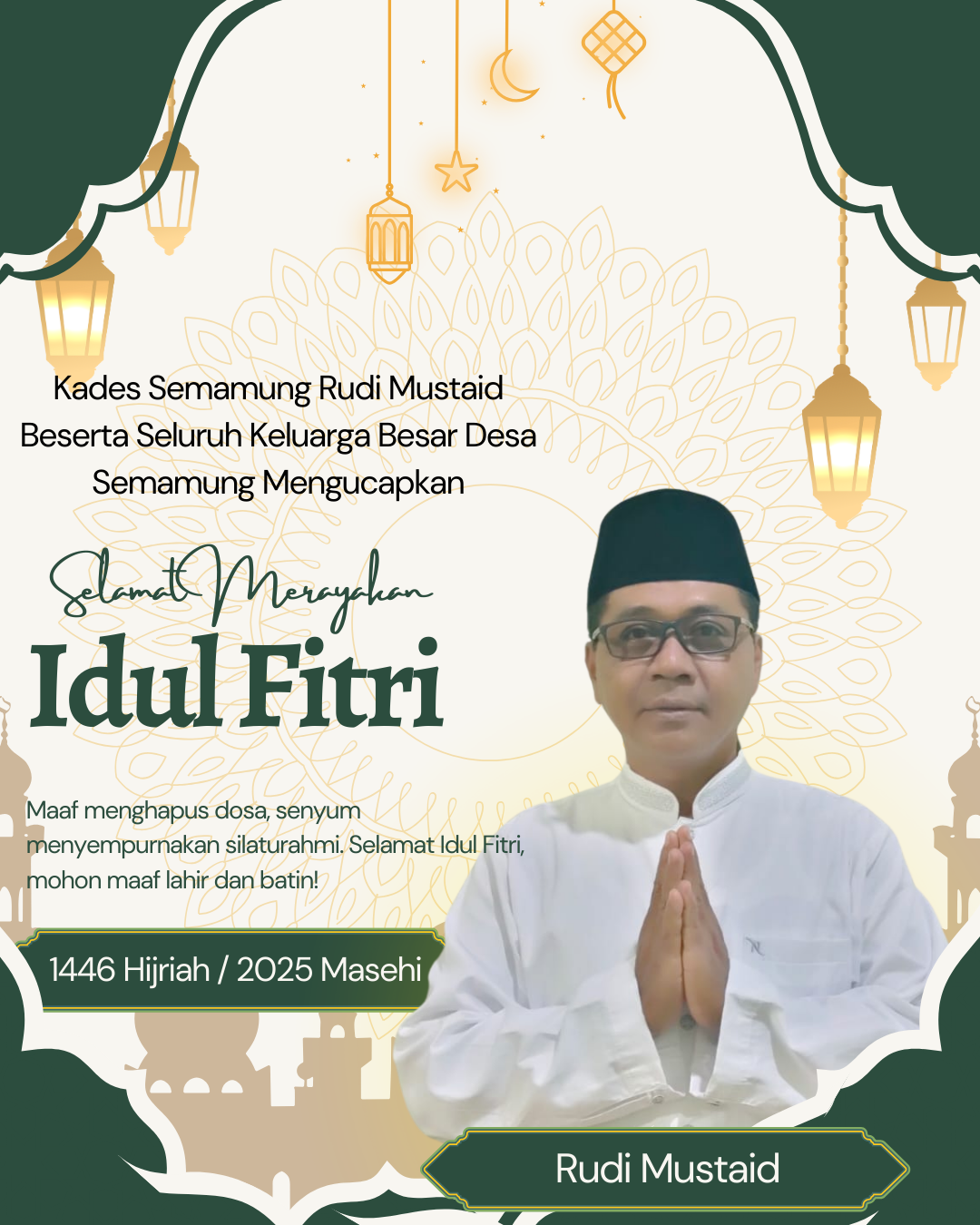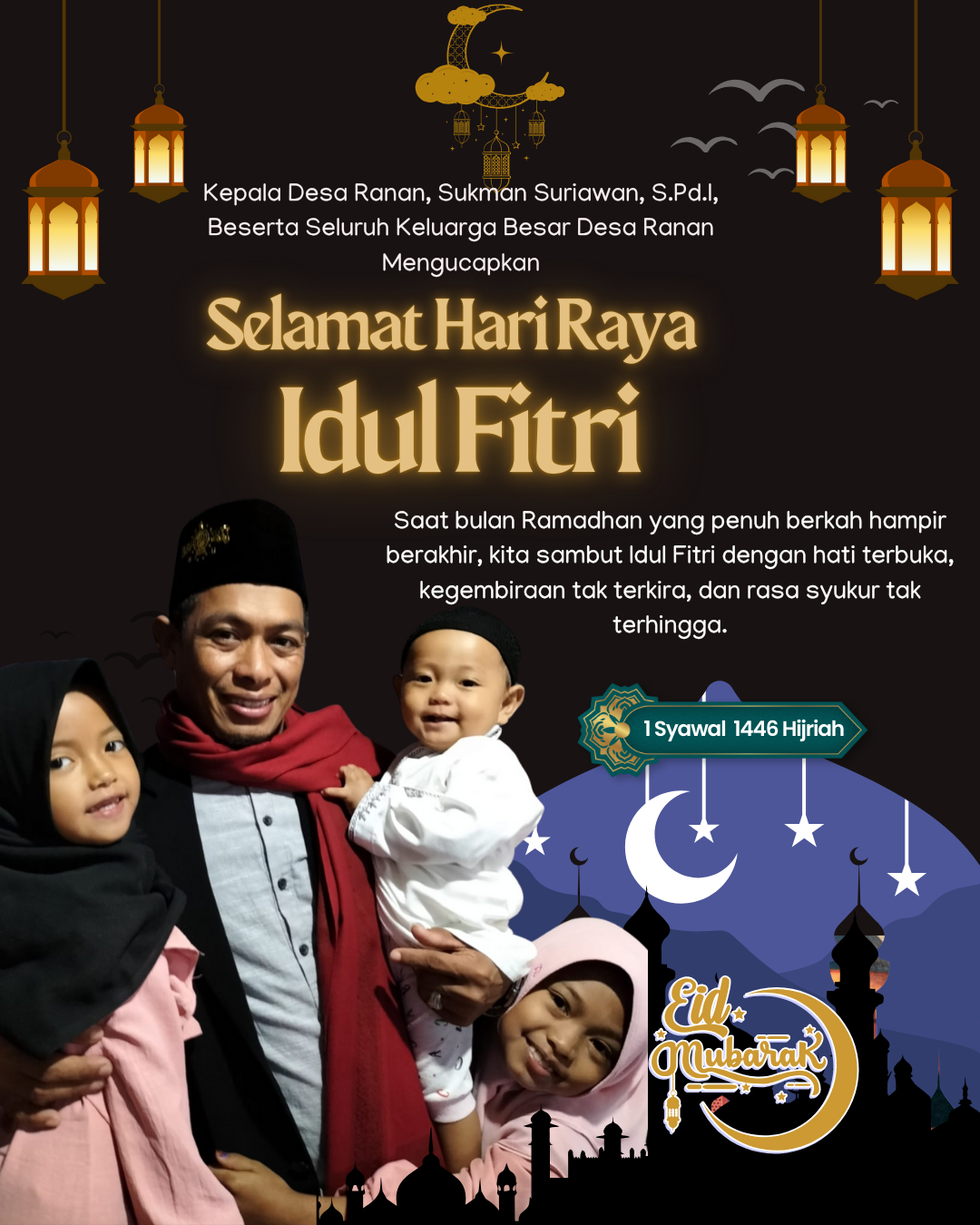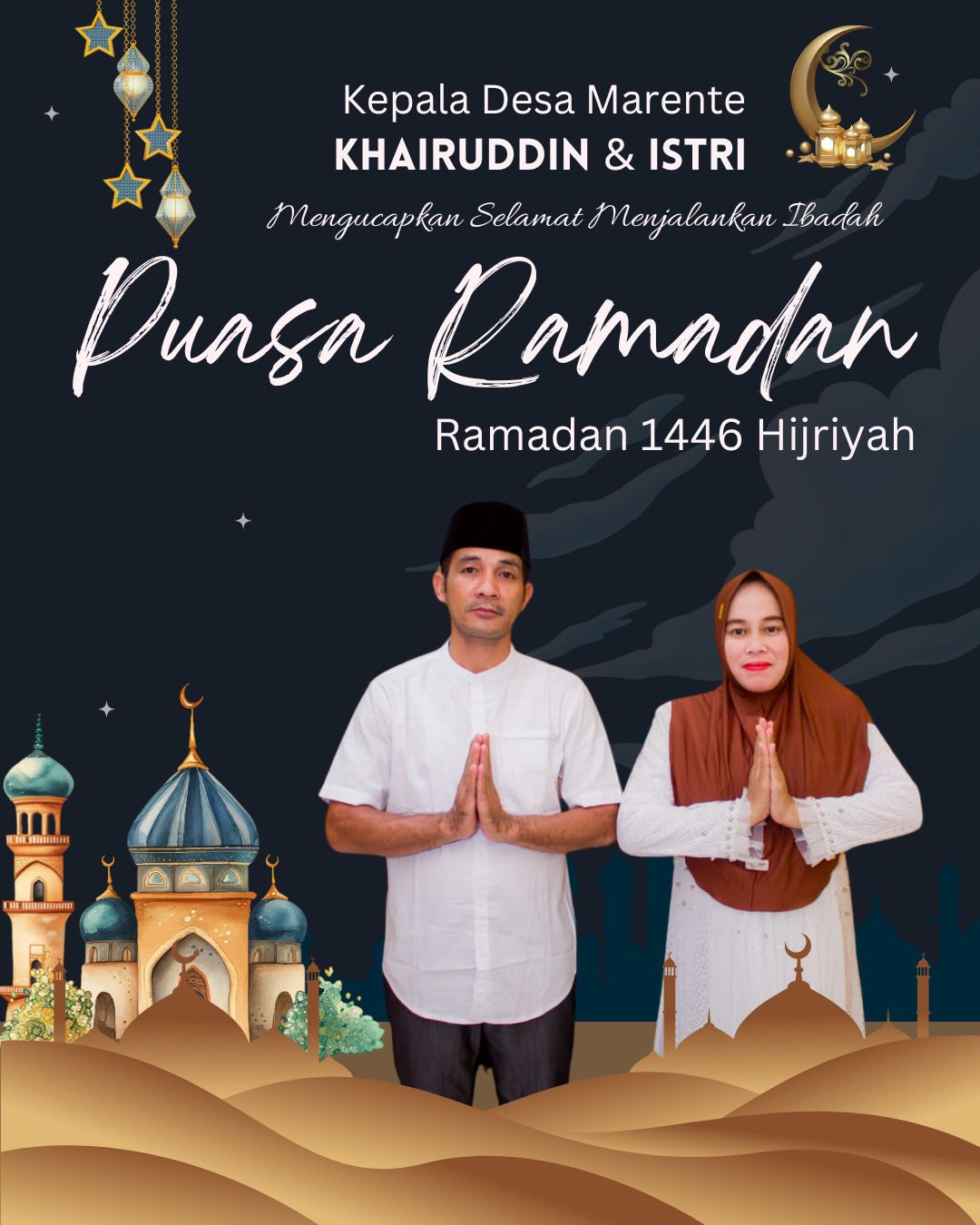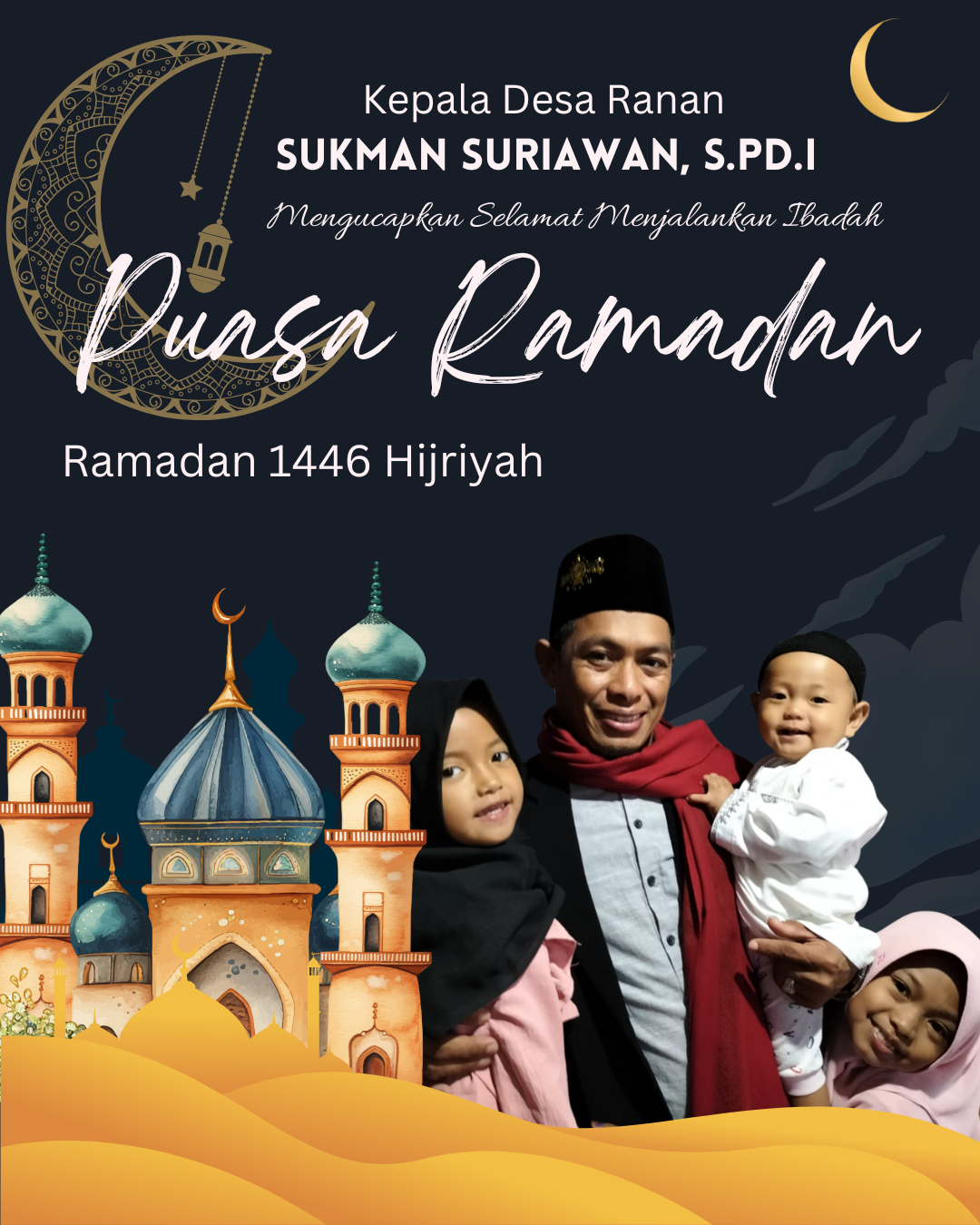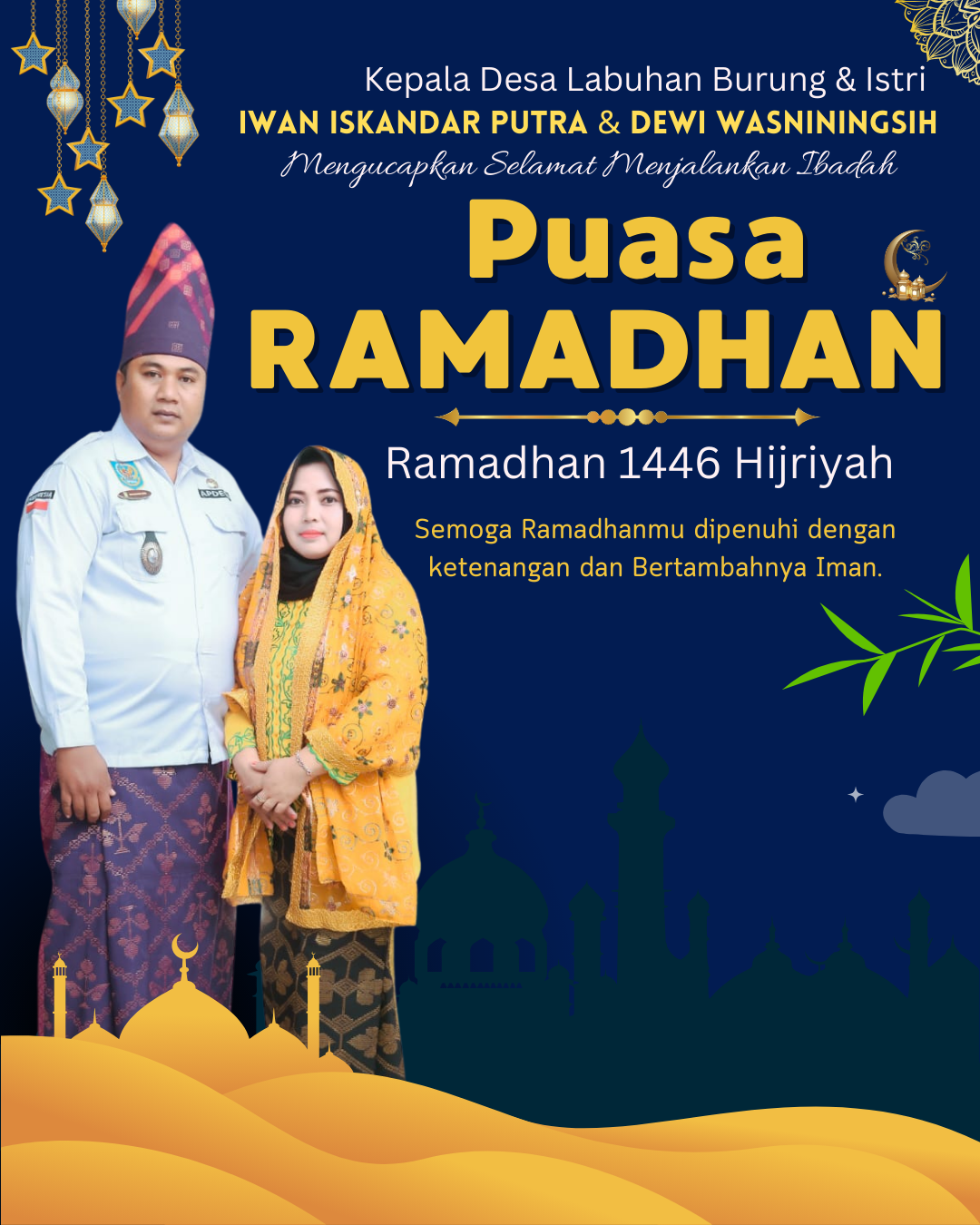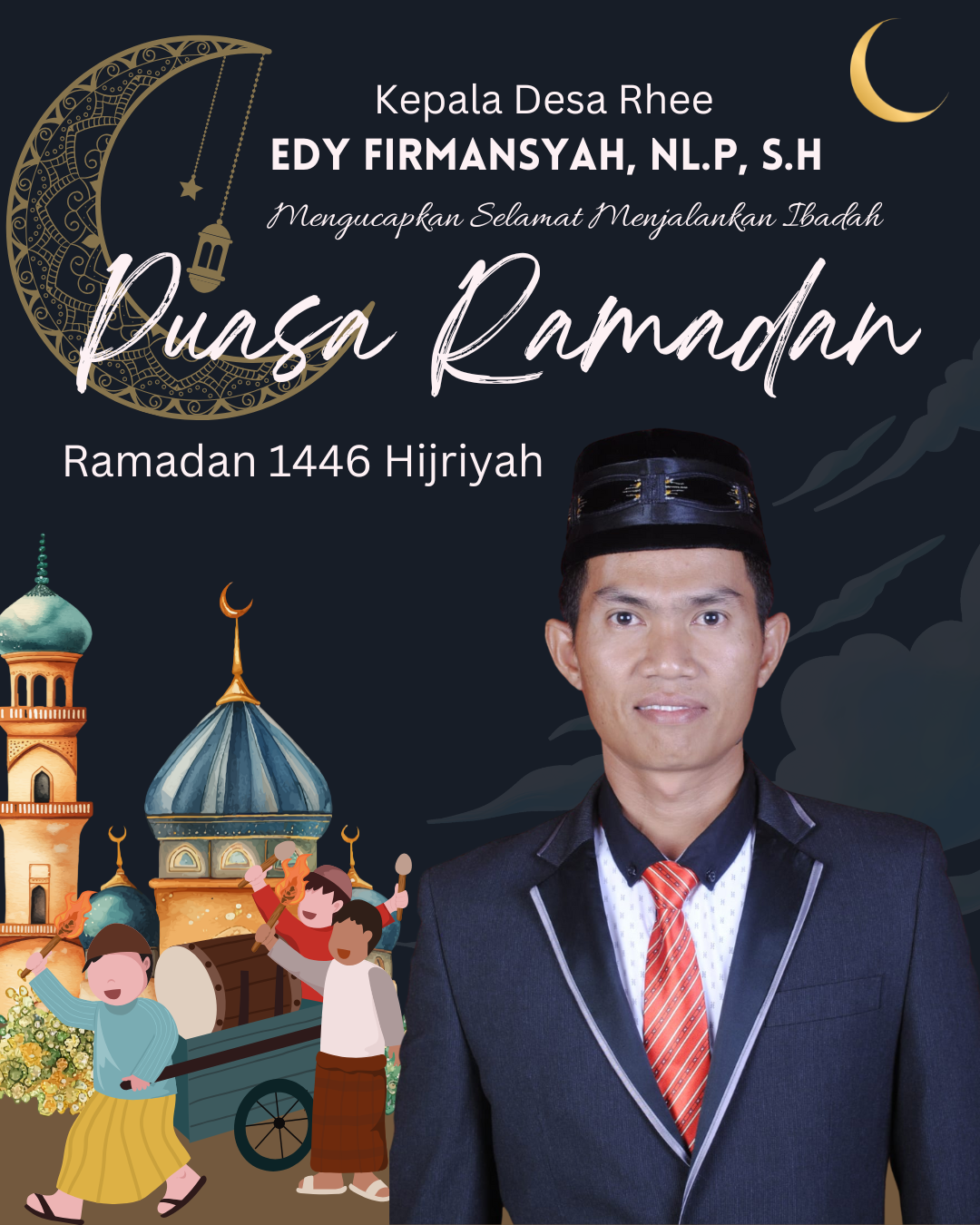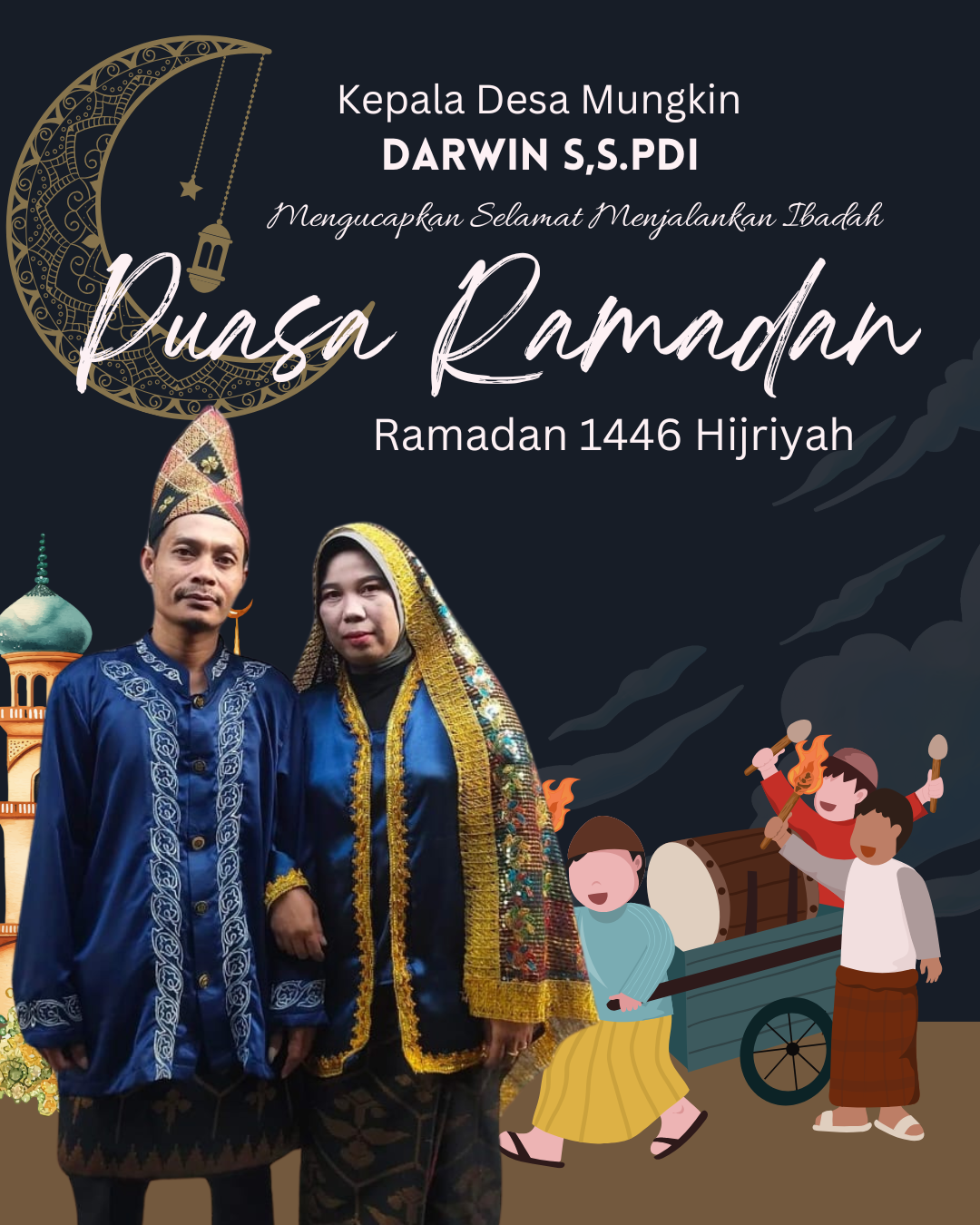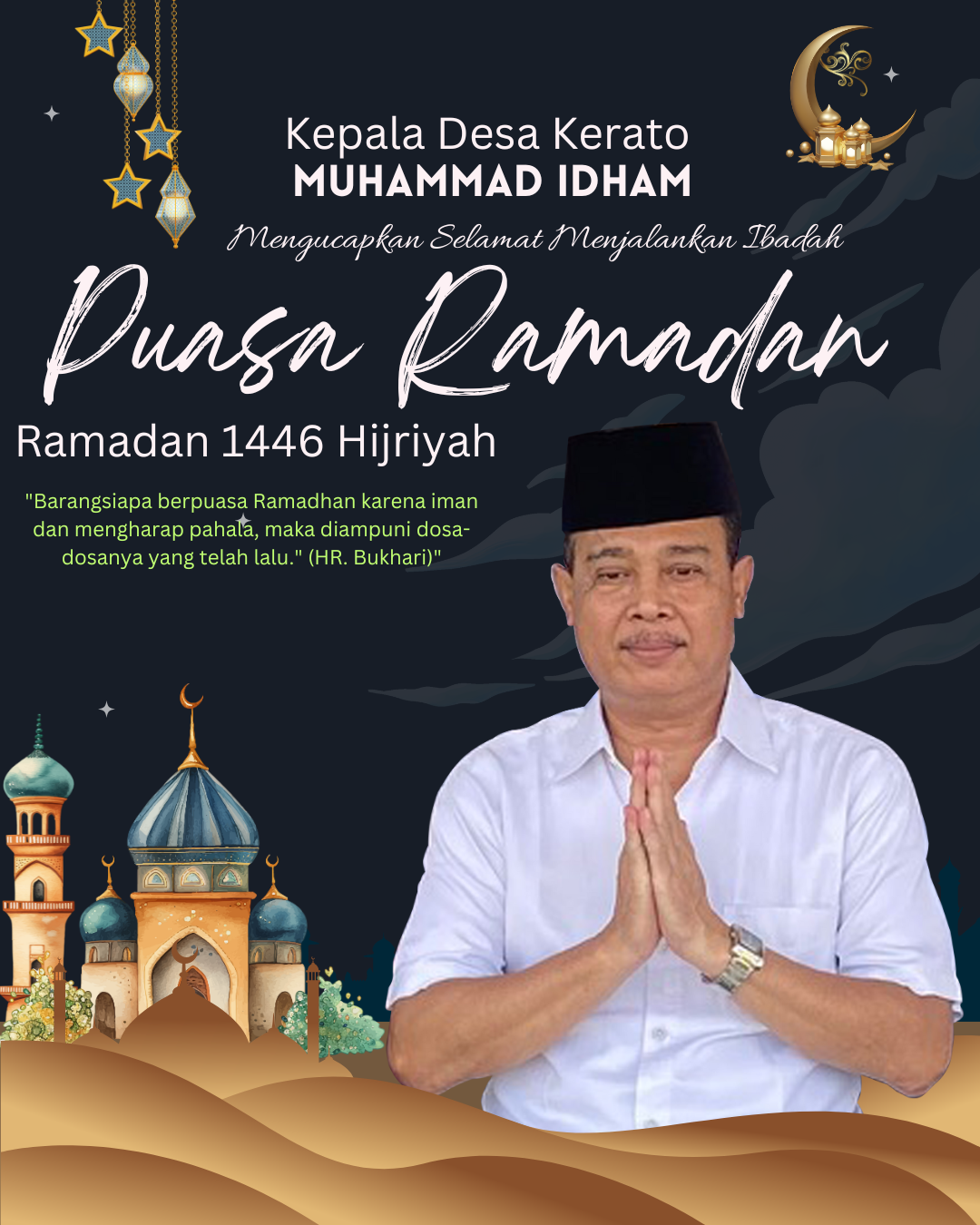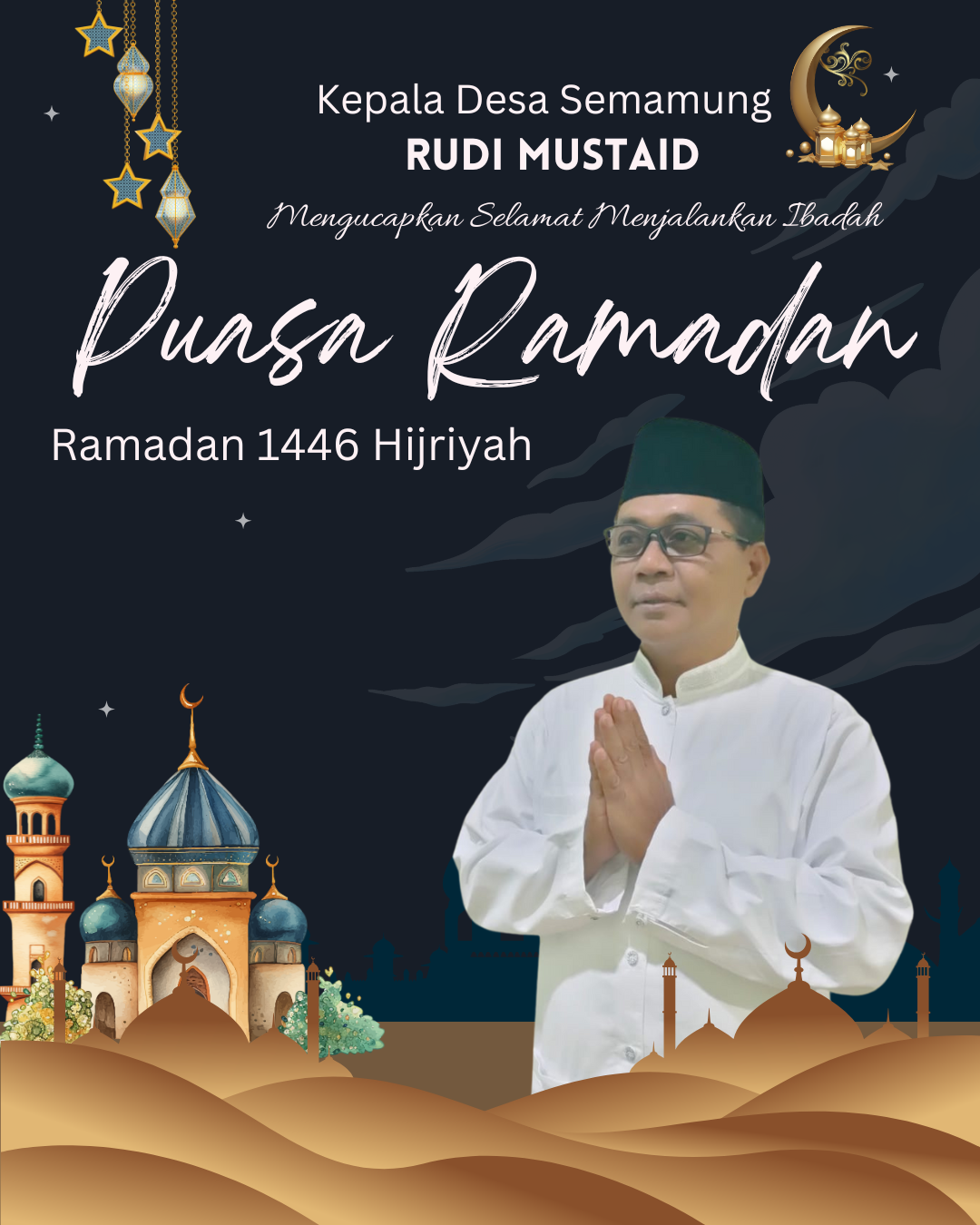Oleh [Egy Permana Putra]
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Sumbawa-Nijang)
Setiap 24 September, bangsa ini kembali disapa oleh sebuah ingatan kolektif: Hari Tani Nasional. Ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk menengok kembali akar peradaban kita—bertani. Nenek moyang bangsa ini adalah petani, bukan sekadar pemburu atau peramu. Dari tangan merekalah, peradaban nusantara bertumbuh, anak-anak bangsa dibesarkan, dan kekayaan alam dipertaruhkan hingga menjadi alasan kolonialisme yang panjang.
Namun, di Hari Tani Nasional 2025 ini, satu pertanyaan kembali menggema: benarkah nasib petani telah menjadi pusat perhatian, ataukah mereka hanya menjadi catatan kaki dalam pidato tahunan yang cepat dilupakan?
Janji swasembada pangan yang bergema sejak Orde Baru hingga kini, nyatanya masih sering kandas. Kemandirian pangan belum juga terwujud, sementara ketergantungan pada impor terus berlanjut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga Juli 2025, impor beras tetap tinggi, disusul gandum yang hampir 100% diimpor dan bawang putih yang masih membanjiri pasar lokal. Ketergantungan ini bukan sekadar masalah perdagangan, melainkan soal keberlangsungan hidup petani.
Kebijakan pangan sering kali tidak berpihak pada petani kecil. Salah satu contoh nyata adalah kebijakan impor yang kerap dilakukan saat musim panen, membuat harga komoditas lokal anjlok. Petani seakan terjebak dalam lingkaran setan: biaya produksi tinggi, hasil panen murah, dan perlindungan dari negara pun setengah hati. Akarnya jelas: pertanian tidak menjadi fondasi dalam perencanaan pembangunan nasional.
Dalam situasi ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo muncul sebagai kebijakan strategis yang layak diperhatikan. Program ini menjanjikan makan bergizi bagi jutaan anak setiap harinya, sekaligus membuka peluang bagi tumbuhnya pasar domestik pangan lokal. Jika dijalankan dengan tepat, MBG bisa menjadi mesin permintaan raksasa yang memicu peningkatan produksi, distribusi, dan kesejahteraan petani.
Namun, peluang ini tidak datang tanpa ancaman. Mari kita ambil contoh Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jika terdapat 50 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masing-masing melayani 3.500 porsi per hari (Senin–Sabtu), maka akan ada 175.000 porsi disajikan setiap hari. Dengan estimasi kebutuhan 90 gram sayuran per porsi, maka kebutuhan harian mencapai 15,75 ton sayur, atau sekitar 409,5 ton per bulan—hanya untuk satu kabupaten.
Volume sebesar ini dapat menimbulkan disrupsi serius terhadap rantai pasok tradisional. Pemerintah bisa menjadi pembeli tunggal (monopsoni) yang mendominasi pasar. Ini berpotensi menggeser peran tengkulak dan pedagang pasar tradisional—yang selama ini, suka tidak suka, memainkan peran penting dalam menyerap hasil petani kecil.
Persoalannya menjadi lebih pelik jika pasokan untuk program MBG justru tidak berasal dari petani lokal, melainkan didatangkan dari luar daerah seperti Jawa, Bali, atau bahkan impor terselubung. Alih-alih memberdayakan petani setempat, program ini malah bisa menyisihkan mereka dari pasar di kampung sendiri. Tidak hanya itu, logistik antardaerah juga akan memperbesar jejak karbon dan pemborosan energi.
Yang juga perlu diwaspadai adalah lemahnya partisipasi petani dalam perencanaan teknis program MBG. Selama ini, petani kerap menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Serikat petani, koperasi desa, dan lembaga lokal harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, bukan hanya diminta “ikut serta” di ujung eksekusi. Tanpa keterlibatan mereka, program ini akan kehilangan keberpihakan sosial yang seharusnya menjadi rohnya.
Ada pula masalah struktural yang membayangi: alih fungsi lahan. Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan laju konversi lahan pertanian produktif di Indonesia mencapai 100–150 ribu hektar per tahun. Di NTB dan daerah penyangga pangan lainnya, tekanan ini semakin kuat. Tanpa proteksi yang tegas terhadap lahan pangan berkelanjutan, seluruh upaya swasembada—termasuk MBG—akan runtuh di atas tanah yang tak lagi tersedia.
Hari Tani Nasional harus menjadi titik balik, bukan sekadar ajang nostalgia. Program MBG berpotensi menjadi berkah besar bagi pertanian nasional, tetapi juga bisa menjadi petaka jika salah kelola. Pemerintah harus memastikan keberpihakan kepada petani lokal, membangun sistem pasok yang adil dan transparan, serta menahan laju konversi lahan secara berani.
Yang terpenting, petani harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan—bukan hanya penyedia bahan mentah, tapi juga pengambil keputusan dan penerima manfaat.
Indonesia terlalu besar untuk bergantung pada pangan impor. Tapi negeri ini juga terlalu kaya untuk membiarkan petaninya hidup dalam kemiskinan.
Selamat Hari Tani Nasional. Saatnya petani berdaulat atas tanah, pangan, dan masa depannya sendiri.