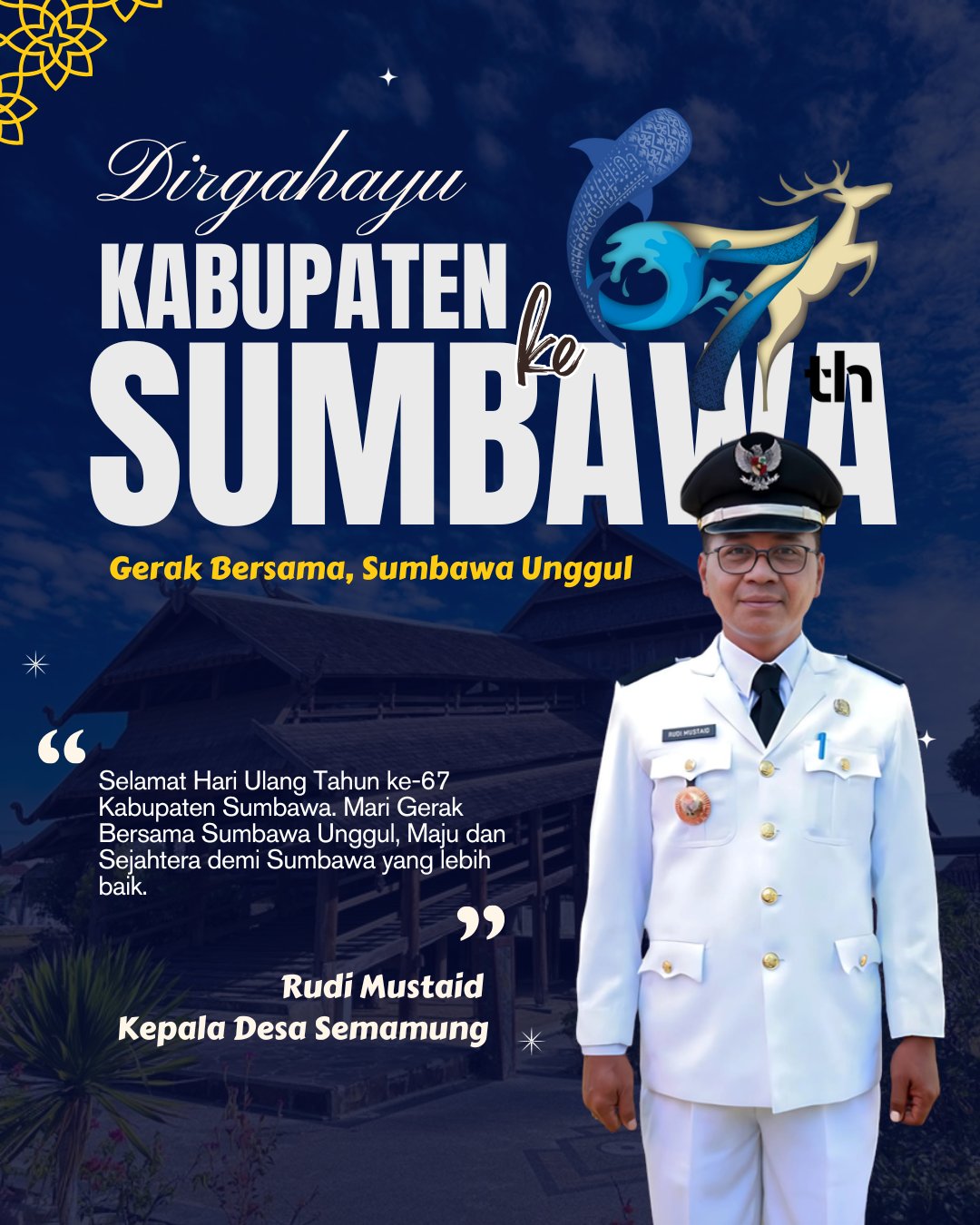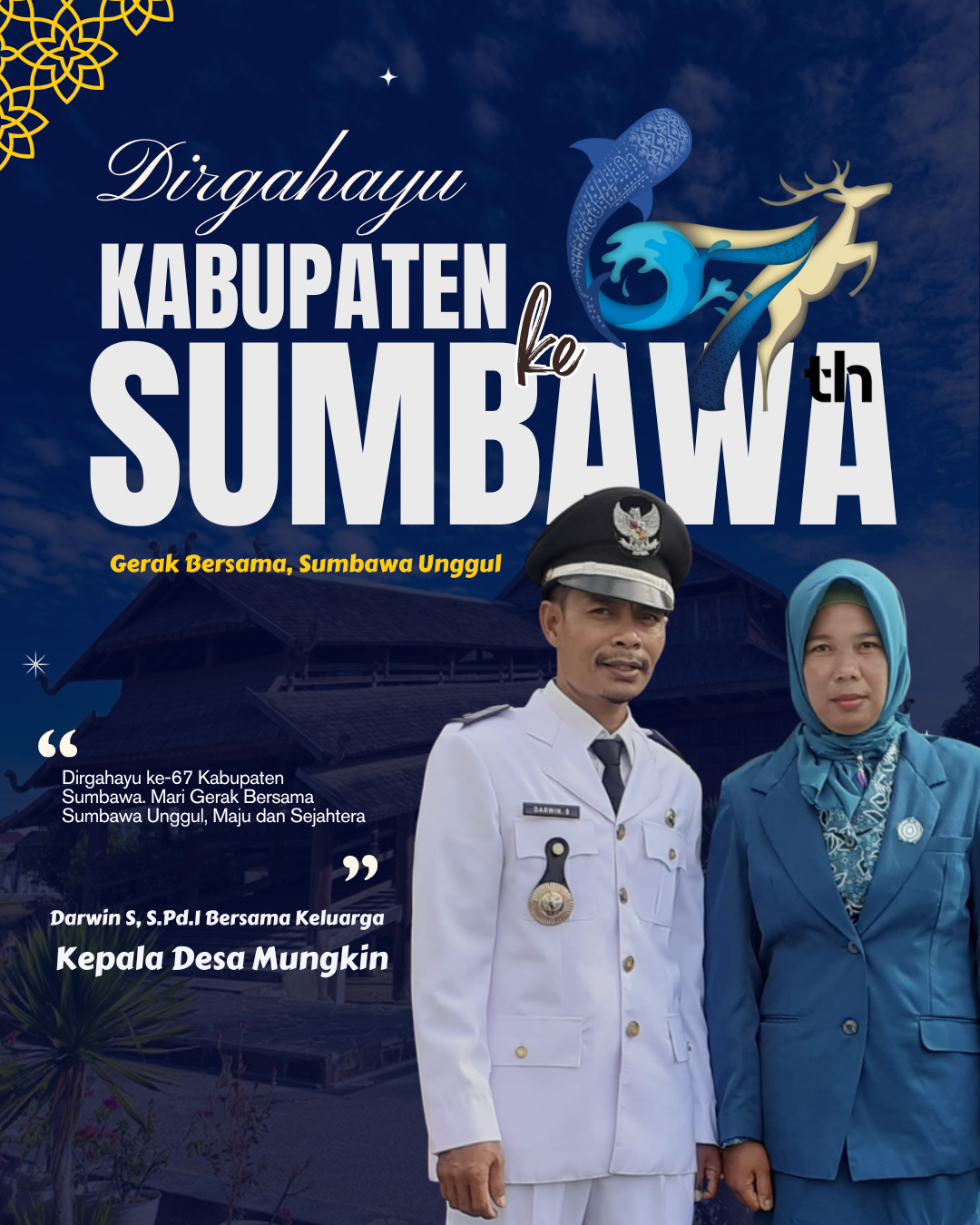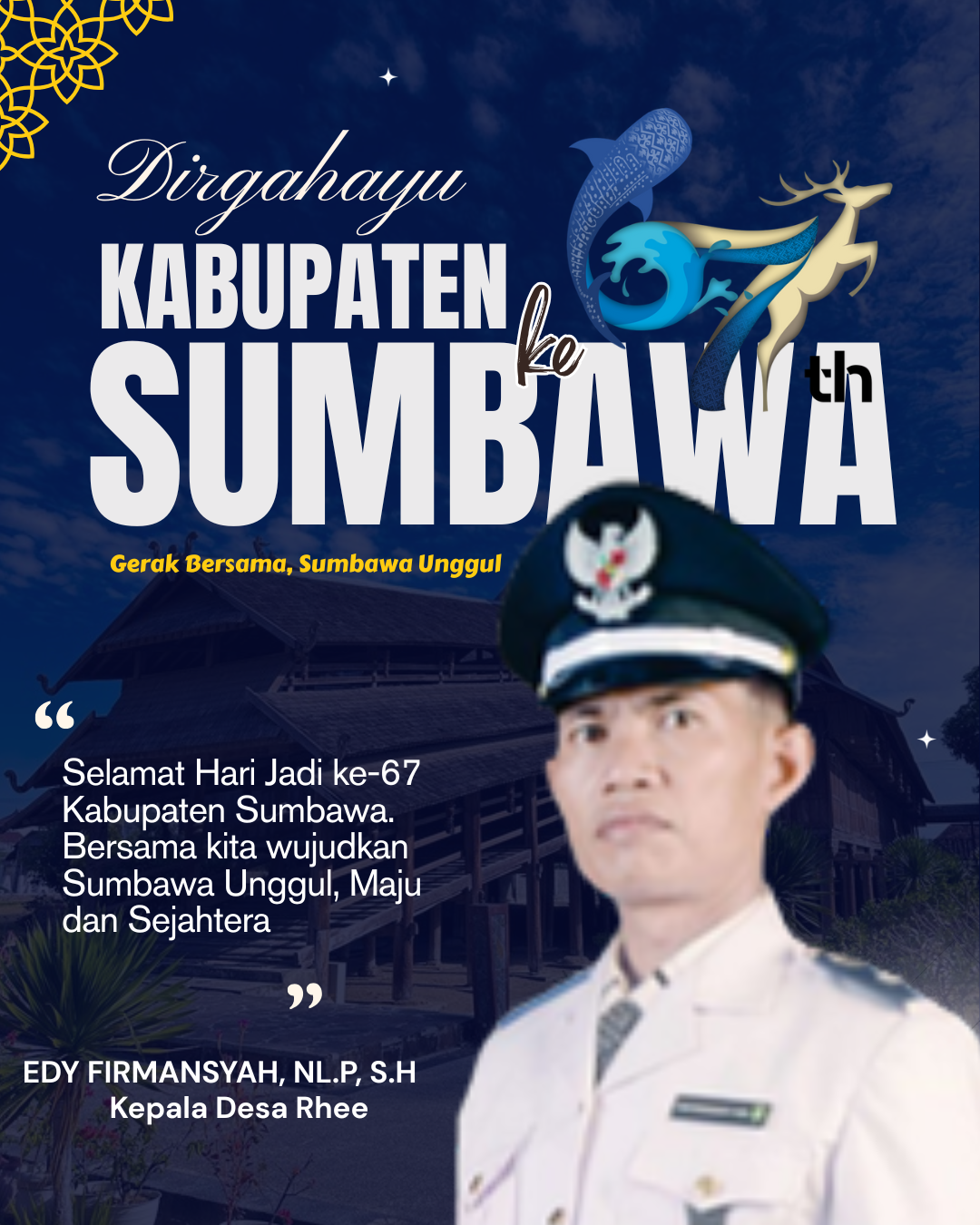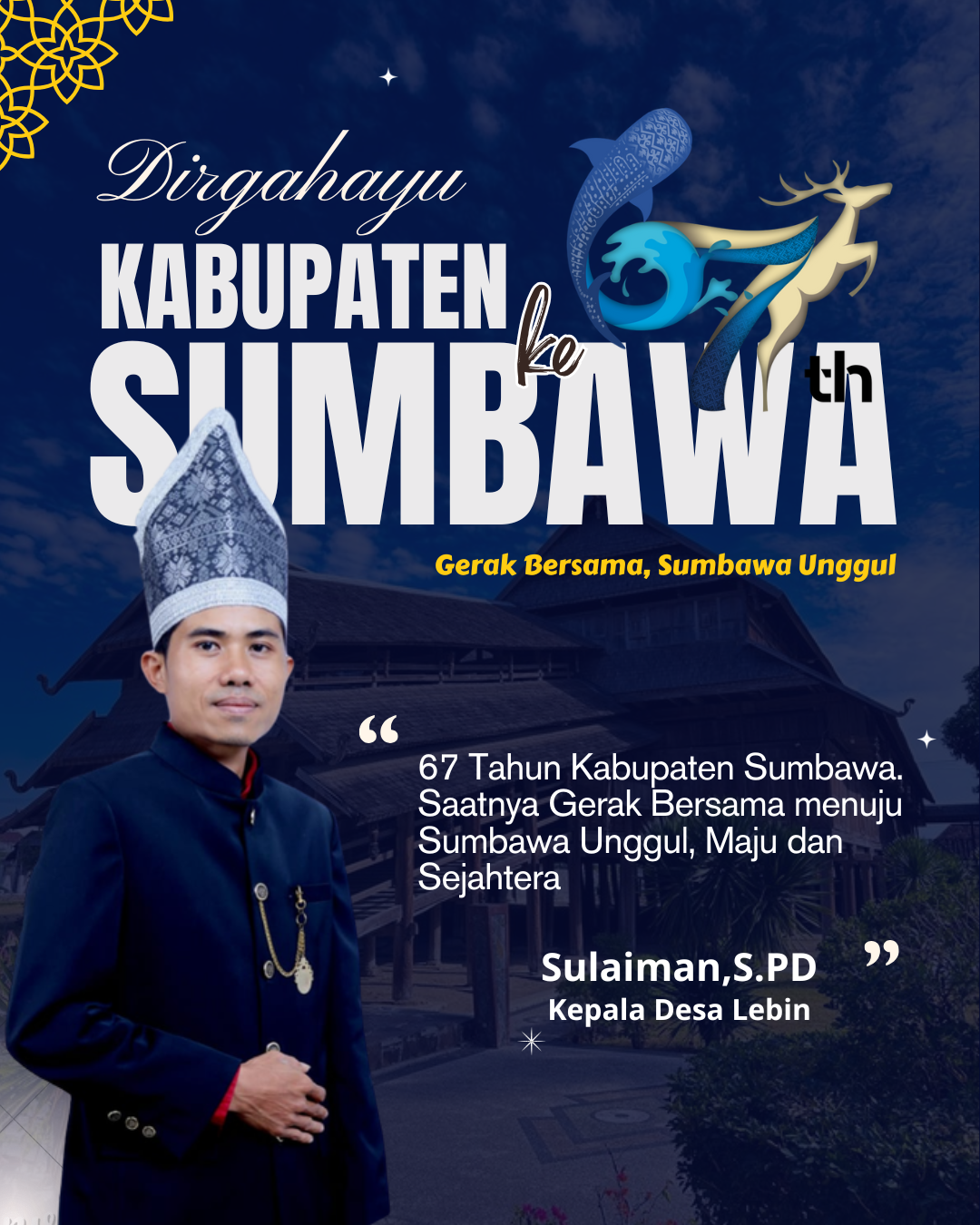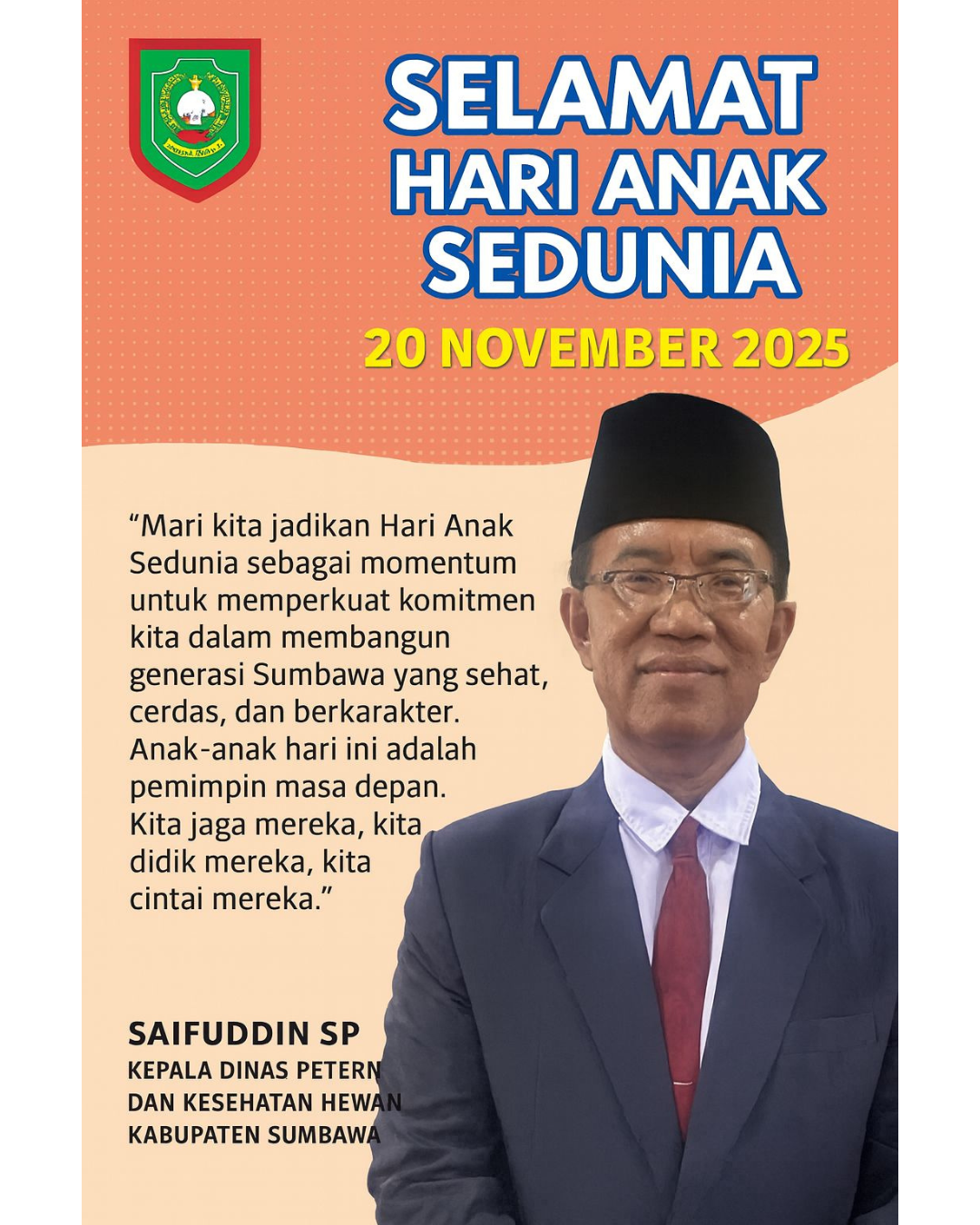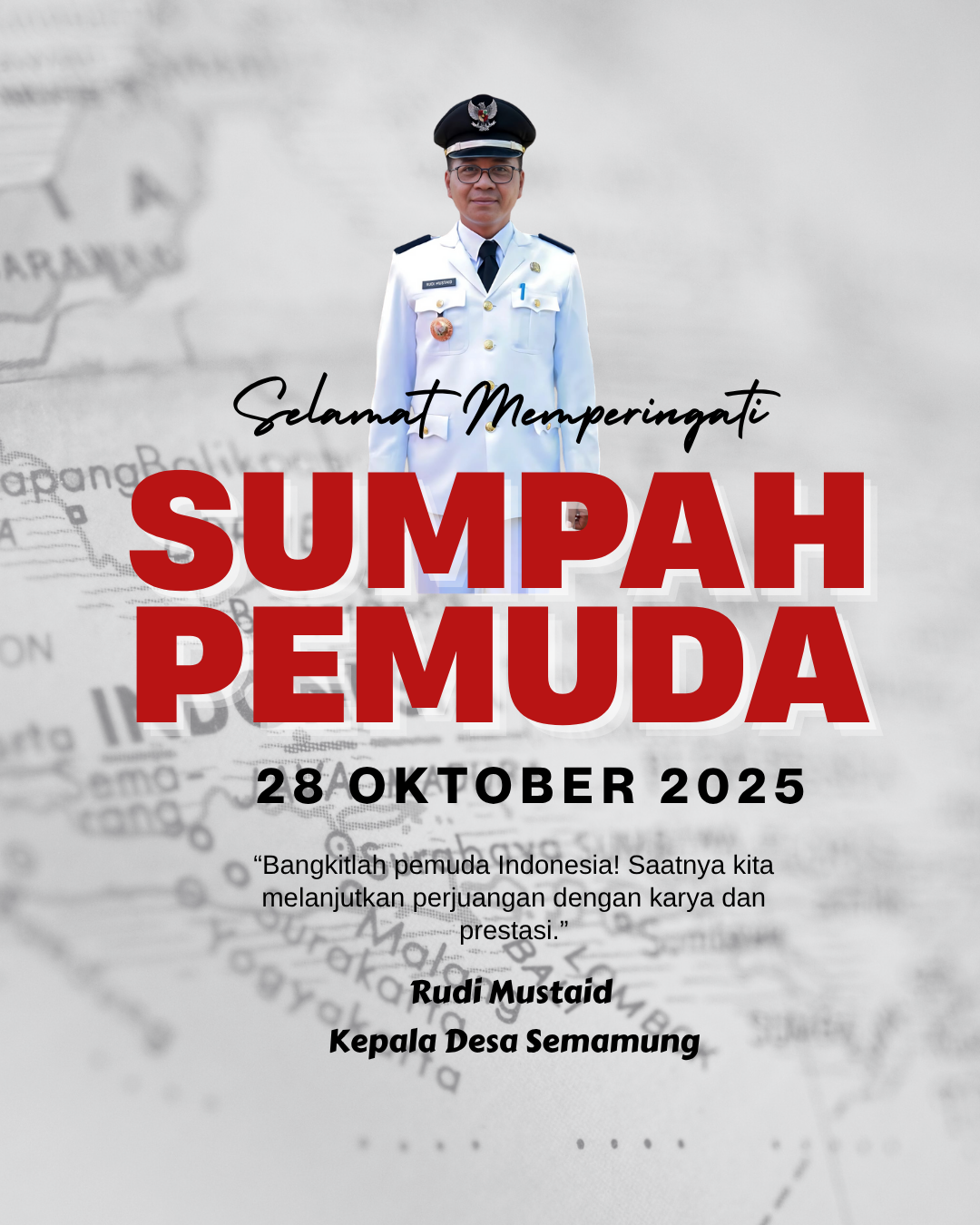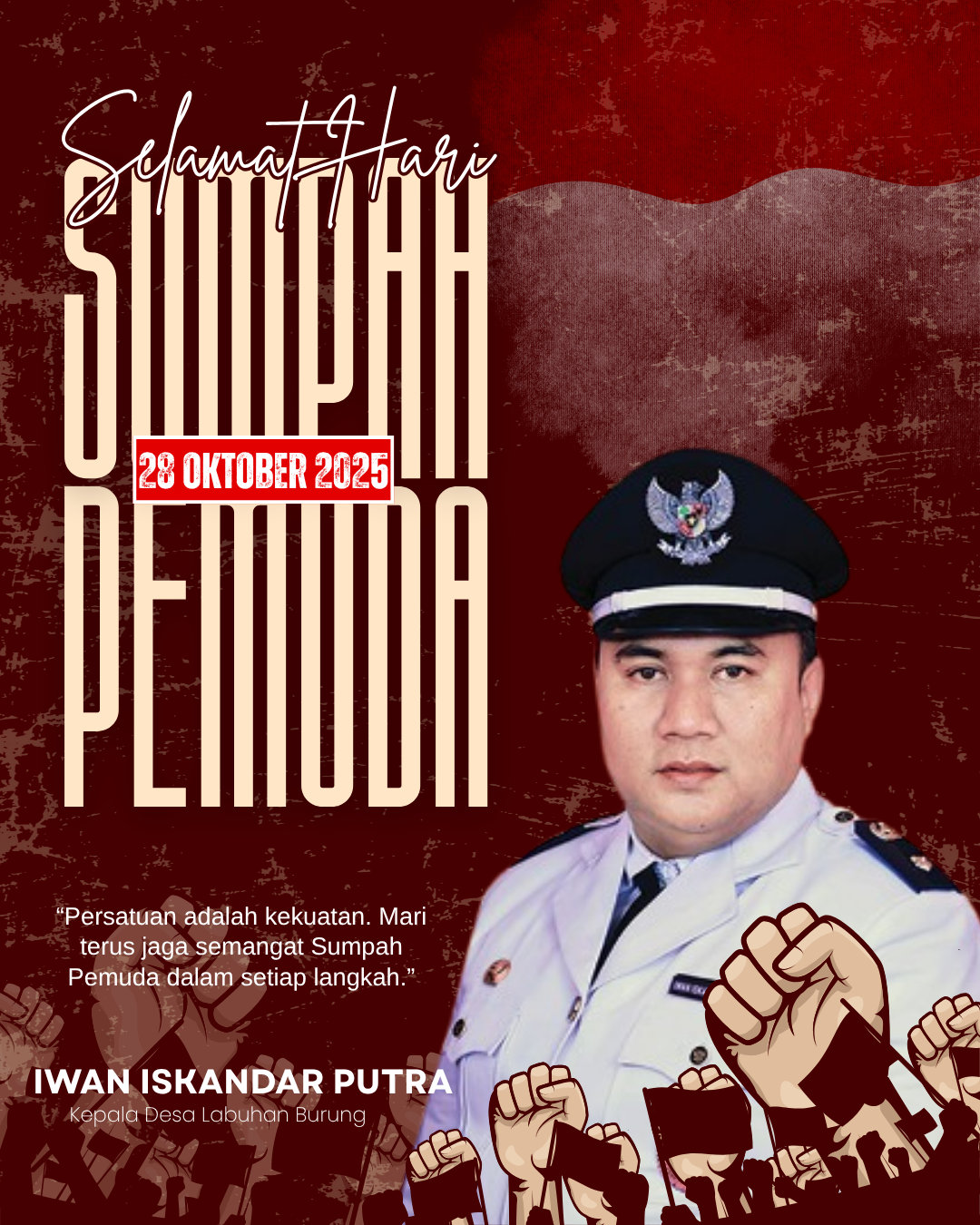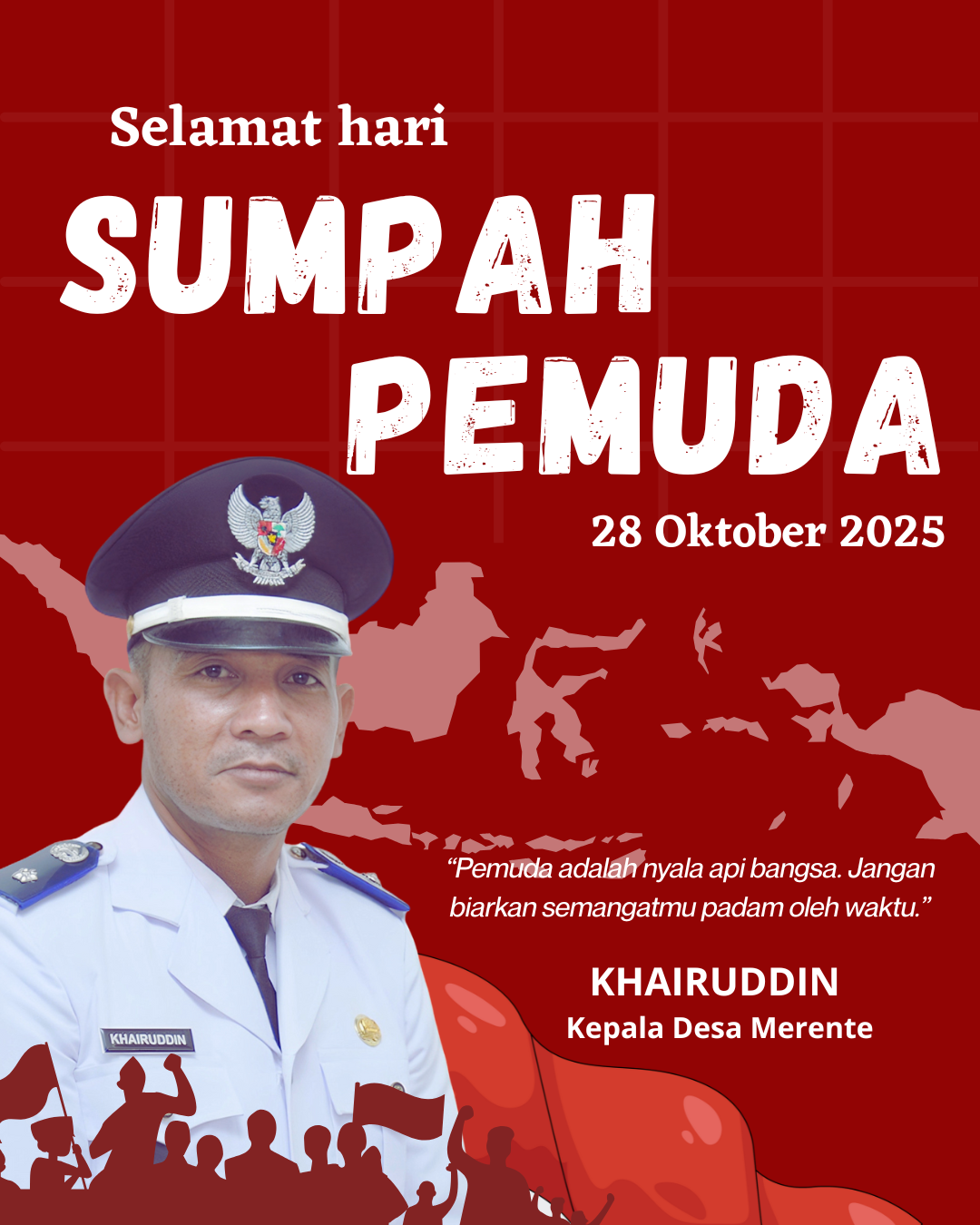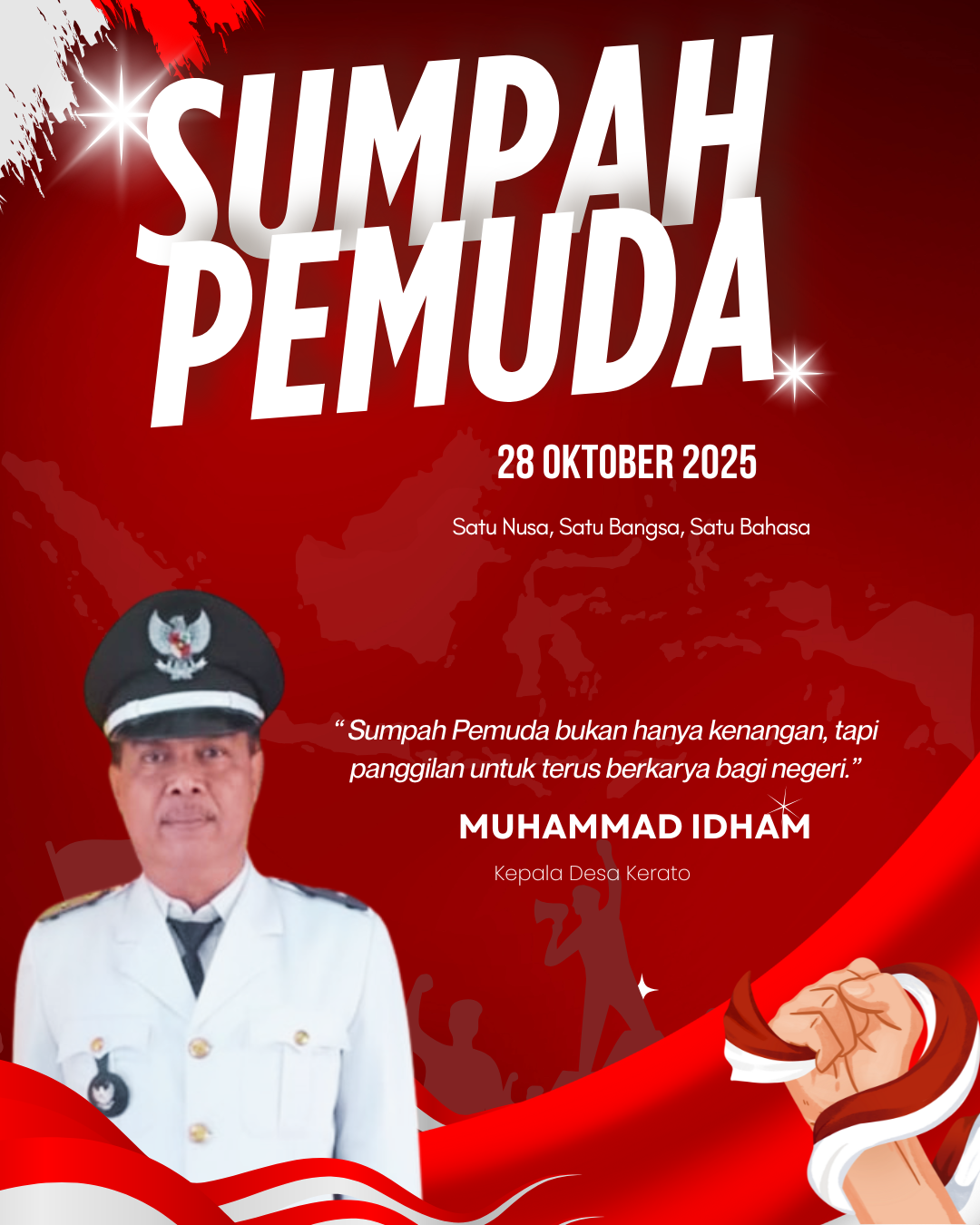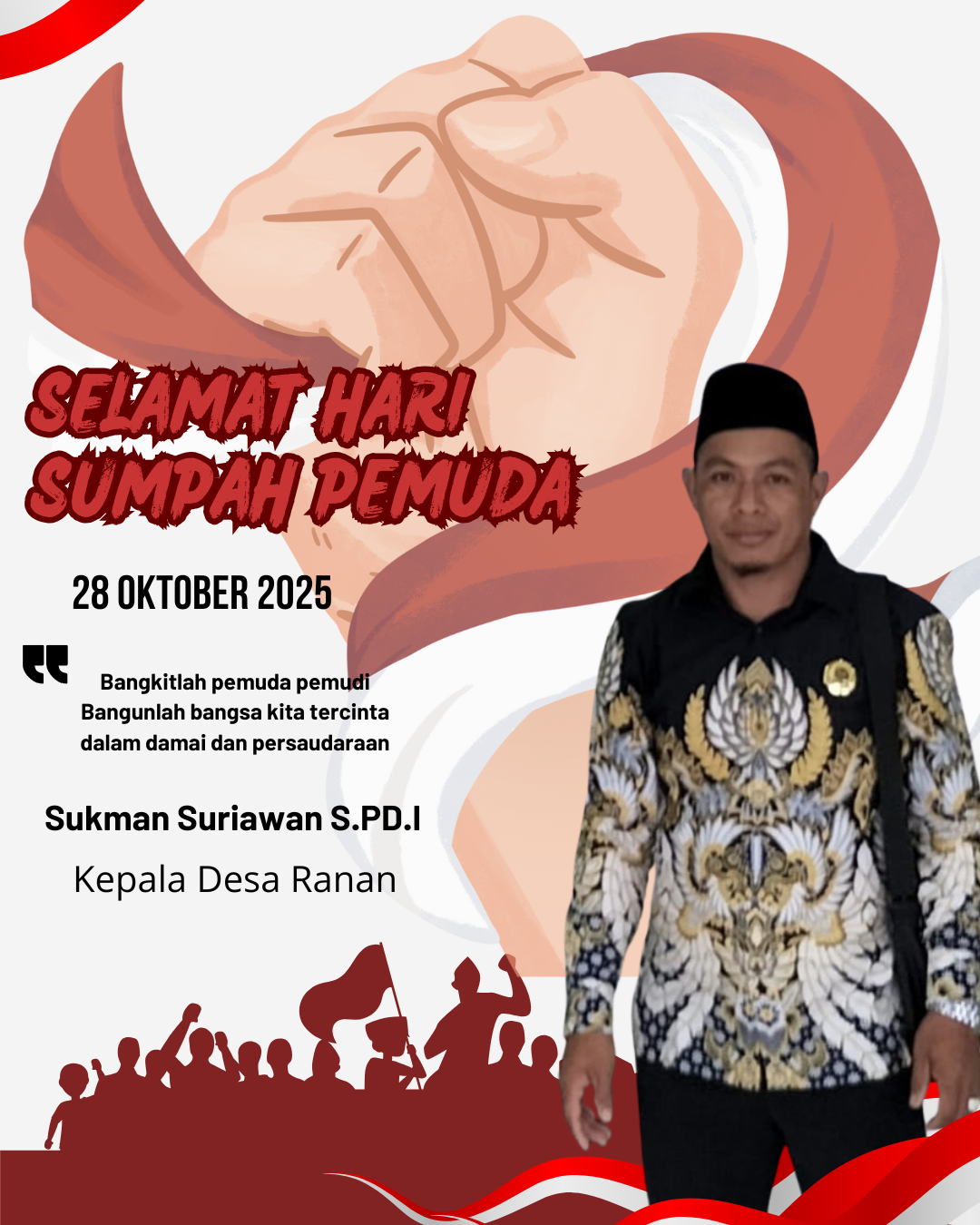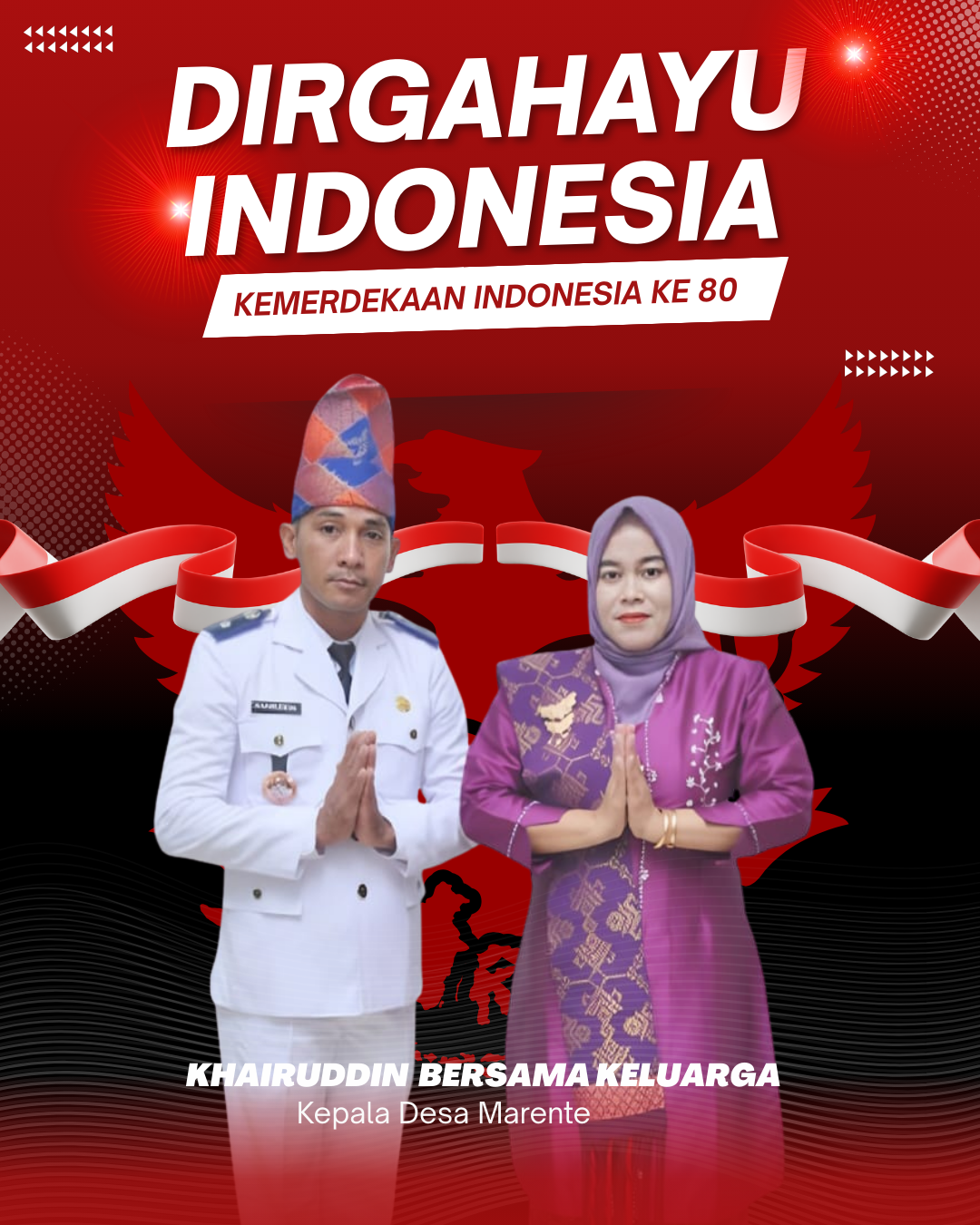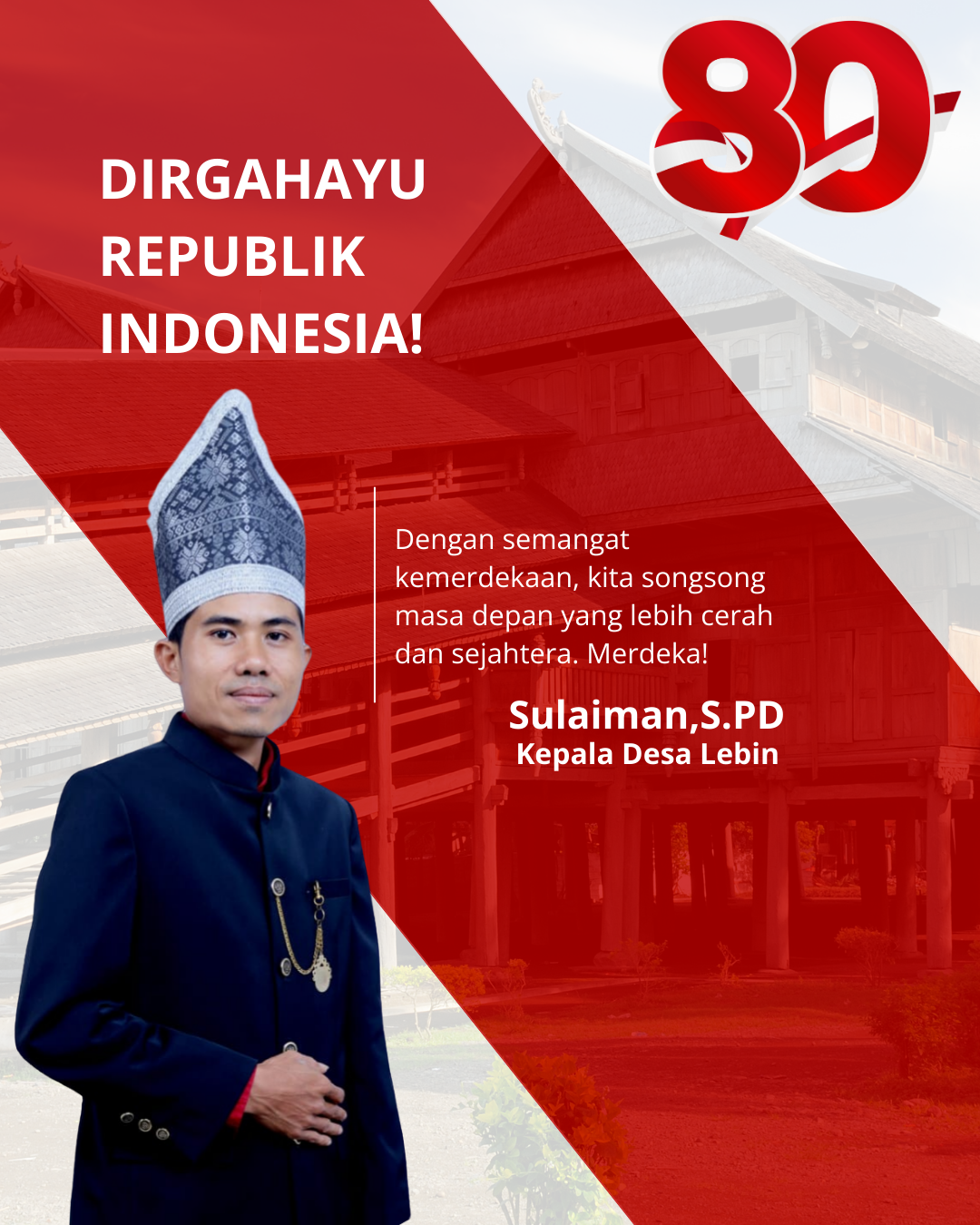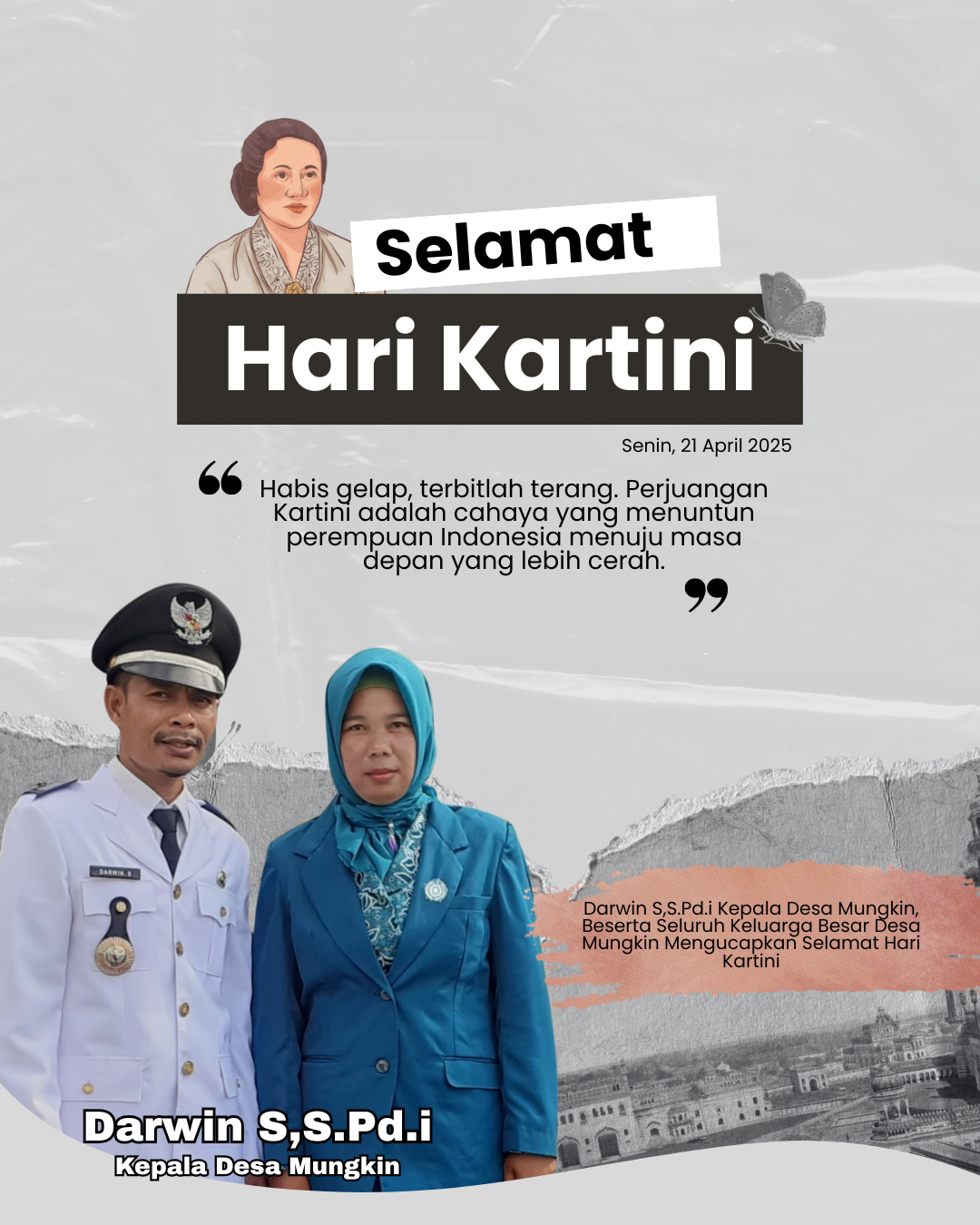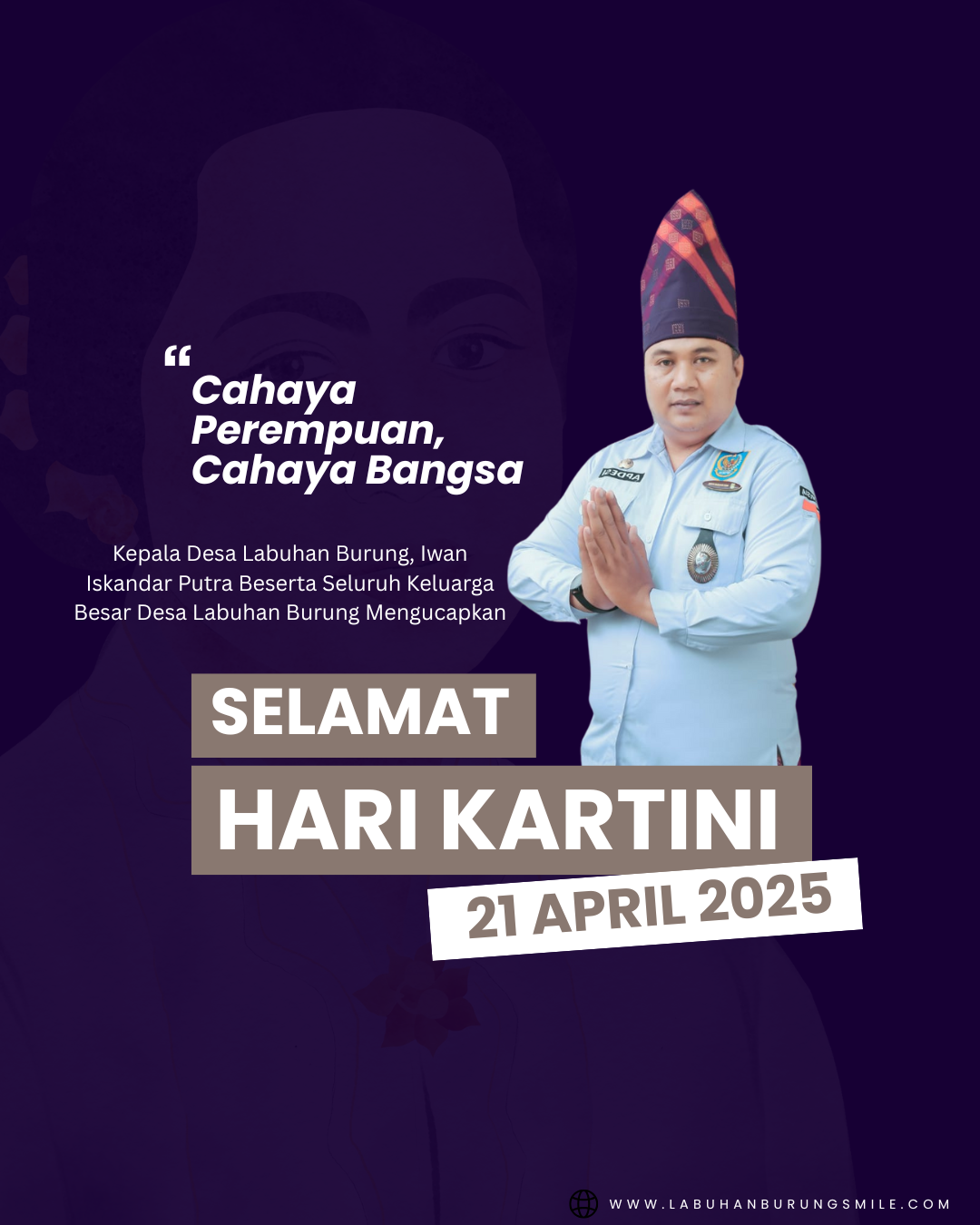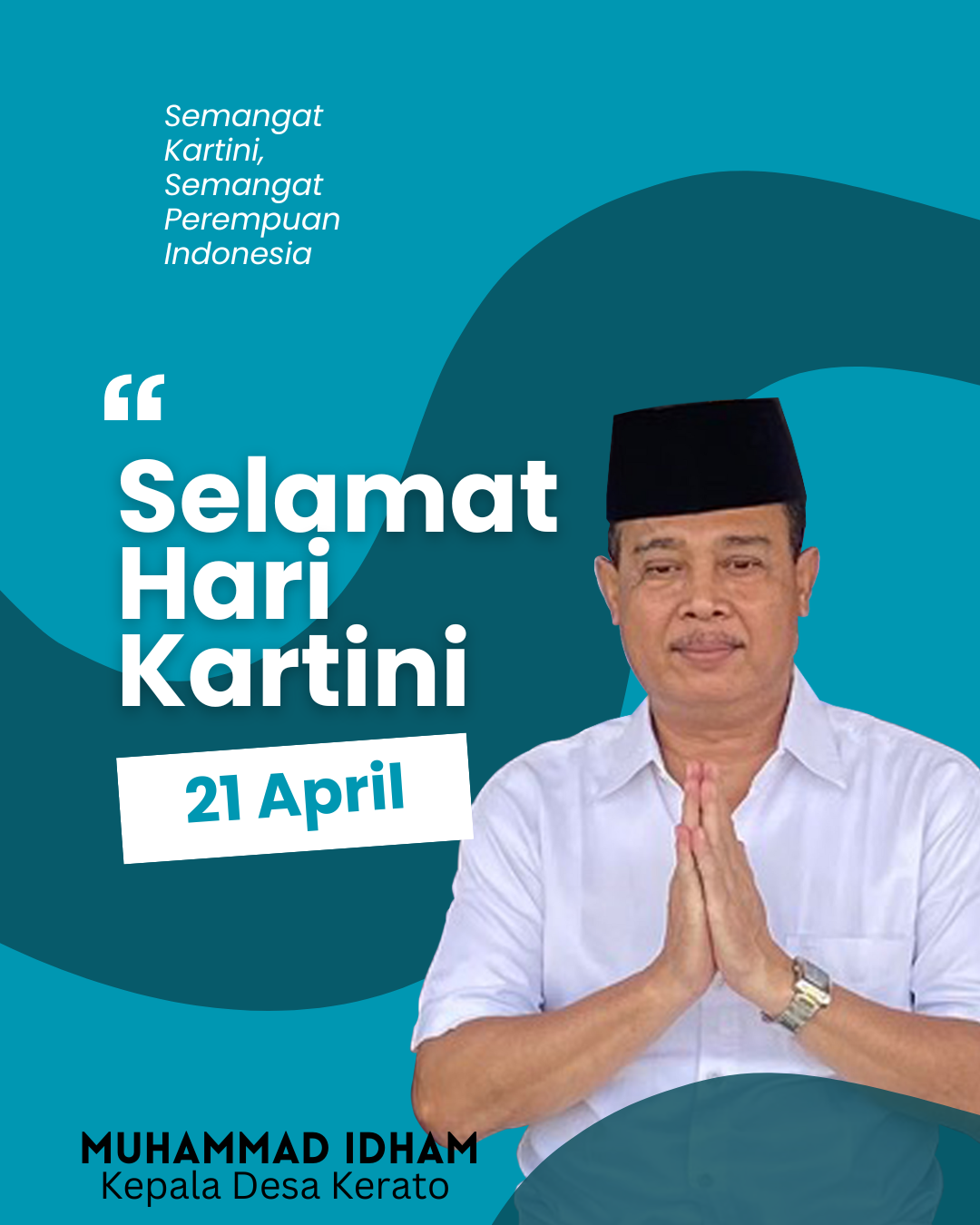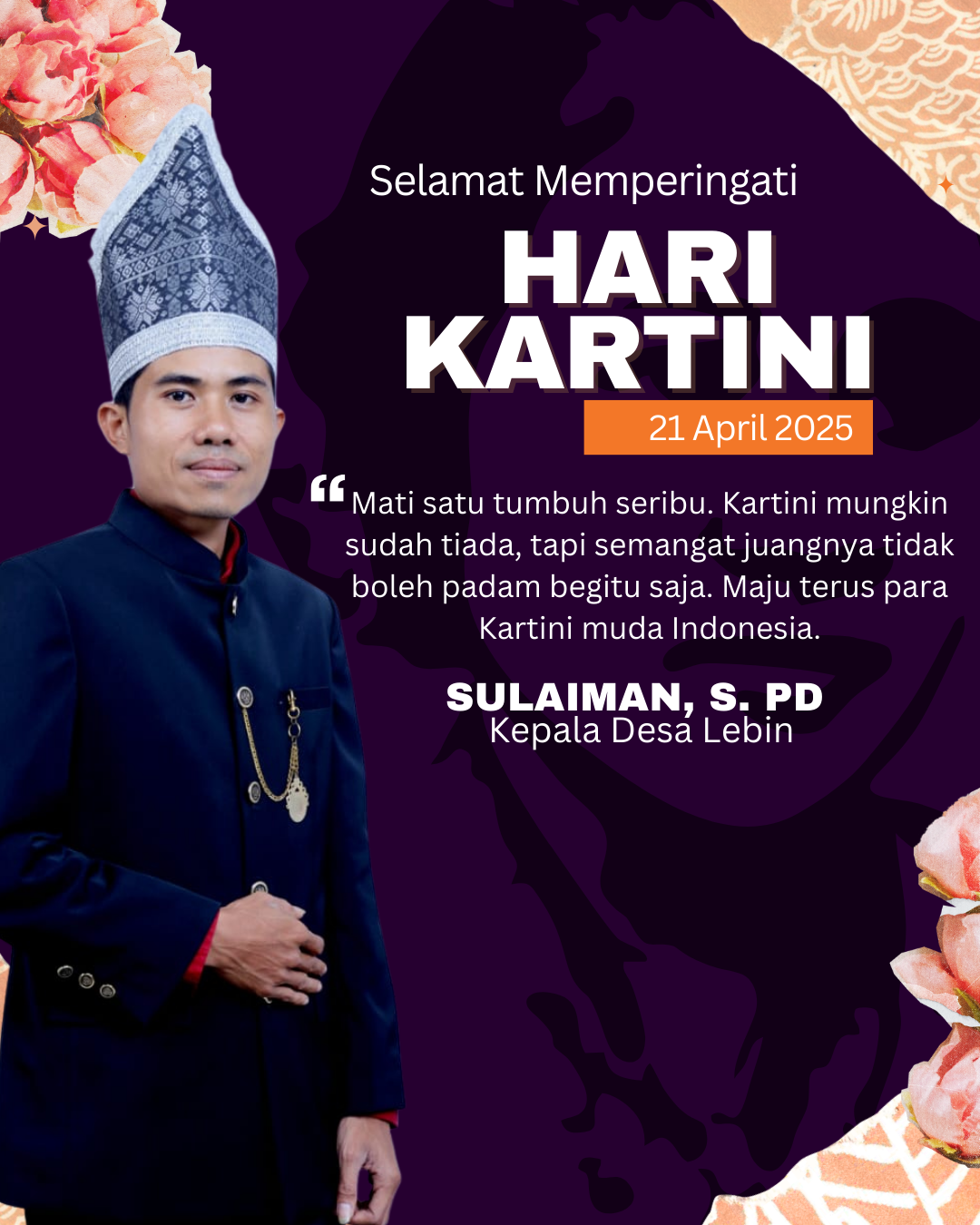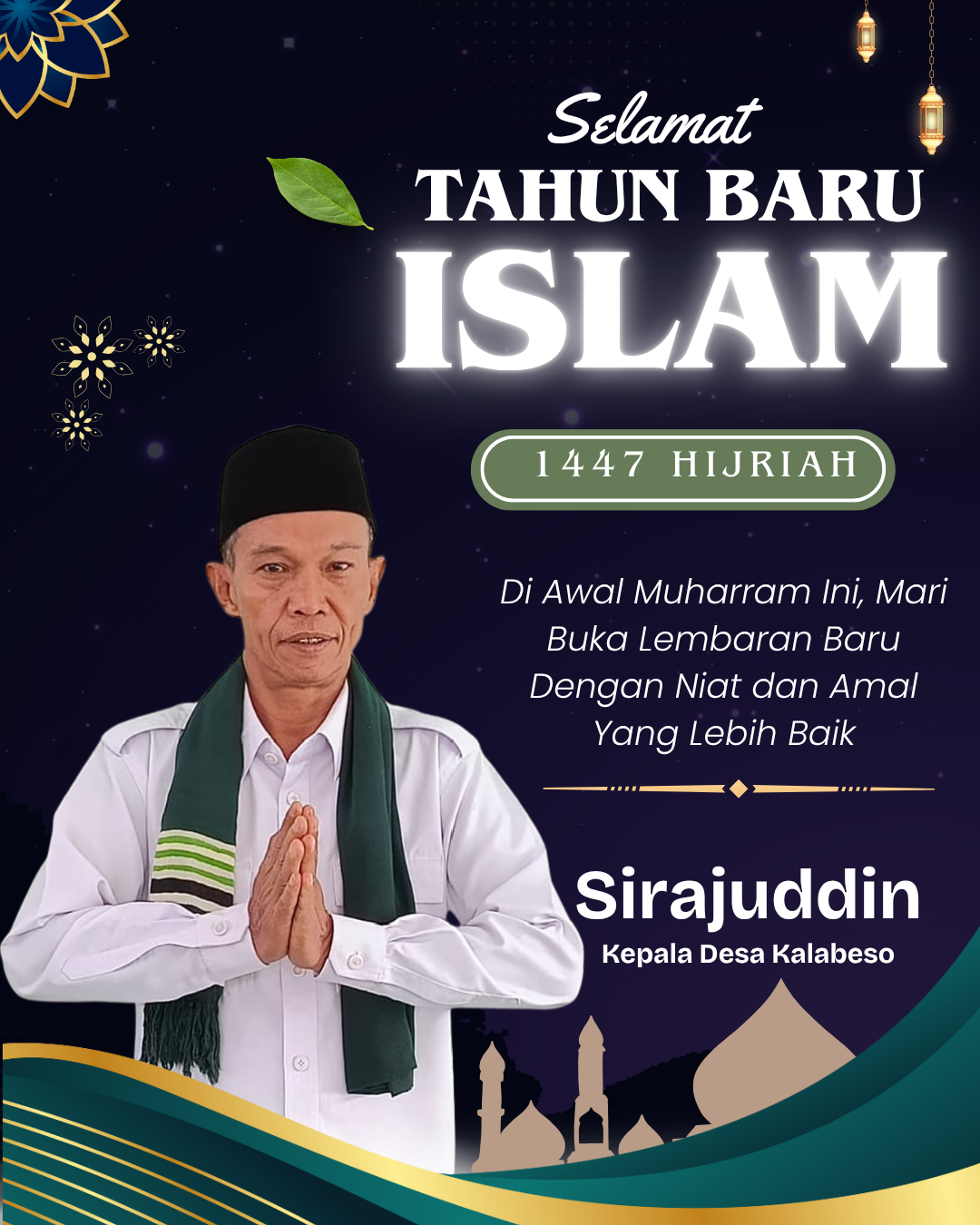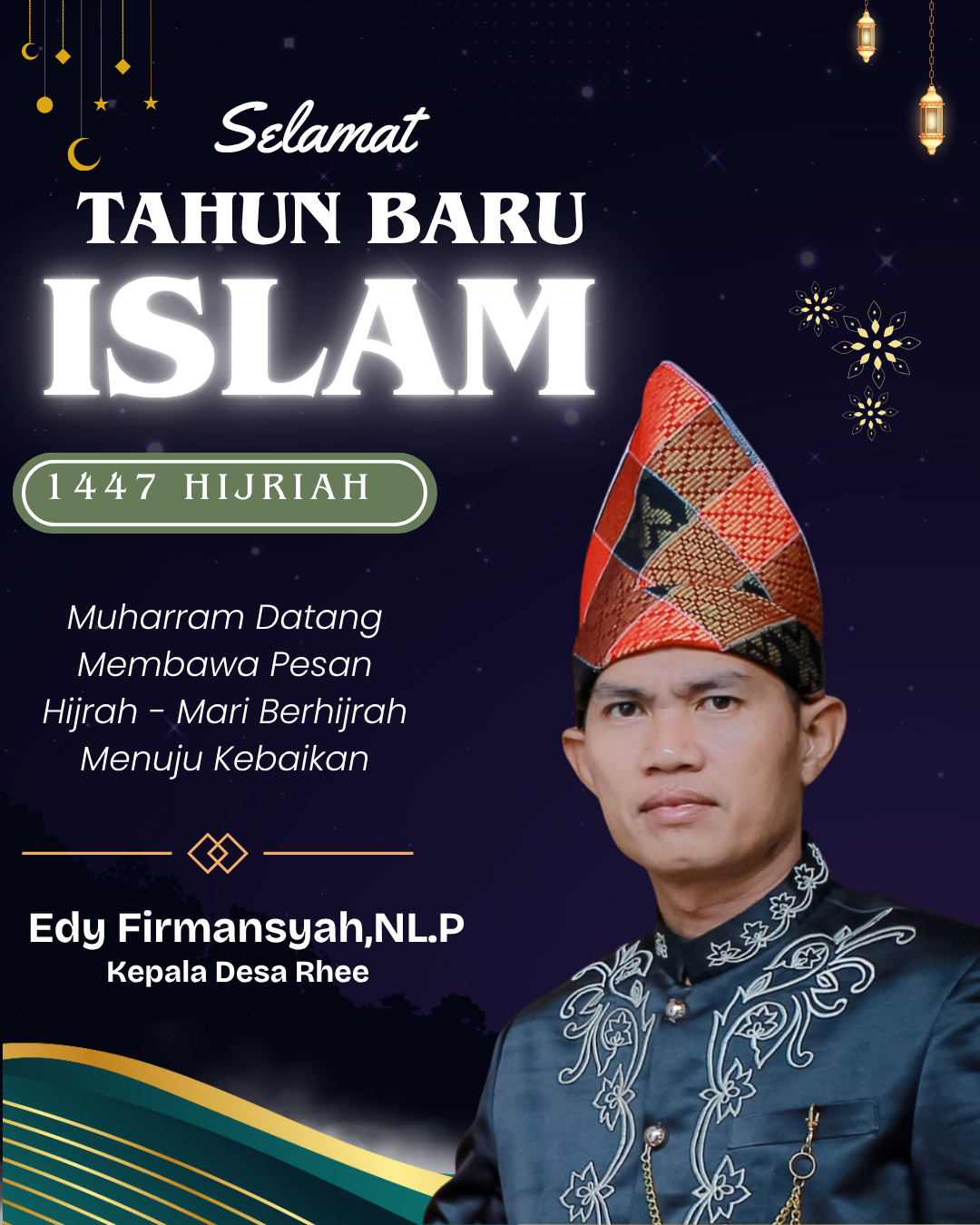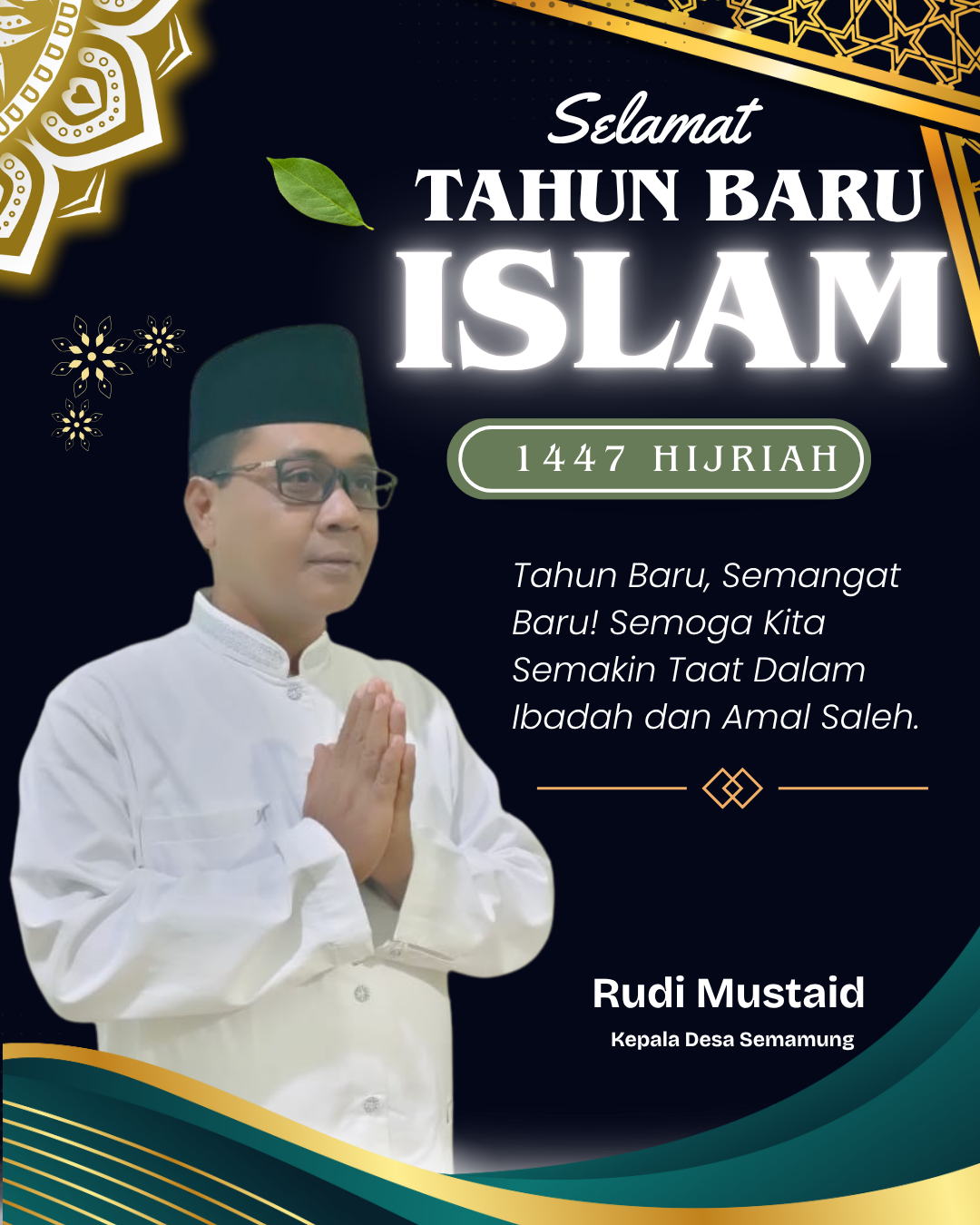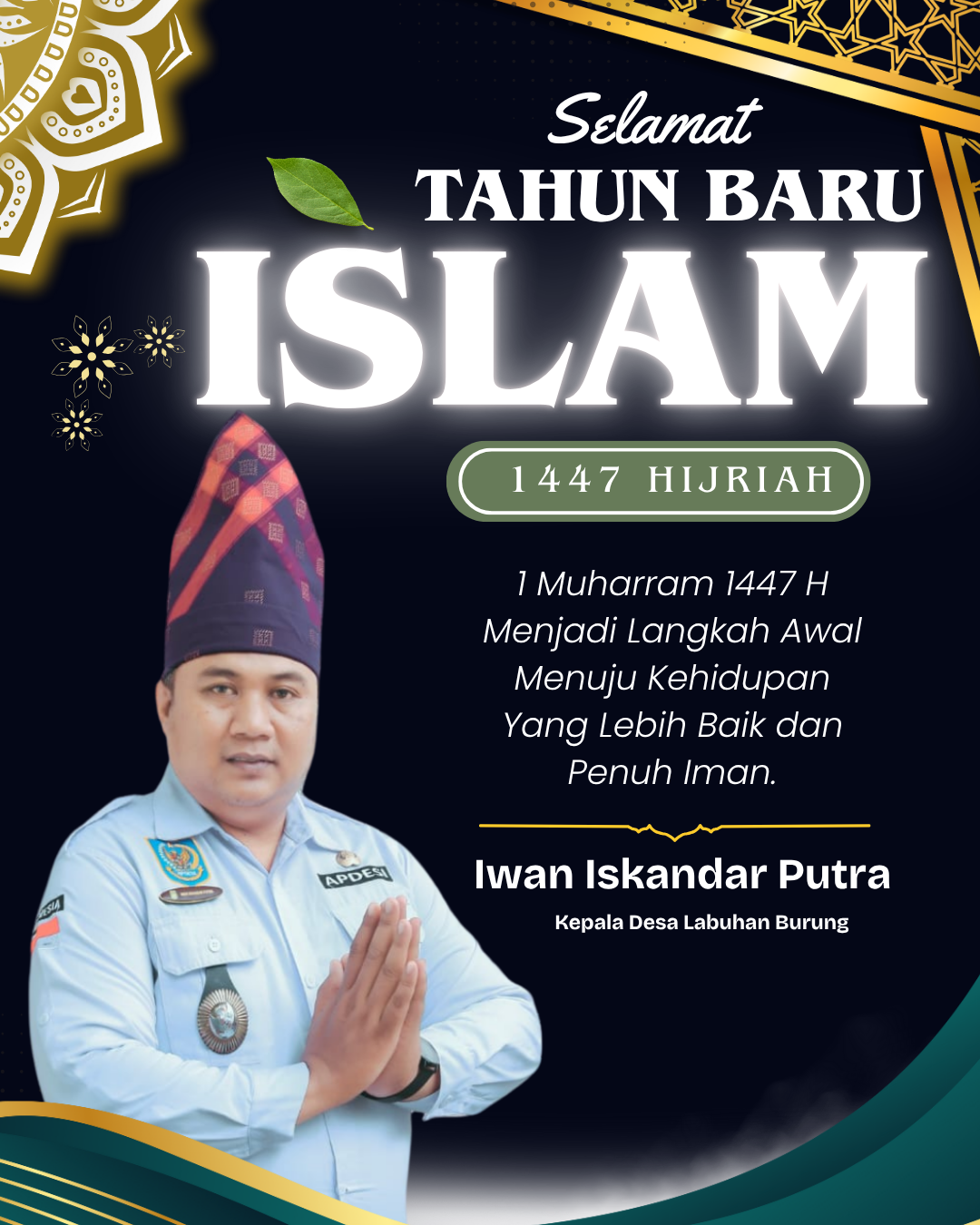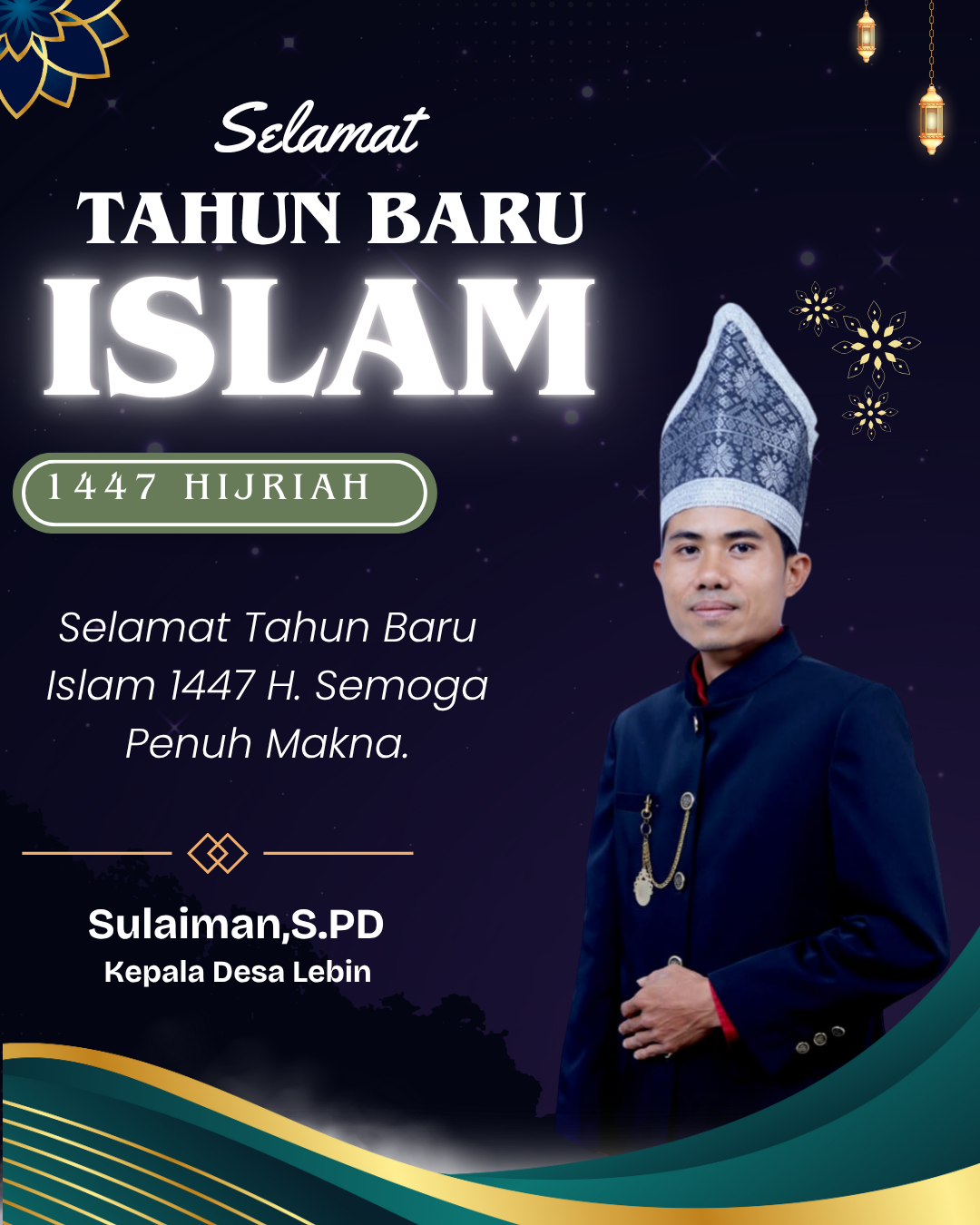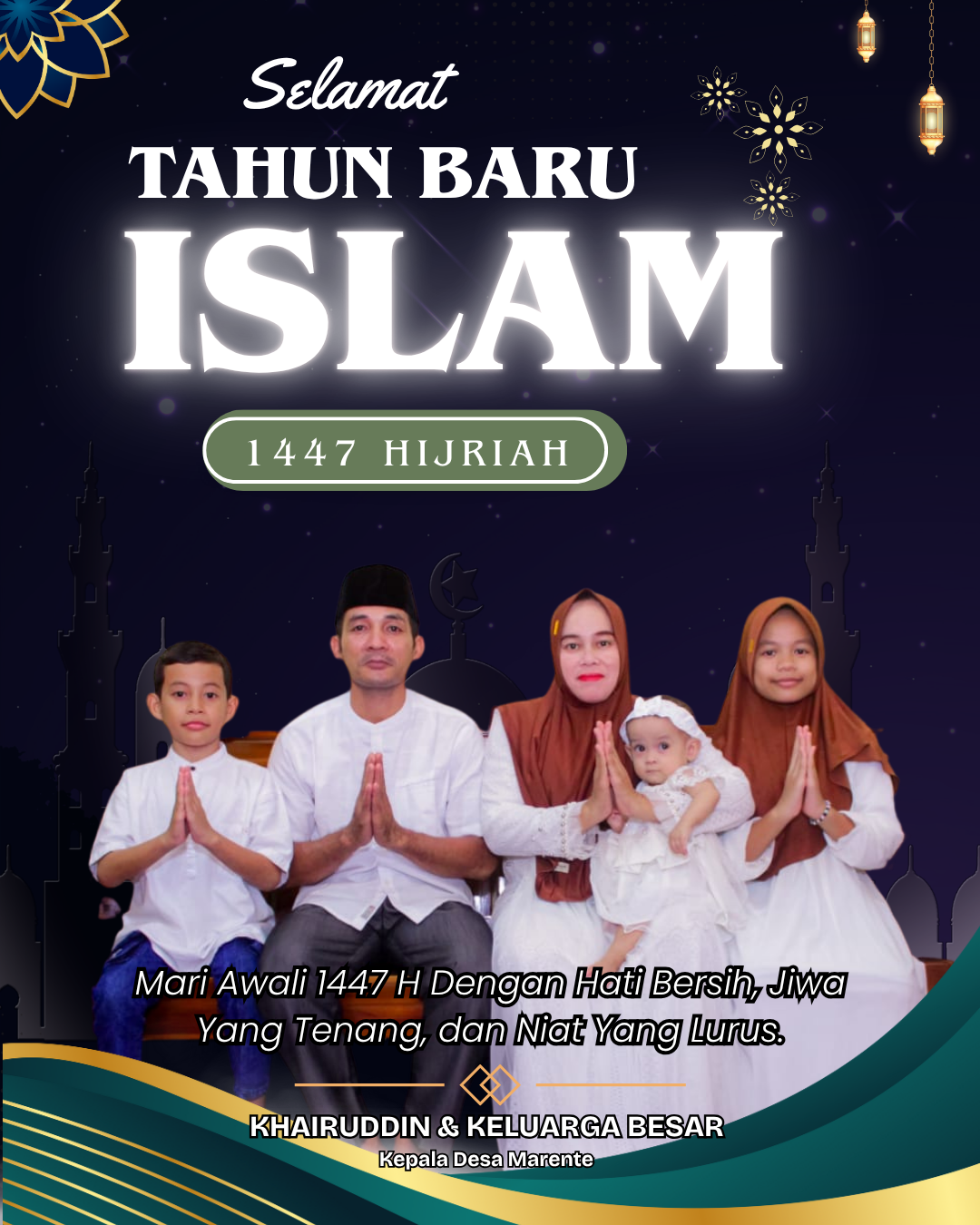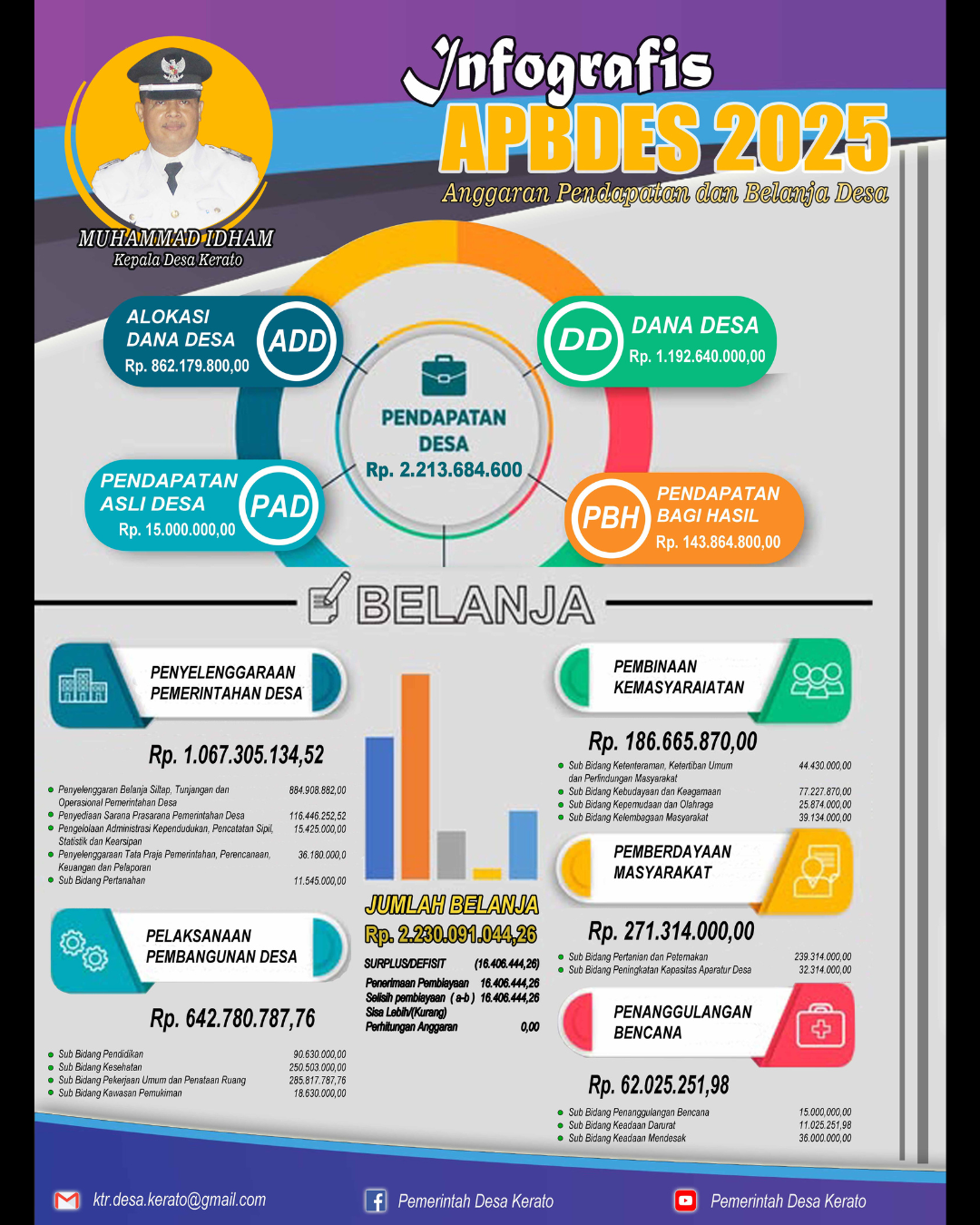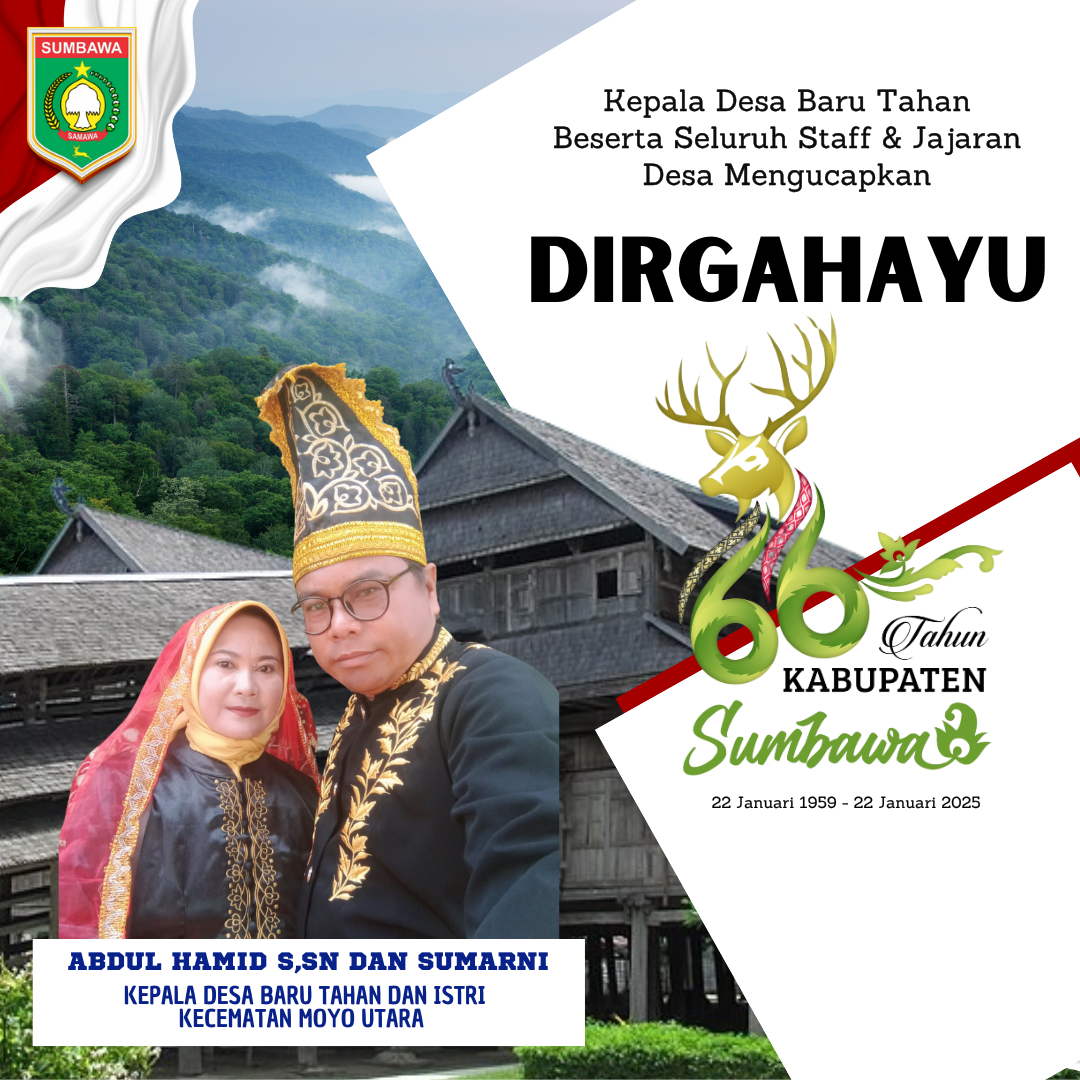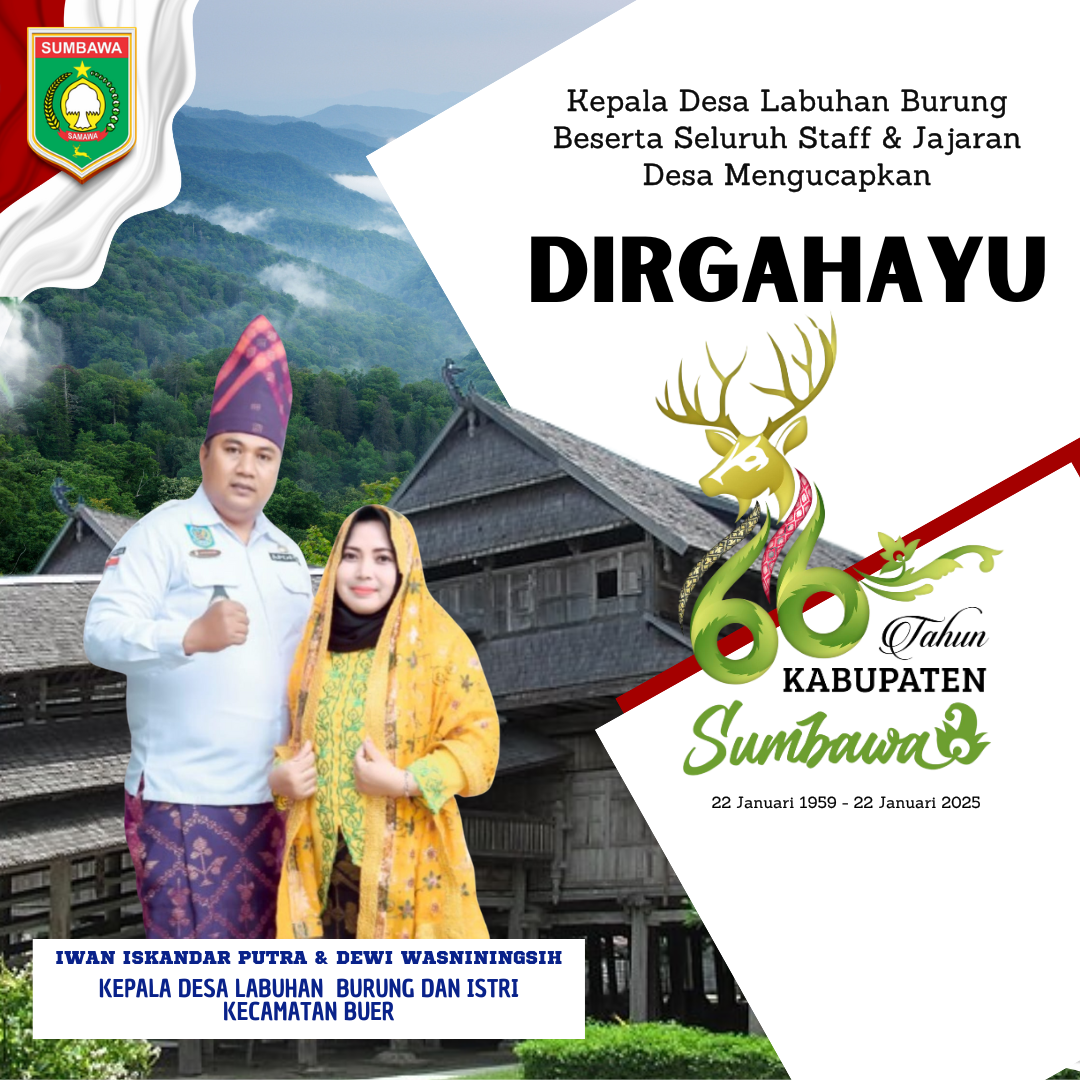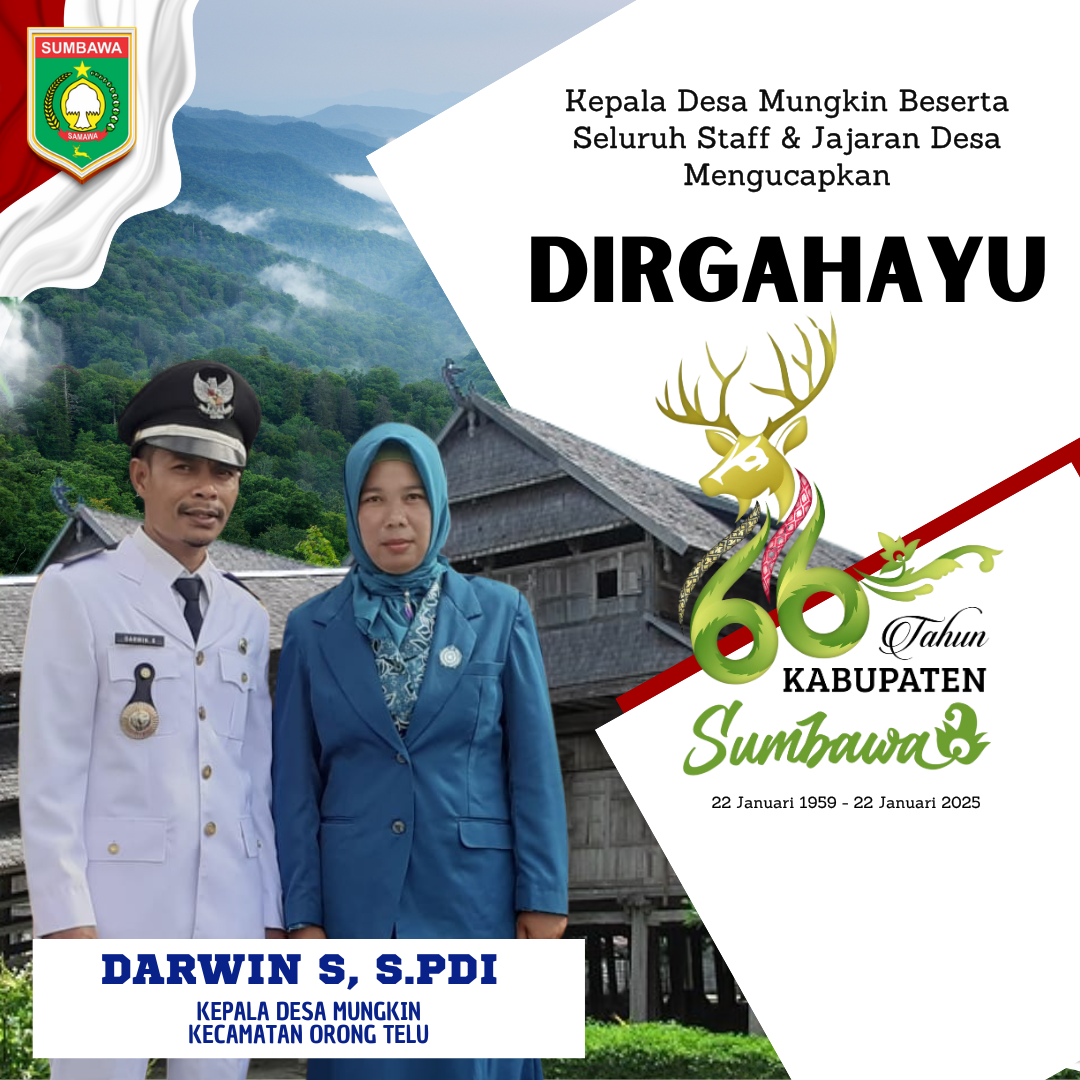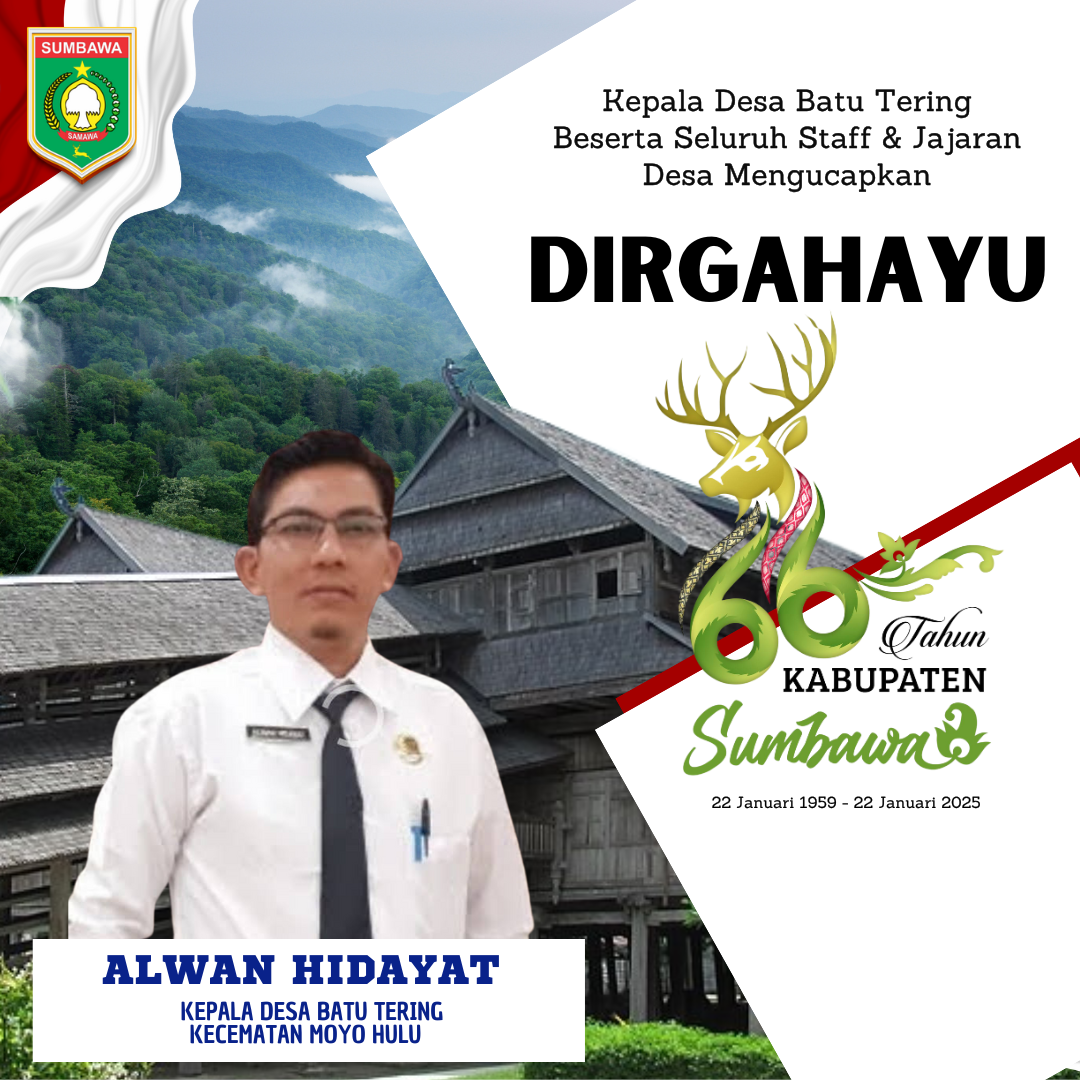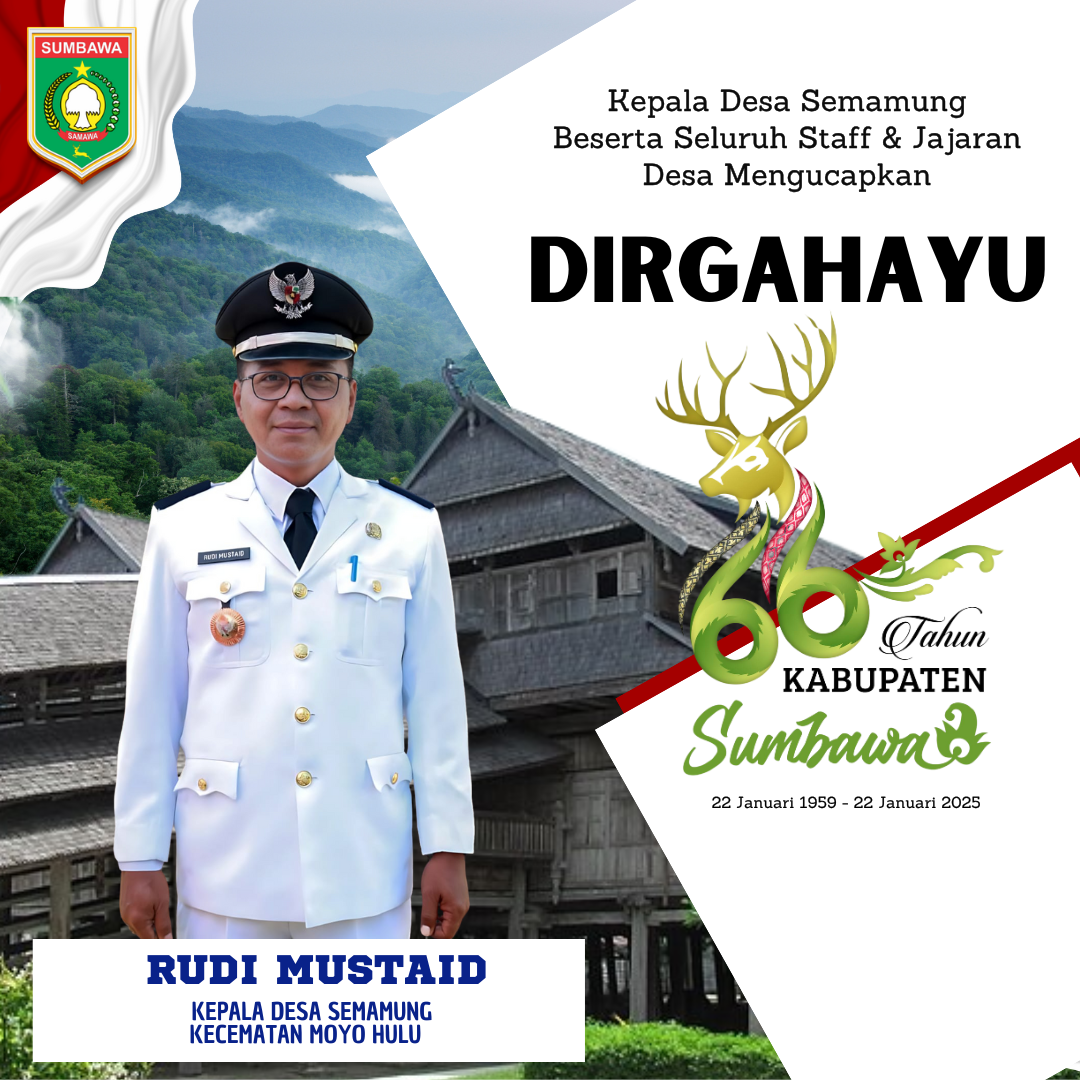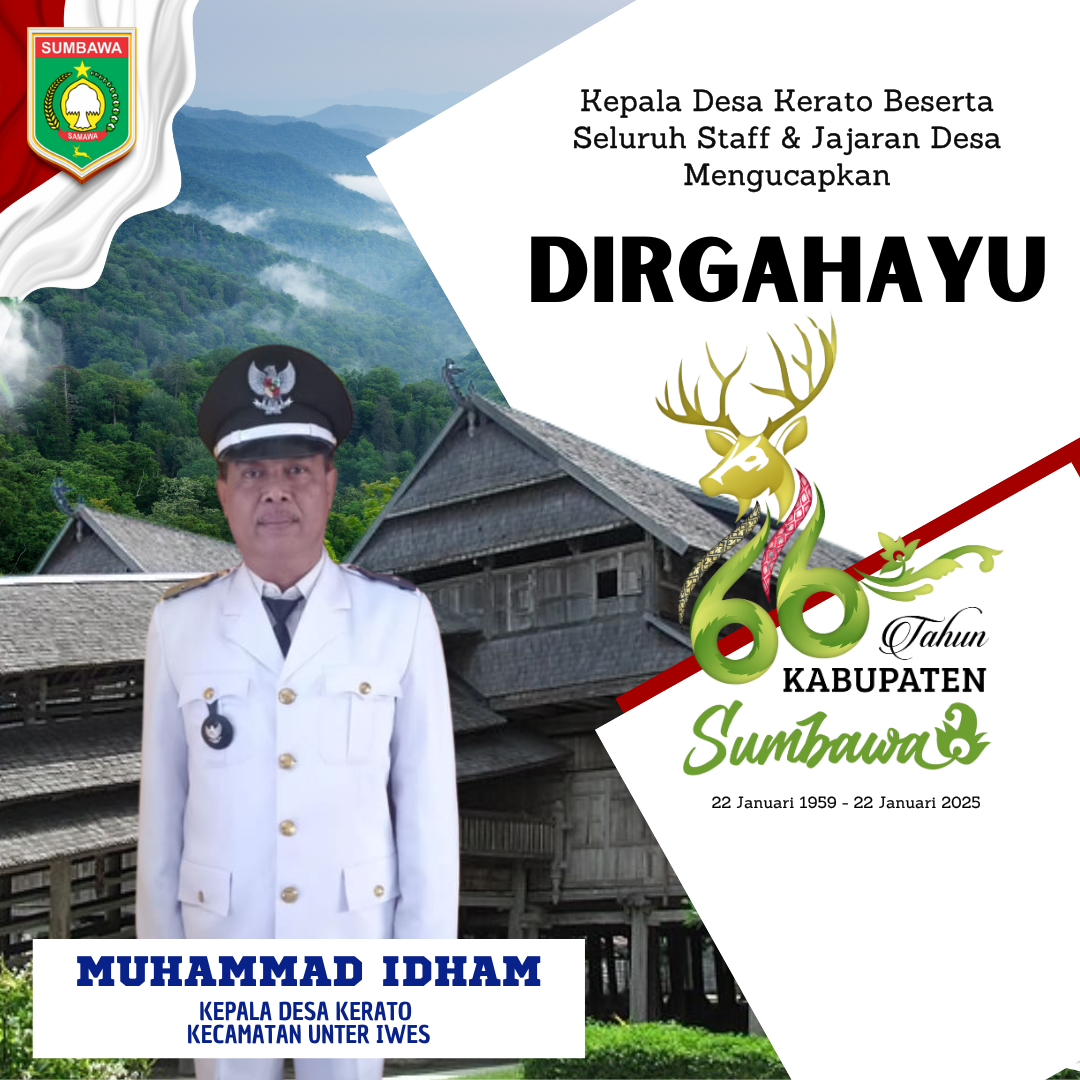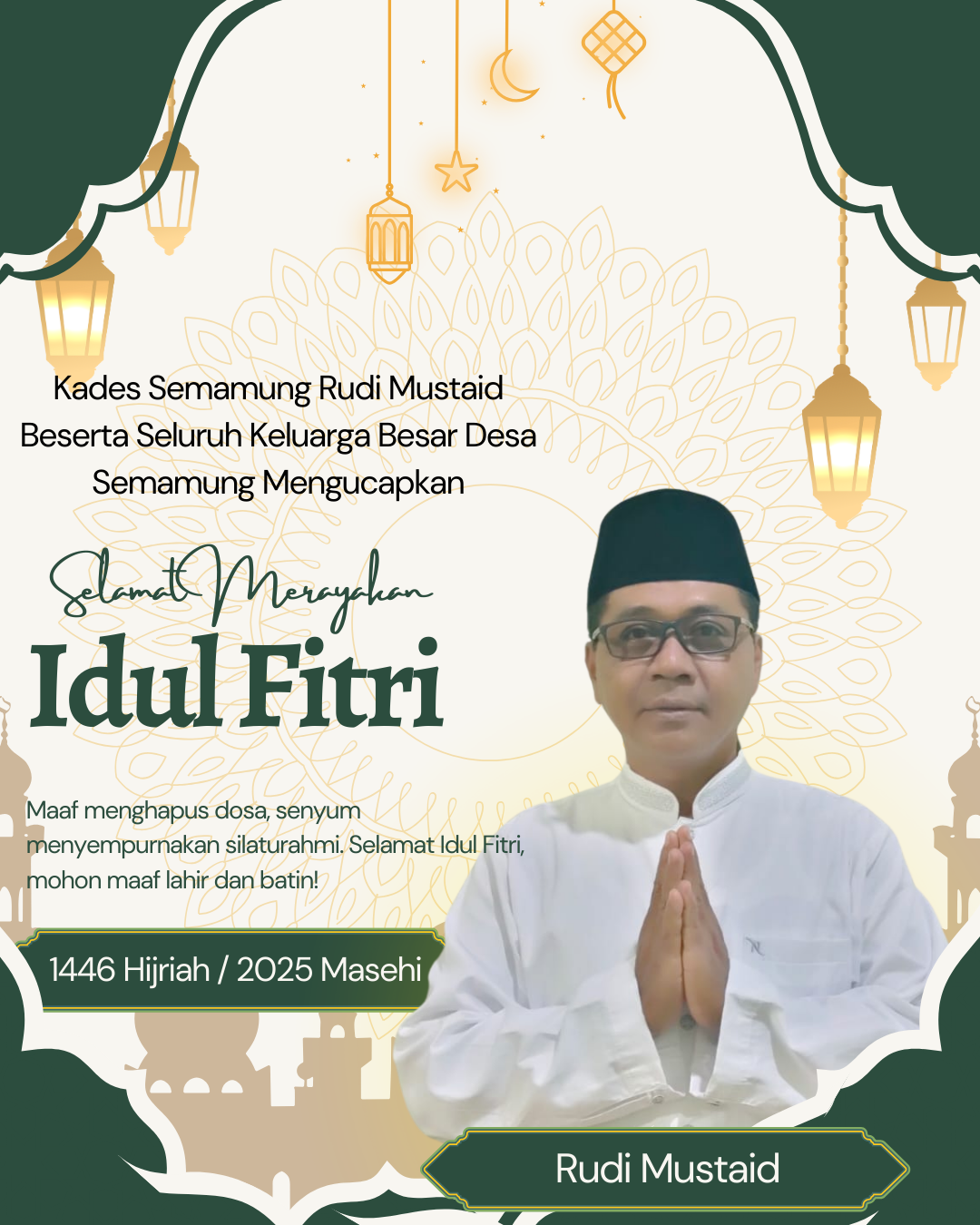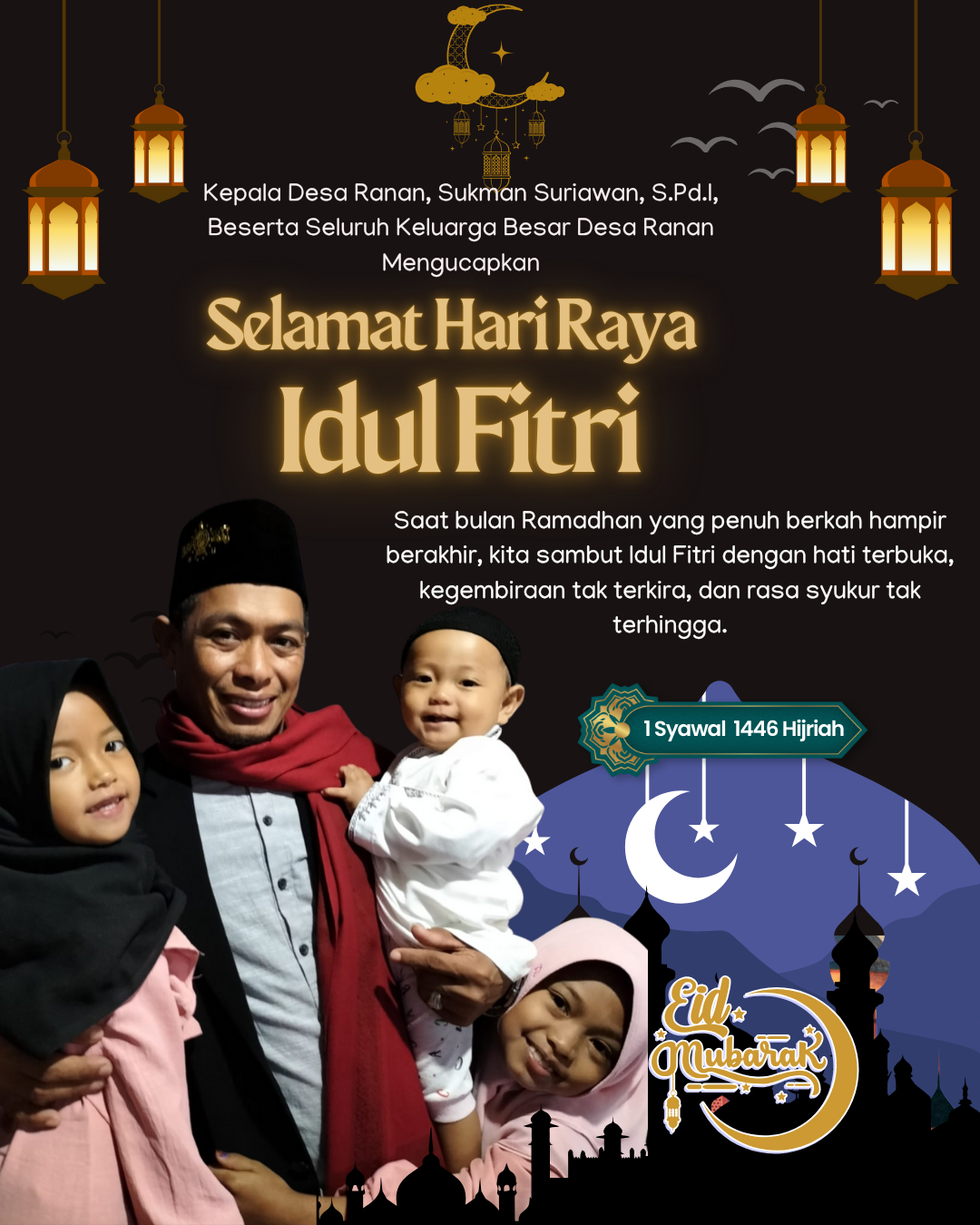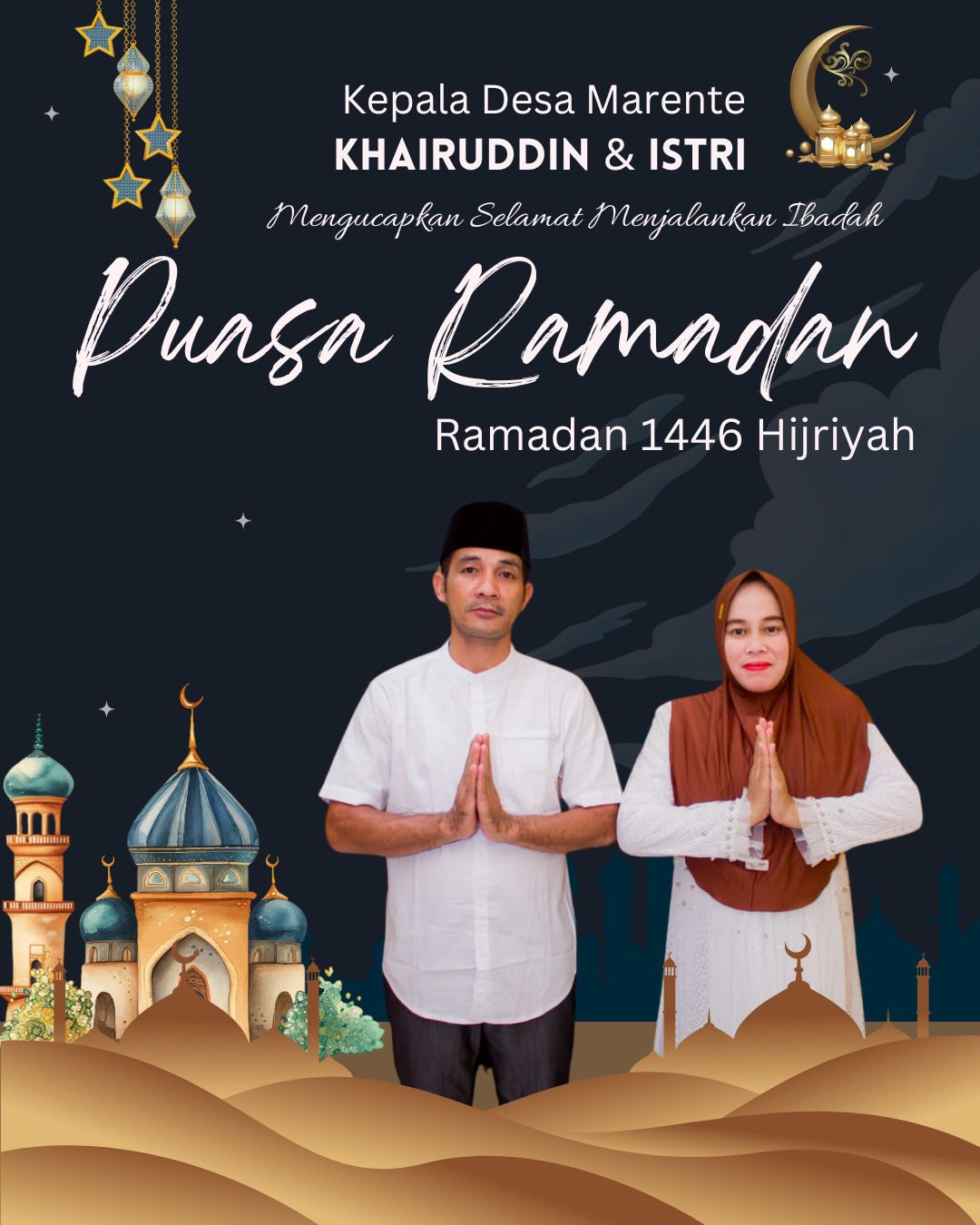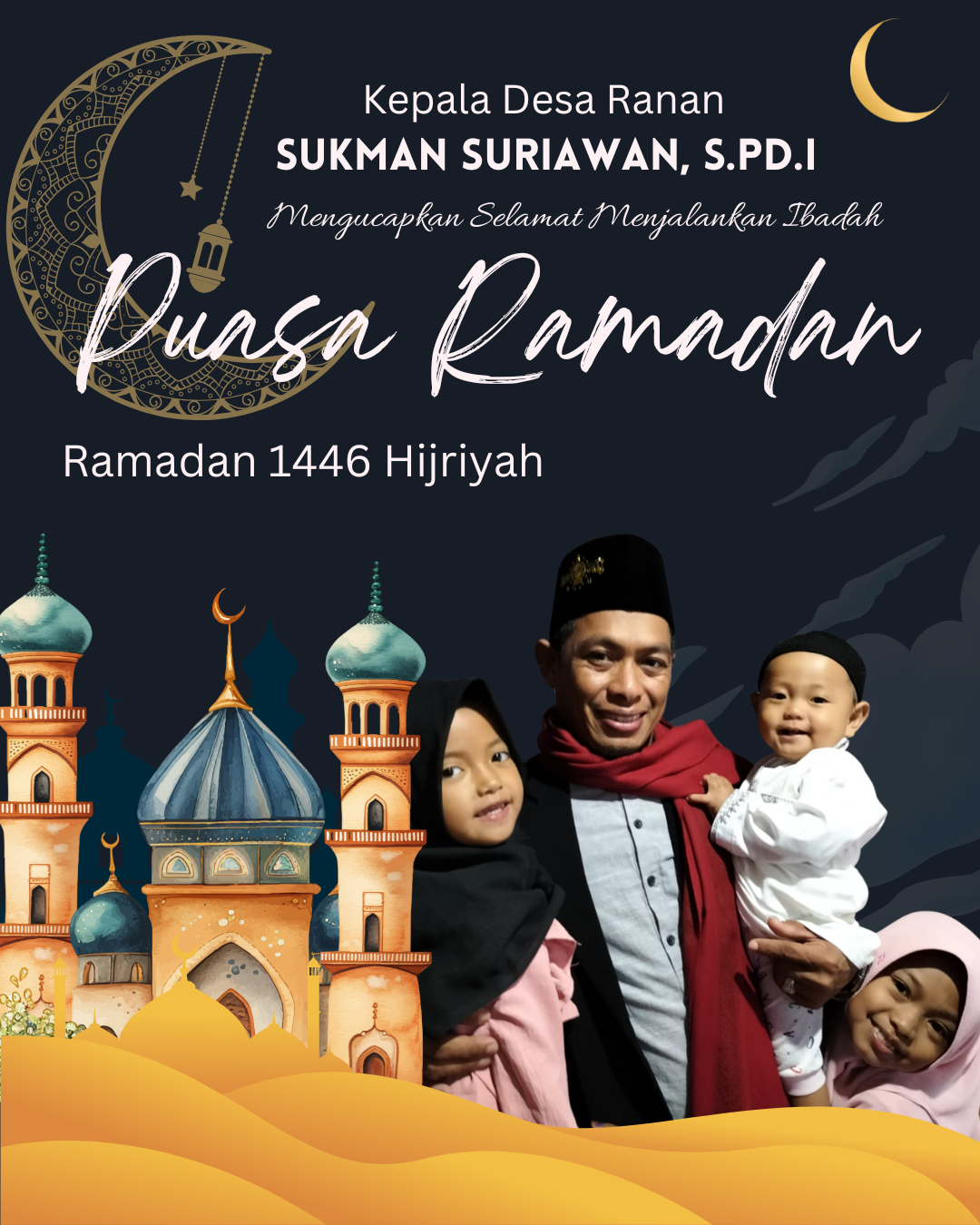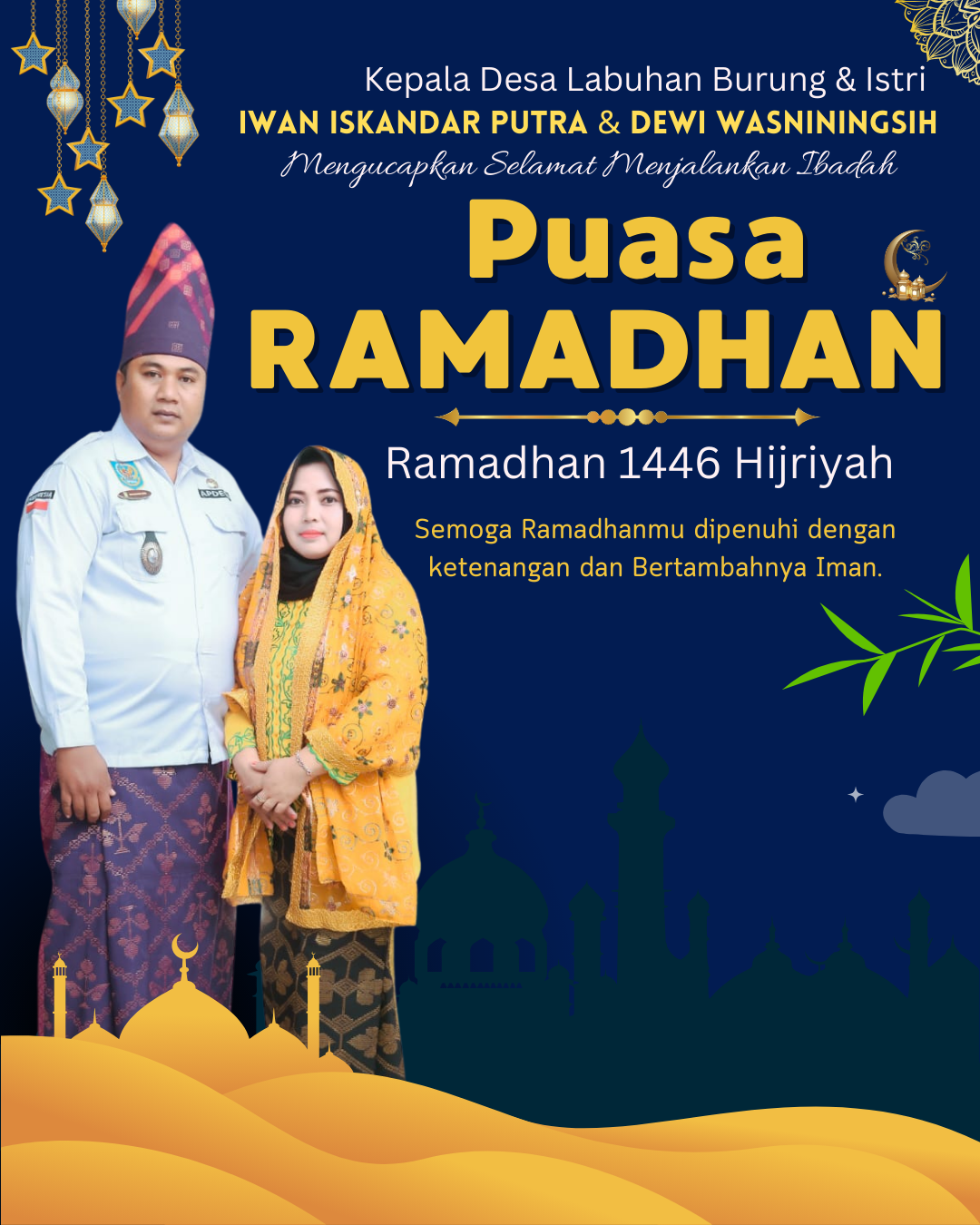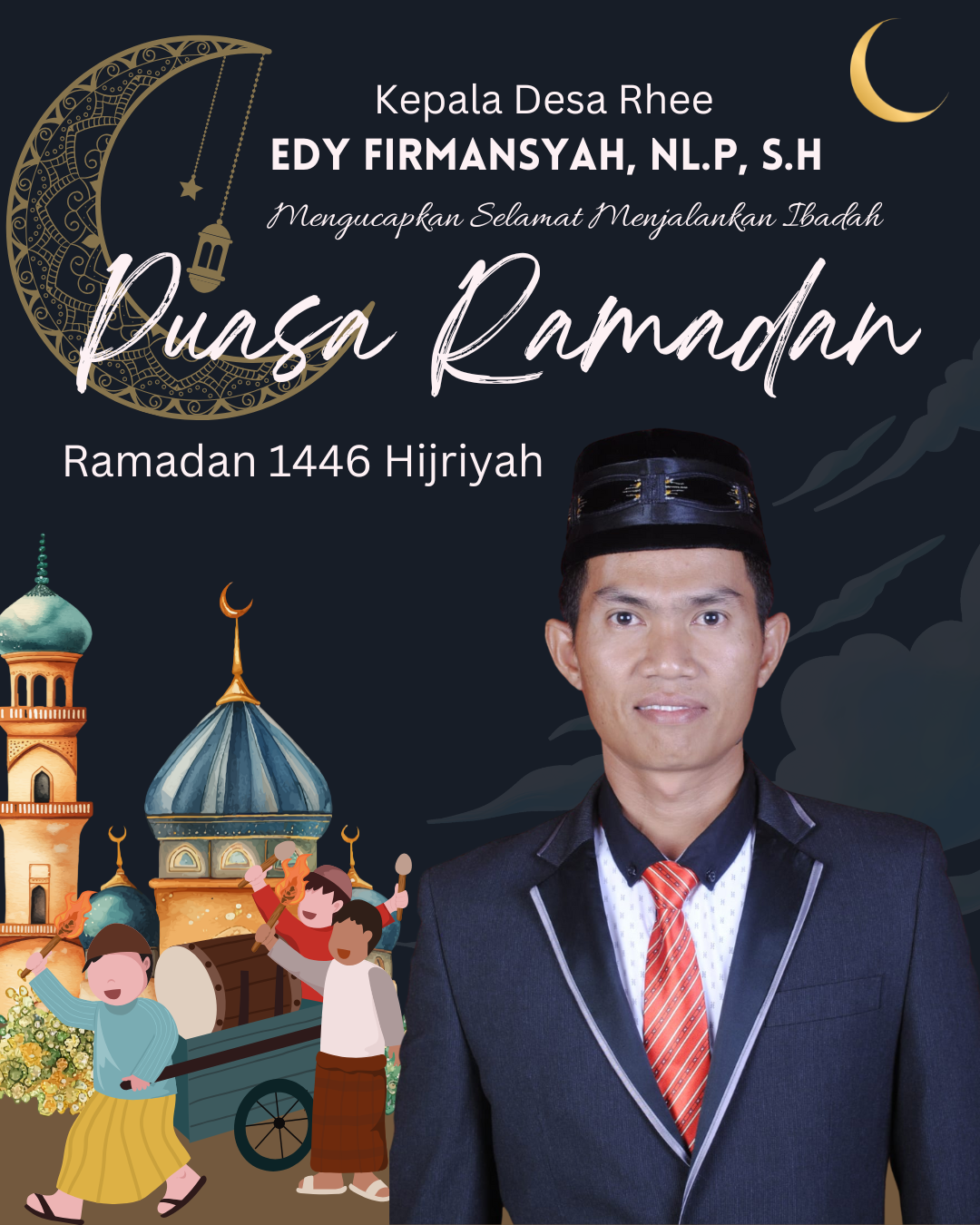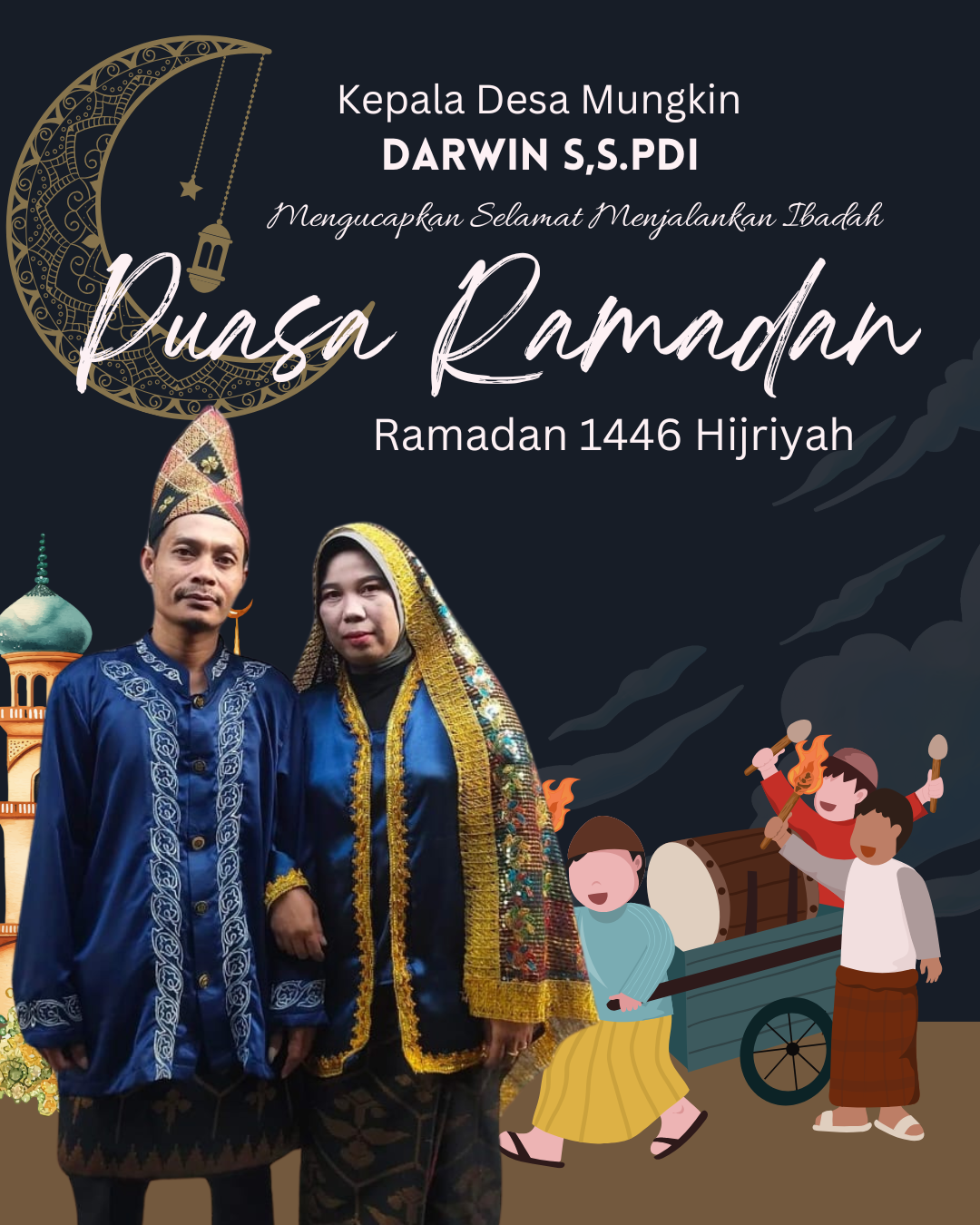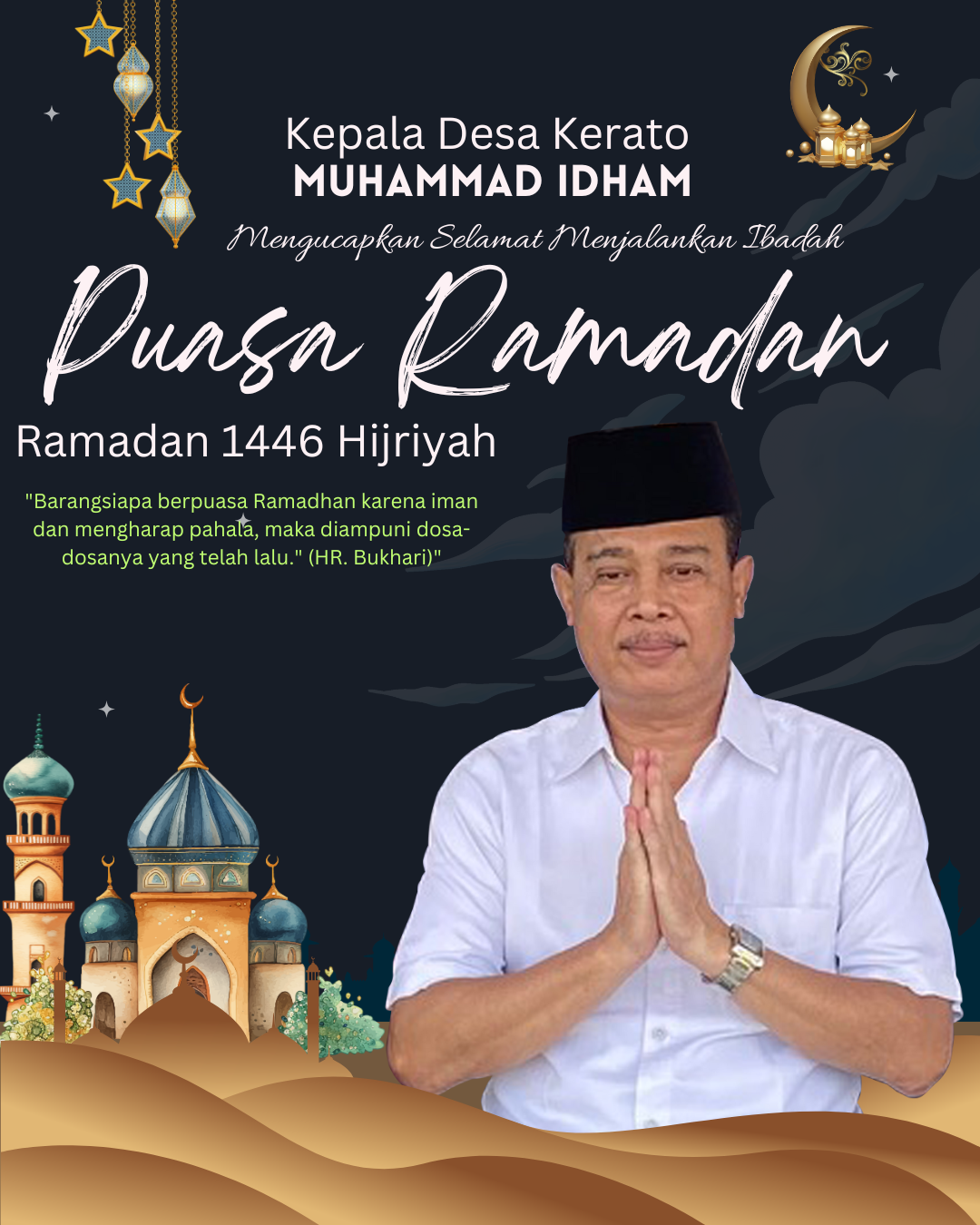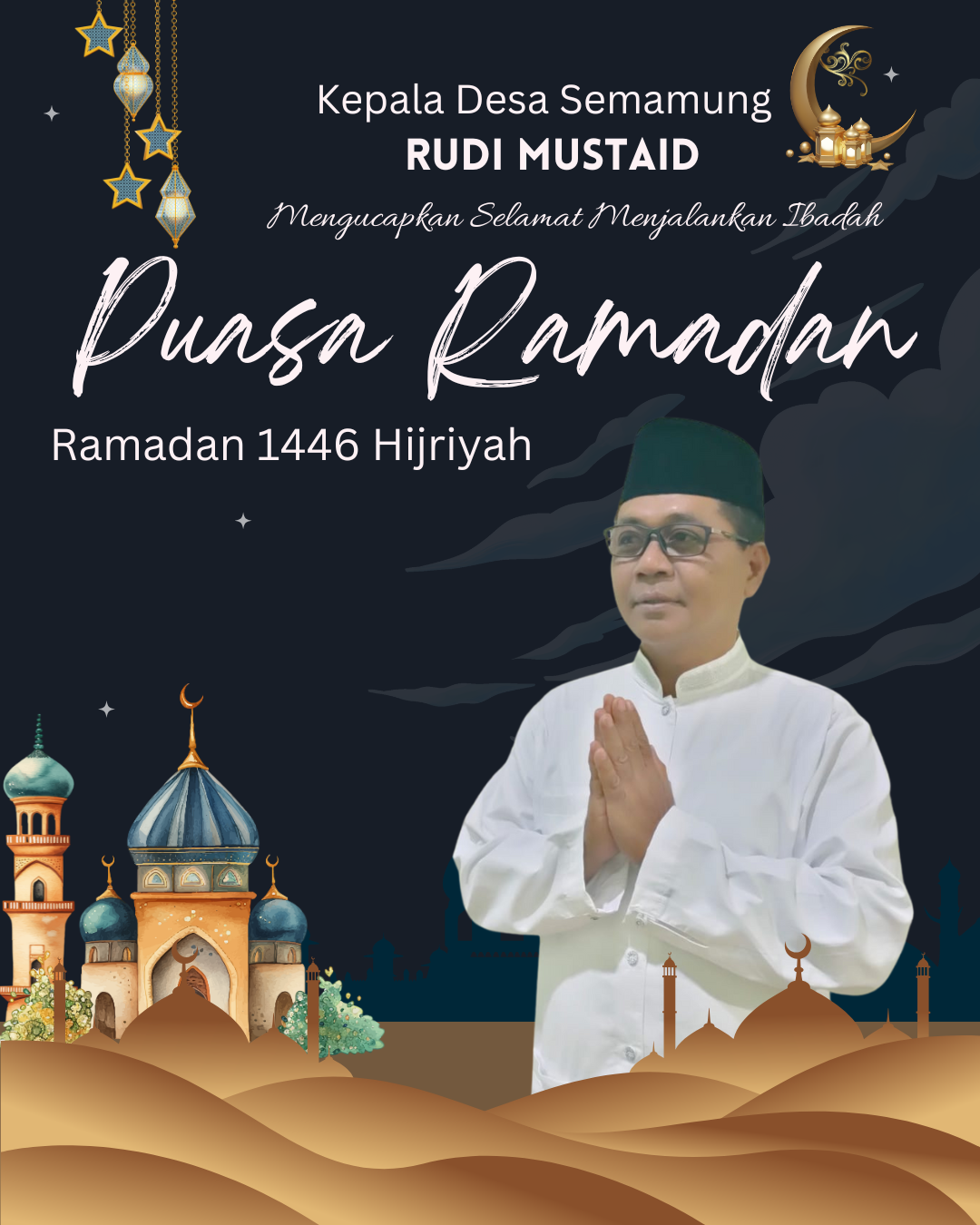Oleh: Egy Permana (Kader Gerakan Pemuda Ansor Sumbawa)
“Aku akan menciptakan dunia baru!”
Itu bukan kutipan Bung Karno, melainkan pekik semangat Monkey D. Luffy, tokoh utama dari anime One Piece. Ucapan ini menggema di ruang-ruang virtual, di mural-mural jalanan, bahkan kini dikibarkan dalam bentuk bendera bajak laut Jolly Roger di berbagai tempat di Indonesia menjelang Hari Kemerdekaan. Fenomena ini mencuri perhatian, bukan hanya karena unik atau “viral”, tetapi karena ia menggugat secara diam-diam: apa arti nasionalisme hari ini?
Setiap Agustus, Merah Putih berkibar megah di berbagai sudut negeri. Tapi tahun ini, sebuah ironi menggoda ruang publik: bendera bajak laut One Piece, Jolly Roger, berkibar di jalanan, mural, hingga atap rumah-rumah anak muda menjelang perayaan kemerdekaan.
Sebagian orang menertawakannya. Sebagian mengecam. Tapi sebagian lain—terutama generasi muda—menyambutnya dengan penuh bangga. Dalam keheningan, mereka mengibarkan bendera dunia fiksi, seolah hendak berkata: “Ini dunia yang aku percaya.”
Apakah ini bentuk penghinaan terhadap simbol negara? Atau justru alarm senyap dari generasi yang kehilangan koneksi terhadap narasi kebangsaan?
Mengapa bendera fiksi lebih menggugah rasa bangga daripada Sang Merah Putih? Apakah ini sekadar kegandrungan remaja pada budaya Jepang (otaku culture), atau ada sesuatu yang lebih dalam sedang bergerak di lapisan bawah kesadaran kolektif bangsa?
Simbol yang Kehilangan Getarannya
Bagi generasi 1945, Merah Putih bukan sekadar simbol, ia adalah gema sejarah, kenangan luka dan harapan. Tapi seiring waktu, simbol ini kehilangan getaran emosionalnya di hadapan generasi digital. Ia menjadi formalitas: dikibarkan tiap upacara, difoto tiap lomba, dicetak di tiap kaus kampanye. Namun jarang ditafsir ulang, jarang dikaitkan dengan pengalaman hidup sehari-hari, apalagi dibincangkan secara reflektif.
Sejak Orde Baru hingga Reformasi, narasi kebangsaan kita stagnan: dikunci dalam buku teks sejarah, dibacakan dalam upacara, tapi jarang menyentuh pengalaman batin dan realitas hidup generasi baru.
Apalagi… anak muda masa kini tidak hidup dalam trauma kolonial. Mereka hidup dalam trauma lain: kesenjangan sosial, ketidakpastian kerja, polarisasi politik, korupsi struktural, dan banalitas kehidupan digital. Dalam dunia yang absurd ini, mereka butuh narasi baru untuk menjelaskan diri mereka—dan di sinilah fiksi mengambil alih ruang kosong itu.
Dunia Fiksi sebagai Tempat Berlindung
One Piece, serial Jepang yang sudah berjalan lebih dari dua dekade, bukan hanya menawarkan cerita petualangan. Ia menawarkan struktur moral alternatif. Di sana, pemerintah dunia digambarkan korup dan manipulatif, aparat negara bersikap brutal, dan para “penjahat”—para bajak laut—justru kerap membela kebenaran, menolong yang lemah, dan memperjuangkan dunia yang lebih baik.
Dalam One Piece, Luffy dan krunya bukan sekadar bajak laut. Mereka simbol perlawanan terhadap kekuasaan represif, pelindung yang lemah, dan pencari kebebasan sejati. Mereka tidak sempurna, tapi penuh nilai: solidaritas, kesetiaan, pengorbanan.
Bagi banyak remaja, dunia ini terasa lebih jujur dibanding dunia nyata. Luffy dan kawan-kawan mungkin bajak laut, tapi mereka memiliki idealisme, keberanian, dan rasa keadilan yang tidak mereka temukan dalam sistem pendidikan formal, tokoh publik, atau partai politik. Dalam dunia fiksi, keberanian menentang kekuasaan menjadi sah, dan impian membangun dunia baru bukan ditertawakan, tapi dirayakan.
Nasionalisme yang Dibentuk Ulang
Kita bisa menganggap ini sebagai ancaman terhadap nasionalisme. Tapi kita juga bisa melihatnya sebagai proses pembentukan ulang. Seperti yang pernah dikatakan Benedict Anderson dalam Imagined Communities, bangsa adalah komunitas yang dibayangkan, dibentuk melalui simbol, narasi, dan perasaan memiliki bersama. Ketika simbol-simbol lama tak lagi menyentuh, komunitas akan mencari simbol baru.
Proses ini bukan berarti pengkhianatan terhadap negara, tapi kritik terhadap negara yang dirasa gagal menjadi rumah imajinatif bagi warganya. Kritik yang tidak disampaikan lewat orasi politik atau esai panjang, tapi lewat gestur simbolik: mengibarkan bendera dunia fiksi di tiang yang biasanya dikhususkan untuk bendera negara.
Gus Dur dan Nasionalisme Bebas
Mari kita tilik kembali pemikiran tokoh besar K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai guru bangsa. Dalam suatu tulisannya, Gus Dur menulis:
“Nasionalisme kita ini harus bersifat inklusif. Kalau tidak, ia akan mati dengan sendirinya.”
Dalam konteks ini, pemikiran Gus Dur tentang kebangsaan terasa sangat relevan. Gus Dur pernah berkata, “Kita ini belum selesai menjadi bangsa.” Bagi beliau, nasionalisme bukan hanya urusan simbol, tapi tentang keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan pada mereka yang termarjinalkan.
Gus Dur menolak nasionalisme yang sempit dan eksklusif. Dalam banyak tulisannya, ia membela nasionalisme yang lentur: yang mampu menampung perbedaan, mengakomodasi keresahan, dan membuka ruang dialog dengan zaman. “Kalau kita mencintai Indonesia, kita harus berani mengkritiknya,” tulisnya suatu ketika.
Apa yang dilakukan anak muda hari ini, lewat simbol-simbol seperti One Piece, bisa dibaca sebagai bentuk nasionalisme yang sedang mencari bentuk baru. Nasionalisme yang tidak puas dengan simbol, tapi menuntut makna. Nasionalisme yang tidak bisa lagi dipaksa melalui upacara, tapi perlu dihidupkan lewat pengalaman hidup, kisah, dan harapan.
Ketika Negara Tak Lagi Romantis
Generasi muda butuh alasan untuk mencintai negaranya. Tapi cinta, sebagaimana dalam relasi apa pun, tidak bisa dipaksakan lewat slogan. Ia harus tumbuh dari pengalaman: pengalaman dilindungi, didengar, dihargai, dan diberi ruang untuk bermimpi.
Jika hari ini mereka memilih Luffy ketimbang tokoh nasional, barangkali karena Luffy memberi mereka harapan tentang keadilan, persahabatan, dan perjuangan yang tidak palsu. Mereka tidak menolak nasionalisme, mereka menolak nasionalisme yang terasa kosong, normatif, dan tidak relevan.
Merah Putih Harus Dihidupkan Kembali
Hari ini, mungkin kita perlu lebih banyak bertanya daripada menghakimi. Mengapa simbol-simbol negara kehilangan daya magisnya? Apa yang tidak kita berikan kepada anak-anak bangsa ini, sehingga mereka mencari rumah di dunia imajinatif?
Bendera Merah Putih adalah simbol sakral, tapi sakralitasnya harus terus dirawat—bukan dipaksakan. Ketika pendidikan sejarah menjadi hafalan, ketika tokoh nasional dibingkai sebagai dewa yang tak tersentuh, dan ketika pengorbanan dijadikan materi ujian—maka kita kehilangan kisah.
Nasionalisme tidak boleh berhenti pada tanggal 17 Agustus, tidak boleh berhenti pada bendera dan lagu. Ia harus lahir kembali dalam bentuk yang bisa dirasakan, dibayangkan, dan diperjuangkan. Seperti kata Gus Dur, “Bangsa ini akan tetap berdiri, selama rakyatnya tidak kehilangan harapan.”
Dan jika saat ini harapan itu hinggap di dunia fiksi, tugas kitalah—kaum pendidik, budayawan, dan pemimpin—untuk merebut kembali ruang imajinasi itu. Bukan dengan melarang atau mengejek simbol-simbol alternatif, tapi dengan memberi makna baru pada yang lama.
Karena Merah Putih tidak boleh kalah dari bendera bajak laut. Tapi untuk itu, ia harus kembali menjadi lambang dunia yang layak diperjuangkan.